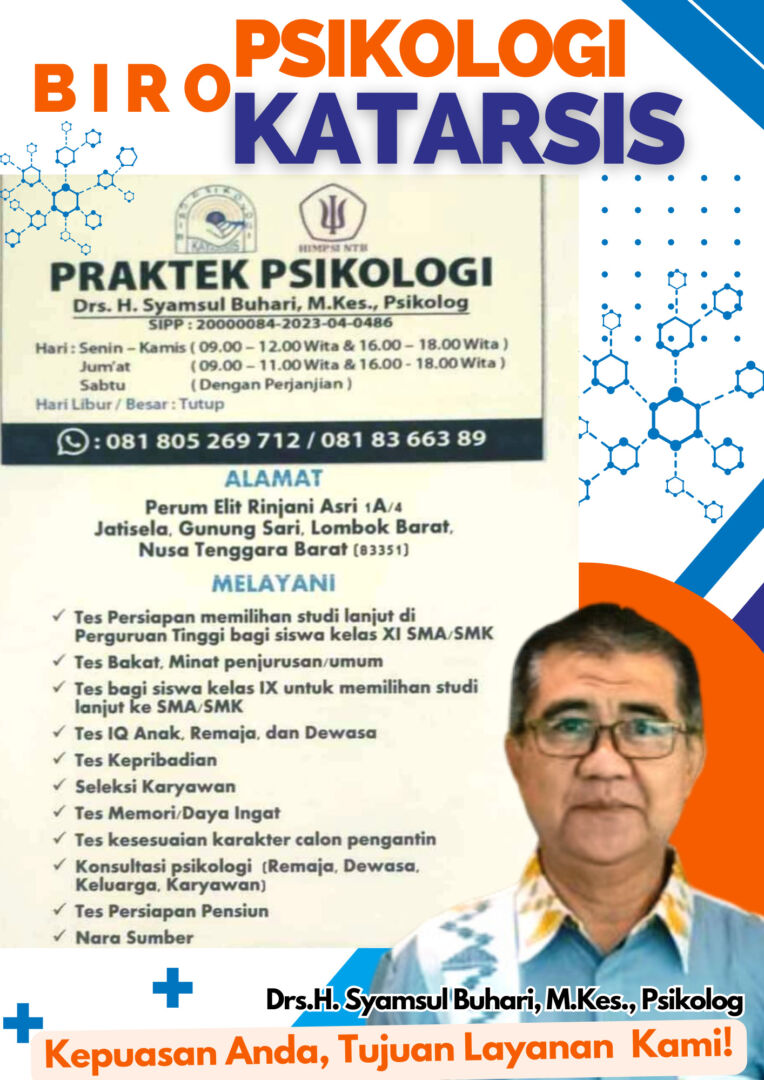Andai saja WRS lebih dari sehari berada di Lombok, catatannya tentang pulau ini, setidaknya kondisi Kota Ampenan, Mataram, dan Cakranegara di tahun 1924, lebih lengkap dan akurat. Sayang ia hanya beberapa jam saja punya kesempatan ngelamang (keluyuran, bahasa Sasak) di pulau ini. Itu pun tanpa ada rencana. Tujuannya ke Pulau Jawa, bukan Lombok.
Sama ceritanya dengan naturalis Alfred Russel Wallace di tahun 1856. Dari Singapura sebenarnya ia hendak ke Celebes. Tapi rute perjalanan mengharuskan ia mesti transit di Ampenan, menunggu beberapa bulan kapal yang membawanya ke Makassar. Untunglah ia mendapat anugerah paling berharga dari seluruh rangkaian perjalanan risetnya selama delapan tahun mengembara di Nusantara. Tanpa ke Lombok, takkan lahir garis imajinernya, garis Wallace yang kesohor itu.

Lombok, selama lebih dari setengah abad pasca perang 1894, minim data. Apakah lantaran tak memiliki penulis — selain para penutur lisan?


Sebenarnya, Ampenan punya penulis hebat, bahkan eksis jauh sebelum negeri ini merdeka. Sama dengan WRS, ia juga tergabung sebagai anggota redaksi Pemberita Makassar. Boleh dibilang ia jurnalis angkatan pertama dari Lombok.
Namanya Soe Hong Hie. Sayang tak ditemukan tulisan-tulisannya tentang daerah kelahirannya. Beberapa artikelnya yang terbit di tahun 1932 banyak dikutip dalam penulisan buku sejarah tentang kedatangan orang-orang Tionghoa di Nusantara.
Kita kembali pada WRS dan kawan-kawannya yang kembesuhan (kekenyangan) setelah menyantap sup ayam di sebuah pasar di bilangan Mataram.
Sehabis makan mereka melanjutkan perjalanan. Mereka membelok ke arah selatan, melintasi hutan yang cukup luas. Rimba tua, karena banyak pohon raksasa yang tumbuh tak teratur. Beberapa diantaranya nampak mengering.
Di sekitar hutan juga ditemukan pecahan-pecahan batu dan banyak kuburan, menandakan di tempat itu pernah ada peradaban. Selama satu jam mengamat-amati, ketiganya tak berjumpa dengan seorang pun manusia. Ke luar kawasan itu, mereka kembali melihat hamparan sawah sejauh mata memandang, yang berdekatan dengan pemukiman orang-orang Hindu.
Jam setengah satu mereka sampai di depan kediaman controleur di Mataram. Bangunannya kecil dengan pekarangan tak seberapa luas namun bersih. Di sana terlihat beberapa ambtenaar dan orang partikelir. Di sekitarnya berdiri beberapa toko milik orang Cina. “Jalan di situ hanya bercabang dua. Terlihat banyak anak bertelanjangan,” jelas WRS, dan menyebutkan di sekitar rumah controleur juga berdiri sebuah Sekolah Melayu dan sebuah lagi volkschool, sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak pribumi dengan masa belajar tiga tahun.
Seperempat jam perjalanan, mereka melihat bangunan-bangun tua yang sebagiannya rusak. “Di sini saya melihat bekas benteng Cakranegara,” ungkapnya.
Di Cakranegara, tulisnya, penduduknya juga sangat banyak. Ia juga mengamati lingkungan yang berada di belakang benteng. Terdapat banyak pohon beringin besar. Rumah-rumah di situ masih utuh terpelihara, juga beberapa kuil. Hampir semua bangunan berukuran luas dan sangat artistik.
“Barang siapa yang mempelajari sejarah Cakranegara tentu akan memuji dan dapat mengira-ngira bagaimana besar kota itu pada zaman dulu. Bekas-bekas kota yang saya lihat sampai ke dalam kampung-kampung,” sebutnya.
Mereka juga menyempatkan diri mengunjungi pasar Cakranegara. Tak beda dengan di Pulau Celebes, pasar di sini juga menjajakan bermacam benda hasil kerajinan tangan. Ada baliyung (semacam kapak) dan benda-benda dari bahan rotan. Dijual mulai dari 10 hingga 50 sen. Hasil-hasil kerajinan yang nampak halus dan apik.
Khawatir hujan akan turun, mereka kembali ke Ampenan menjelang senja. Ketiganya mengayuh sepeda dengan hati riang, sambil makan buah rompis (kemungkinan rambutan, tidak ada ditemukan nama buah ini di search engine).
Sekitar jam 5 sore mereka tiba di Kampung Cina di Ampenan. WRS membayar f 1,50 untuk sewa tiga sepeda yang dipakai selama lima jam. Sebelum kembali ke kapal mereka membeli makanan dan buah-buahan untuk dinikmati di perjalanan.
Benar cerita yang didengarnya di warung es pagi tadi. Tukang perahu yang mengantar kembali ke kapal terus-terusan berteriak, mengulang kata-kata kasar yang hampir sama. “Belot dengan-dengan puteq tie!” teriaknya disambut seruan yang sama para tukang sampan lain.
WRS tak banyak menulis tentang Ampenan. Tetapi, ada yang lebih penting daripada sekadar cerita tentang keasyikan perjalanan tamasya. Ada dendam kolektif yang mesti ia sampaikan ke publik. Dendam orang-orang Ampenan yang jika diterjemahkan adalah sikap antipati menentang penindasan yang telah lama berlangsung. Sama seperti kemuakan suku bangsa lain di Hindia yang terjajah kolonialisme berabad-abad. Dendam dan kesadaran sebagai kaum yang terbelenggu, akhirnya terepresentasi dalam ikrar bersama yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, empat tahun kemudian. (Buyung Sutan Muhlis)