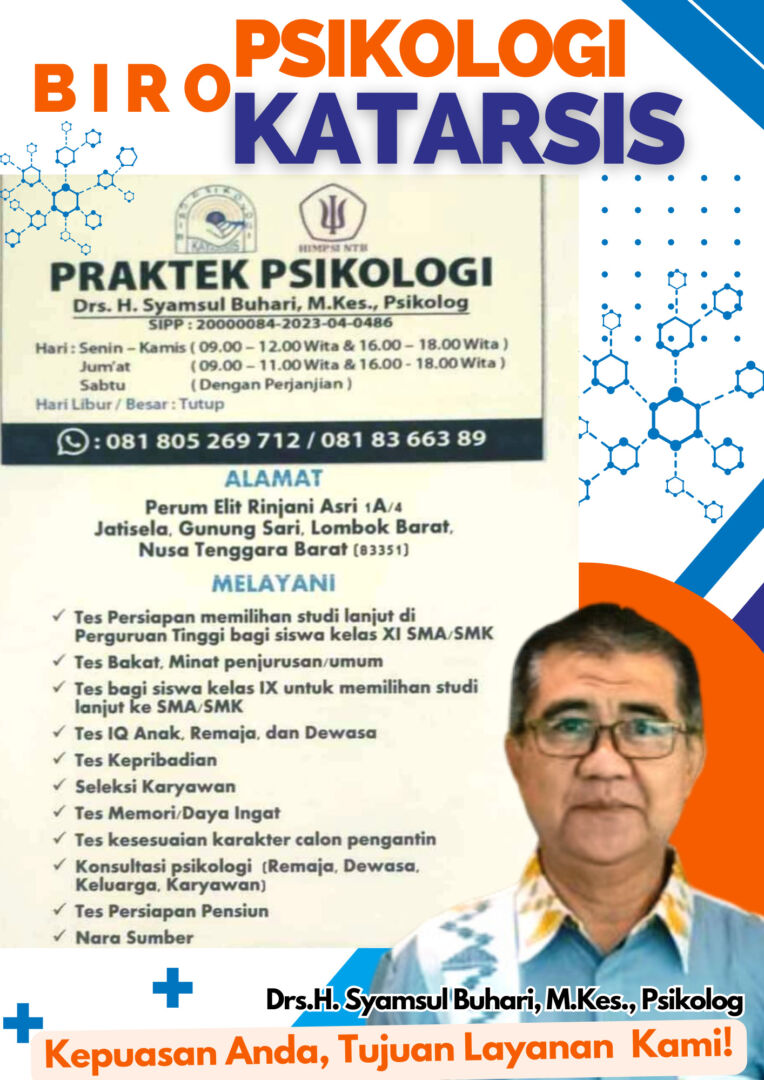Kurang satu mil dari dermaga Ampenan, awak-awak sebuah kapal uap melepas jangkar. Badan raksasa Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM) Barentsz tak memungkinkan lebih mendekat ke arah daratan, mengingat perairan teluk yang tergolong dangkal.
Awal tahun 1924, langit Ampenan cukup cerah. Matahari baru merangkak sepenggalah.
KPM Barentsz sudah dua hari tiga malam bertolak dari Pelabuhan Makassar, hendak menuju Pulau Jawa, berakhir di Singapura. Kapal ini singgah di Ampenan untuk mengangkut ternak sapi dan babi.



Baru saja berhenti, kapal dikepung puluhan sampan. Terdengar riuh teriakan para pengemudinya yang menawarkan jasa mengantar penumpang atau barang ke darat. Sebagian lainnya melompat ke atas kapal, membawa barang-barang jualan, berupa makanan dan buah-buahan. Praktis, geladak kapal berubah menjadi pasar.
Harga-harga yang ditawarkan sangat murah. Para penumpang yang datang dari Makassar itu terheran-heran, ketika mereka menyadari perbandingan harga yang cukup jauh dengan di tempat asal. Satu sisir pisang susu hanya 5 sampai 10 sen. Jeruk bali 10 sen. Satu buah nenas cuma 8 sen.
Kapal akan berangkat 12 jam lagi. Waktu yang cukup panjang ini dimanfaatkan sejumlah penumpang untuk pelesiran di daratan Ampenan. Salah seorang diantaranya lelaki Jawa, penumpang di ruangan kelas empat. Bersama tiga pria lainnya, dua pelajar asal Manado, kenalannya di atas kapal, dan seorang peranakan Cina, ia urunan menyewa sampan seharga f 1 (satu rupiah), pergi dan pulang.
Ia jurnalis Pemberita Makassar, koran berbahasa Melayu yang terbit sejak 1903. Ia menggunakan inisial WRS. Perjalanannya dari Makassar ke Pulau Jawa dan transit di beberapa pelabuhan ditulisnya secara bersambung.
“Kira-kira 10 menit sampailah kami ke darat dan terus ke pasar mengendarai dokar yang letaknya tak jauh dari pelabuhan. Di pasar barulah saya bernafsu makan nasi. Kami bertiga masuk ke sebuah warung nasi sedangkan kawan saya Bangsa Cina itu pergi ke lain tempat,” tulisnya.
Menu warung-warung makan di pasar Ampenan lebih dominan menyediakan lauk daging ayam dan telur, dengan tarif begitu murah.
WRS menduga-duga, murahnya harga-harga mungkin lantaran penduduk di tempat ini sangat sulit mendapatkan uang. Harga empat ekor ayam dewasa yang masih hidup hanya 90 sen. Sebutir telur dijual setengah sen saja. Dan, setelah bertiga makan sekenyang-kenyangnya, tarifnya hanya f 1,35. “Sedangkan kalau di Makassar, tak cukup seringgit (f 2,5),” jelasnya. Ia sempat menimbang-nimbang untuk tinggal di Ampenan saja, tergoda biaya hidup yang serba murah tersebut.
Dari pasar, mereka berjalan menuju kantor pos, mengirim kabar ke para sahabat dan handai-tolan.
Ampenan, demikian WRS, kota yang kecil yang nampak kumuh. Meski kecil, tetapi penduduknya sangat banyak. Hanya ada dua kantor di sini, yaitu kantor pos dan KPM. Kebanyakan bangunan di jalan utama hanya toko-toko milik orang Cina yang menjual barang keperluan sehari-hari.
Dalam banyak hal, penduduk dikendalikan bangsa lain. Mata pencaharian warga setempat kebanyakan menjadi kuli bangsa asing, dengan upah yang sangat minim. “Tapi, meskipun berpenghasilan kecil mereka memerlukan membuat rumah sendiri-sendiri. Karena itu, sangat banyak rumah di situ dan letaknya rapat-rapat sehingga jalan-jalan di kampung terlalu sempit,” paparnya.
Bentuk-bentuk rumah kebanyakan bulat. Dindingnya dari tanah liat. Kebanyakan tak memakai genteng, tapi beratap ijuk. Di pemukiman orang-orang Hindu, meski rumah-rumah yang berdiri tergolong kecil, tapi hampir semua berukir dan memiliki arca.
Kota ini dihuni para pemeluk sejumlah agama. Dua agama yang dominan adalah Islam dan Hindu. “Tapi kami tak bisa membedakan mereka, sebab mereka berpakaian yang sama saja,” lanjutnya.
Lelaki itu bertanya-tanya, meskipun di Ampenan cukup banyak pemeluk Hindu, tetapi ia tak melihat satu pun orang Bombay (India — yang notabene asal Hindu). Tokonya juga tak ada. Begitu juga dengan pendatang dari Jawa, ia hanya bertemu dengan satu-dua orang saja. Berbeda dengan komunitas Banjarmasin. Di Ampenan, pendatang dari Borneo ini bahkan membentuk perkampungan yang cukup padat.
Setelah satu jam keluar-masuk kampung, sang jurnalis dan teman-temannya kelelahan. Mereka memasuki kedai yang menjual es. Pemiliknya seorang pendatang asal Banjarmasin.
Kesimpulannya tentang harga-harga yang serba murah di Ampenan seketika buyar. Di kedai itu, harga segelas es cendol ternyata sangat mahal. Ia membayar per gelasnya 10 sen, sama dengan harga dua sisir pisang susu di atas kapal. Belakangan ia baru tahu, di Lombok saat itu belum ada pabrik es. Wajar mahal, karena es didatangkan dari Pulau Bali. Begitu sampai, balok-balok es lebih banyak mencair, meskipun telah diselubungi selimut wol tebal rapat-rapat. Apalagi di masa itu siapa yang mengenal freezer? Kulkas saja baru muncul di negeri ini lebih dari seperempat abad kemudian. (Buyung Sutan Muhlis/bersambung)