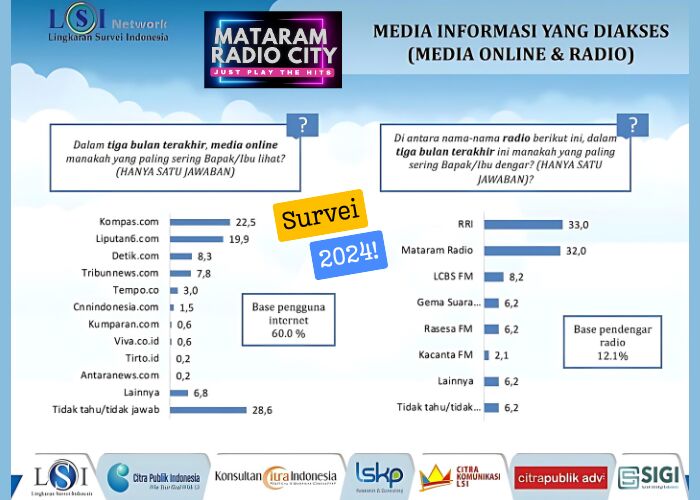Perang adalah bapak dari semua hal, kata Heraklaitus sekian ribu tahun yang lalu. Kini apa yang akan lahir dari perang Ukraina?
Ingatan akan dibayangi kekerasan; trauma akan berlapis-lapis. Senjata akan kian penting dalam kehidupan politik internasional. Aliansi militer seperti NATO akan tambah dianggap diperlukan, terutama oleh negeri Eropa yang kecil-kecil. Perdamaian akan semakin dijaga dengan kesediaan berperang. Kewaspadaan akan berarti paranoia.

Apapun niat Putin mengirimkan pasukan besar menyerbu Ukraina, dan apapun hasilnya, itulah yang akan dia dapat — dan itulah yang akan berdampak di dunia. “Old violence is not too old to beget new values,” tulis Penyair Robinson Jeffers dalam salah satu sajaknya yang muram.


Dalam sebuah diskusi di YouTube, Yael Noah Harari punya prediksi yang lebih gelap: serbuan Putin ke Ukraina akan bisa jadi pola baru dalam tatanan internasional. “Kita kembali ke rimba raya”, katanya.
Harari menguraikan perubahan yang akan terjadi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, katanya, banyak perang berkobar dengan korban besar, tapi apa yang dilakukan Putin di Ukraina berbeda. Dalam perang Putin di Ukraina, satu negara menyerbu masuk ke sebuah negara lain untuk menghapusnya dari peta bumi. Ini akan jadi sesuatu yang dianggap normal, jika Putin dibiarkan menang, seperti ketika ia mengambil-alih Krimea di tahun 2014. Pola itu bisa menular. Akan rusak keadaan dalam tatanan dunia sebelumnya. Tak ada lagi sebuah world order yang dirawat bersama. Meskipun masa itu bukan masa yang adil dan damai, dunia tak pernah mengalami guncangan, bahkan destruksi, seperti kali ini.
Tentu saja Harari — meskipun kini dianggap begawan bijak yang bisa menjelaskan pelbagai persoalan dunia — kurang saksama. Invasi Putin ke Ukraina bukan guncangan yang luar biasa. Awal Agustus 1990, Presiden Saddam Hussein memerintahkan pasukannya menyerbu Kuwait; Iraq menganggap Kuwait semacam umbai cacing wilayah kekuasaan Baghdad. Tak berdaya melawan, raja dan para pemimpin Kuwait melarikan diri. Saddam Hussein pun mengangkat orangnya sebagai pengganti mereka, seraya memaklumkan negeri Teluk yang kecil itu sebagai “propinsi ke-19 Irak”.
Tapi Saddam tak bisa meyakinkan dunia. PBB mengecam invasi Irak. Meskipun sebelumnya lunak bersikap terhadap Baghdad, AS mengerahkan tentaranya, bersama negeri-negeri lain. Perlawanan di bawah tanah rakyat Kuwait gampang dibasmi dengan bengis oleh Saddam, tapi serbuan pasukan Desert Storm Amerika tak bisa ditahan. Saddam tak punya banyak teman; bahkan Rusia dan RRT mengembargo penjualan senjata.
Tampak, dunia ingin merawat bersama sebuah tatanan, “World Order”, yang mengharamkan invasi ala Saddam. Semacam ketertiban pun menyusul. Tapi tak lama. Pada 2003 perusaknya Amerika di bawah Presiden George W. Bush dan Inggris di bawah Pedana Menteri Blair. Tanpa ada provokasi, pasukan AS dan Inggris menyerbu Irak. Sejak itu, selama 20 tahun, Timur Tengah remuk redam. Ribuan manusia tewas dalam pelbagai jenis kebencian.
Tampaknya untuk tak kembali ke
“rimba raya” — di mana yang kuat, tanpa apologi, bisa menghabisi yang lemah — diperlukan narasi yang dibangun bukan dari rimba-raya: suatu narasi yang mengandung nilai universal. Kita bisa melihat keperluan akan dalih ini ketika Putin mengumumkan akan menghabisi kesewenang-wenangan ‘Nazi’ di Ukraina. Bahkan Saddam menyatakan alasan yang ingin sah: ia hendak mengembalikan Kuwait ke pangkuan Irak, induknya yang “asli”. Dan kita ingat: Bush dan Blair memaklumkan tujuan agresi mereka hendak melucuti Saddam agar Irak tak bisa memakai senjata pemusnah massal.
Kita tahu semua alasan itu bohong. Tapi bahwa narasi itu dijadikan dalih sebuah tindakan agar tak dihujat, menunjukkan perlunya apa yang universal di dasar argumen peperangan yang paling jahanam.
Problemnya, telah lama disangsikan adanya nilai universal yang bukan hanya topeng sang pemegang hegemoni. Kita seakan hidup dengan praduga bahwa manusia, (yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan bagus sebagai “sesama”), tak punya nilai yang bisa diterima siapa saja, kapan saja, di mana saja. Kita hidup dengan xenofobia yang menganggap apa yang “asing” akan tetap asing, atau politik identitas yang menganggap “jati diri” sakral dan tak boleh cemar. Kita mendengar Pak Ustad mewejang Muslim harus berbeda dalam hampir semua hal dari non-Muslim. Para ideolog Leninis menetapkan keindahan proletar mesti berbeda dari keindahan borjuis. Kaum feminis militan menentukan, kaum laki-laki tak akan bisa merasakan kepedihan seorang perempuan.
Mengamati itu semua, sejarawan Marxis terkenal, Eric Hobsbawn, dengan masygul mengatakan: « What holds humanity together today is the denial of what the human race has in common. » Kini manusia seakan-akan bersepakat menolak adanya yang sama di antara sesama.
Dari sini tampak, krisis tatanan dunia punya sebab yang lebih serius ketimbang hanya kekusutan hubungan internasional. Apalagi tak bisa segera ada mufakat, siapa, dan kekuasaan mana, yang sanggup menjaga berlakunya apa yang “baik” secara universal. PBB memberi harapan di sana-sini, tapi lembaga ini tak bisa mencegah, apalagi menghukum, seorang Saddam, sepasang Bush-Blair, seorang Putin.
John Lennon bermimpi, « Imagine there is no country », dan kita senang membayangkan hidup di dunia tanpa sekat tanpa permusuhan. Tapi imajinasi itu tak punya daya…
Jangan-jangan nilai yang universal hanya bisa ditegakkan, biarpun tak lengkap, dengan darah dan besi oleh mereka yang melawan “sang angkara murka” seperti dalam perang Ukraina. Jika benar demikian, yang universal akan kembali diakui dalam percaturan politik dunia, dan manusia akan bisa pulih jadi sesama. Dalam keadaan itu, problem besar yang akan dihadapi sesama di muka bumi — misalnya perubahan iklim — tak akan dihadapi sebagai nasib malang, yang (untuk memakai kalimat Chairil Anwar) merupakan “kesunyian masing-masing”.
Goenawan Mohamad, Tokoh Pers Indonesia