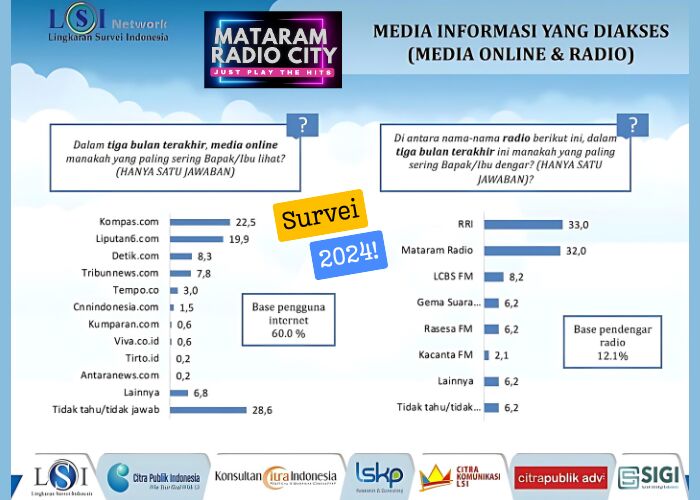Setiap menguliti burung-burung yang akan diawetkan, Manuel Fernandez, asal Portugis, selalu dikelilingi para pendatang Melayu dan Sasak. Orang-orang terheran-heran melihat aktivitas itu. Tapi yang bikin Fernandez disukai penduduk, karena ia sering bekerja sambil bicara, seperti berkhotbah.

“Allah telah menunjukkan kemurahan hati-Nya hari ini, dan telah memberi kita beberapa burung bagus. Kita tak dapat berbuat apa pun tanpa-Nya,” ujarnya.
Seorang Melayu lainnya menimpali, “Sebenarnya, burung pun seperti manusia, umurnya telah ditentukan. Bila ajalnya tiba, tak ada yang dapat menolong mereka. Akan tetapi, bila belum waktunya, kau tidak akan bisa membunuhnya.”


“Butul! butul (tertulis demikian, maksudnya betul! betul)!” sahut hampir seluruh warga.
Fernandez asisten naturalis Alfred Russel Wallace yang pandai berbahasa Melayu. Pembantu lainnya pribumi Melayu bernama Ali.
Sejak 17 Juni hingga 29 Agustus 1856 Wallace berada di Lombok, berhasil mengumpulkan ratusan specimen spesies lokal.
Narasi awal tulisan ini bersumber dari buku Wallace yang kesohor itu, berjudul “The Malay Archipelago”. Di bagian di mana murid Charles Darwin ini menggambarkan betapa interesnya orang-orang Sasak berdialog tentang ketuhanan. Meski Fernandes sendiri sebenarnya penganut Kristiani.
Namun, di sisi lainnya, di bagian itu pula saya menyimpulkan, orang-orang Sasak sudah menguasai bahasa Melayu ketika itu, di pertengahan abad 19.
Hampir bersamaan dengan Wallace, Charles Kordhoff, seorang pelaut AS, juga menyinggung tentang bahasa Melayu di Lombok.
Setelah berlayar 35 hari dari Sidney, Kordhoff tiba di pelabuhan Ampenan. “Pelabuhan Ampenan kecil, namun memiliki perkembangan yang baik. Karena ini adalah tempat Melayu pertama yang saya kunjungi, saya melihat banyak hal yang membuat saya terhibur,” tulisnya dalam “Nine Years a Sailor”, yang terbit pada 1866.
Berminggu-minggu kapalnya berada di Ampenan untuk mengisi perbekalan, sebelum melanjutkan perjalanan ke Tiongkok. Berton-ton beras dinaikkan.
Awak kapal juga membeli 25 ekor unggas yang hanya seharga 1 dolar. Sedangkan kelapa dan pisang bisa diperoleh secara cuma-cuma.
“Saya di sini membeli seekor monyet, karena saya menginginkan sesuatu untuk menghibur diri ketika kami harus berada lagi di laut,” tutur Kordhoff. Harga hewan itu 25 sen.
Orang Amerika itu bercerita tentang barang-barang yang sangat murah di Ampenan. Bahkan banyak yang didapatkan hanya dengan meminta.
Tetapi ada yang tak murah. Salah satunya burung beo lokal. Barangkali Kordhoff ingin memilikinya. Tapi karena mahal, ia hanya sanggup membeli seekor monyet.
Burung beo bisa dibeli mulai dari sepuluh sen hingga setengah dolar. Tapi itu beo biasa, yang belum terlatih. Sedangkan beo yang sudah bisa bicara harganya di atas 30 dolar.
Uniknya, beo Ampenan menguasai dua bahasa, yaitu Melayu dan Arab.
Jika unggas saja bisa berbahasa Melayu, bagaimana pula kemampuan berbahasa penduduk di luar bahasa ibu?
Sejak kapan penguasaan itu masih butuh penelusuran. Begitu pula seberapa besar bahasa Melayu mempengaruhi dialek dan subdialek lokal. (Buyung Sutan Muhlis)