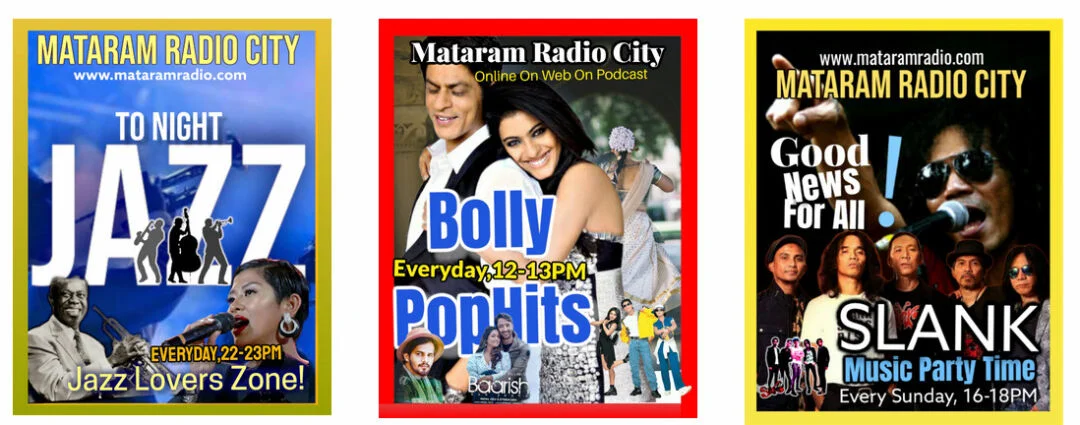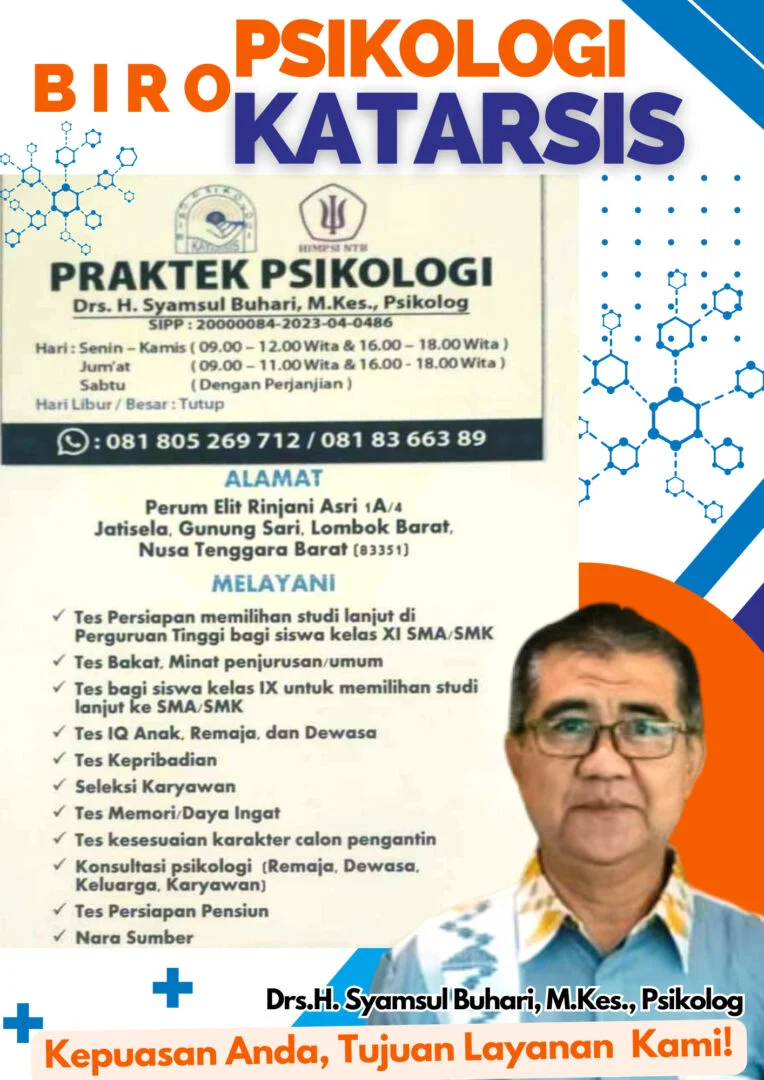Kamis pagi (17/3), saya bersama kawan-kawan Youtuber Lotim Community (YLC) menghadiri acara Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri yang digelar Lembaga Sensor Film (LSF) Republik Indonesia di Aruna Hotel Senggigi. Thema yang diangkat tentang Cerdas Memilih dan Memilah Tontonan.

Terus terang, membaca thema ini mengingatkan saya pada nostalgia kampanye masif yang dilaksanakan KPID NTB sejak 13 tahun silam.
Thema yang oleh sebagian peserta dari komunitas Konten Kreator dianggap kudet, karena sedemikian pesatnya persaingan konten termasuk film dan iklan yang menjadi ranah dan obyek tajamnya gunting sensor lembaga negara bernama LSF.


Seperti apa LSF melakukan sensor di era kekinian terutama terhadap film asing yang diputar bebas di platform digital, Over The Top seperti Itflix, Netflix dan lain-lain? Bagaimana pula dengan tayangan sinetron kejar tayang yang pagi diproduksi dan ditayangkan sore atau malam hari? Sudah maksimalkah LSF menjalankan tugasnya? Atau jangan-jangan LSF mulai kedodoran dan mengajak publik menjalankan sendiri budaya sensor mandiri layaknya menerapkan protokol kesehatan melawan pandemi Covid 19?
Dalam sesi tanya jawab, hal itu saya pertanyakan kepada narasumber dari LSF.
Saya pun menyampaikan beberapa fakta tentang kontrovesi tayangan FTV berjudul Hareem yang ditayangkan Indosiar 12 tahun silam tepatnya 2009.
Ketika itu, FTV yang dibintangi aktris Shandy Aulia dan kawan-kawannya menuai banyak protes dan aduan pemirsa TV di Indonesia termasuk dari NTB.
Sinetron Hareem jadi sorotan publik. Bahkan MUI angkat bicara mendesak KPI menghentikan sinetron yang dianggap menghina perempuan muslim berjilbab yang digambarkan selalu berprilaku buruk.
Persoalannya adalah tayangan itu disiarkan pada jam anak-anak dan remaja masih menonton TV. Sedangkan cerita sinetron berisi konten untuk khalayak dewasa yang wajib tayang Pkl 10 malam ke atas.
Pihak TV berdalih sinetron Hareem sudah dapat TLS atau Tanda Lulus Sensor dan dikategorikan bukan tayangan dewasa. Artinya boleh tayang di jam anak-anak dan remaja masih menonton TV.
Disinilah muncul kesan Industri membenturkan LSF dengan KPI karena berbeda mazhab soal mana tayangan anak, remaja dan dewasa.
Tapi, KPI tak peduli. Karena tiga teguran tak diindahkan. Akhirnya diputuskan memberi sanksi tegas Penghentian sementara Sinetron Hareem yang belakangan ganti judul menjadi Inayah dan semua pemainnya tidak lagi menggunakan jilbab, simbol wanita muslimah. Pihak TV rupanya ngambek karena gara-gara penghentian sementara KPI itu, membuat kue dan pundi iklan mereka lenyap bernilai miliaran.
Nah, itulah betapa sangat awasnya KPI untuk memastikan tayangan TV bebas dari pelanggaran aturan yang bernama P3SPS, walaupun berbenturan pemikiran dengan LSF yang kemudian melahirkan kesepakatan kedua belah pihak tentang batasan klasifikasi usia sebuah tayangan khususnya film dan sinetron.
Menurut saya, budaya sensor mandiri di era kekinian menjadi tidak efektif kalau tidak dibarengi dengan pemberian sanksi yang tegas kepada pihak yang menayangkan konten film apapun media yang digunakan.
Sudahkah ini dipikirkan atau regulasi sensorship tentang ini belum memadai?
Saya sepakat dengan apa yang disebut Rektor UIN Mataram Prof Dr H Masnun Tahir MAg sebagai apa yang disebut dengan kesalehan digital di era kekinian agar orang rajin memeriksa dan memeriksa kembali, cek and rechek apapun informasi yang diterima termasuk hiburan dan tontonan melalui internet. Apakah tontonan itu ada nilai tuntunan?
Saya juga sependapat dengan Dr TGH Lalu Ahmad Zaenuri LC MA, Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam UIN Mataram yang dalam paparannya menilai penting kehadiran LSF Perwakilan Daerah guna meringankan beban tugas LSF terhadap produksi film daerah dan iklan lokal yang bisa jadi ogah mengurus tanda lulus sensor ke LSF di pusat.
Sebagaimana paparan Dr Nasrullah, Ketua Komisi I LSF, kehadiran Lembaga Sensor Film bukan untuk membatasi kreatifitas melainkan bagaimana setiap insan perfilman dan pekerja ekonomi kreatif lainnya memahami tanggungjawab sosial agar bisa menghasilkan karya yang bukan sekedar tontonan tetapi memberi manfaat positif dan inspiratif. Bukan sekedar tontonan tetapi bisa jadi tuntunan. Masyarakat sebagai penikmat karya seni perfilman diharapkan juga membiasakan diri melakukan sensor sendiri untuk bisa memilih dan memilah tontonan sesuai kebutuhan sendiri dan keluarganya. Semoga!