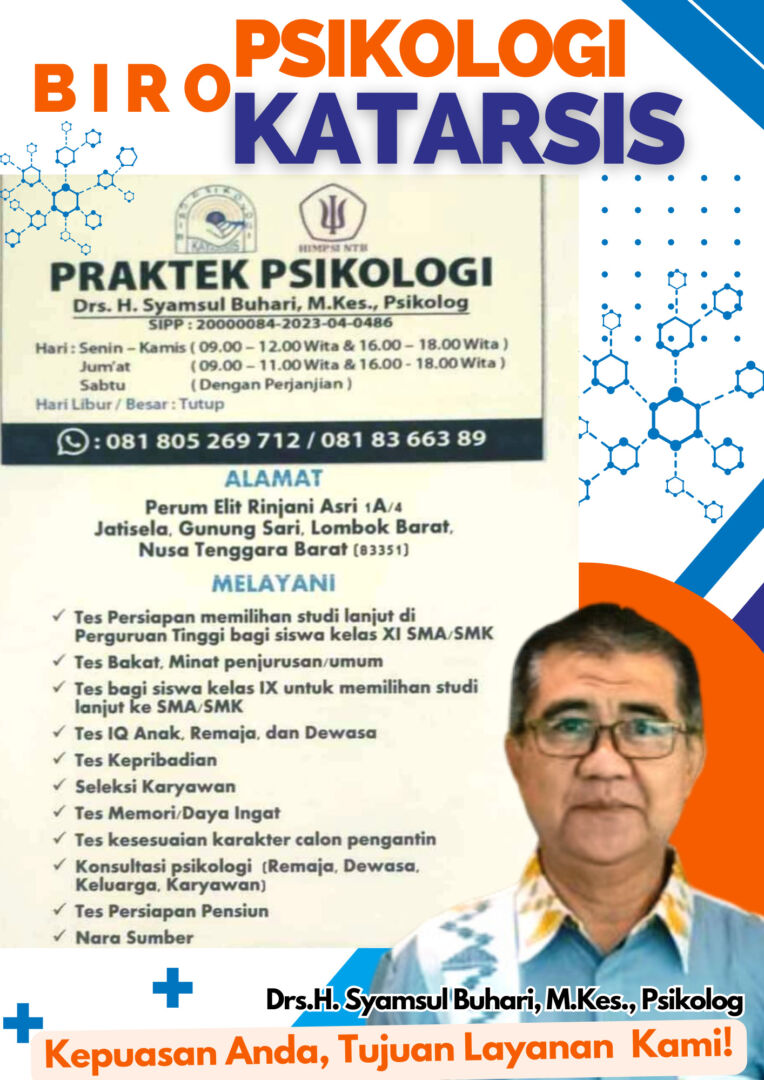Kepala dan wajah saya bengkak-bengkak, di hari ke dua berada di Sembalun, Lombok Timur. Saya kena alergi dingin. Bukannya tubuh tak pernah menghadapi cuaca ekstrem. Saya pernah di Sembalun selama satu bulan di saat temperatur menembus 10 derajat celcius. Hanya, saat ini, saya tumben ketemu suhu dingin yang disertai mendung bergerimis. Barangkali itu penyebab tubuh saya belum siap beradaptasi.
Saya buka pesan WhatApp dari Agus Susanto Batharasena. Ia seorang pelaku wisata, dan kerap terlibat dalam program-program NGO internasional yang dilaksanakan di kawasan kaldera di kaki Gunung Rinjani ini.
“Habis isya saya jemput,” katanya.


Agus mengajak saya ke Desa Sembalun Bumbung, menjadualkan pertemuan dengan seorang tokoh yang saya juluki Van Helsing dari Sembalun. Jika Gabriel Van Helsing spesialis pemburu makhluk vampire dan para drakula di Eropa, maka Van Helsing Sembalun sangat ditakuti siluman tradisional bernama sélak atau tusélak. Ia pun sering memburu tusélak yang dianggap mengganggu dan meresahkan. Kerap pula menggagalkan sangkepan (pertemuan) dan pesta para siluman tersebut.
Dengan kecepatan tinggi sepeda motor yang dikemudikan Agus membelah dingin Sembalun. Jalanan sepi. Orang-orang lebih memilih berdiam di rumah, menghindari udara dingin yang masif dan lembab. Gerimis belum reda. Saya yang membonceng di belakang Agus, menggigil menyilangkan kedua tangan menutup dada sambil berkali-kali menggemeretakkan rahang. Tambah mendekati Sembalun Bumbung, suhu dingin semakin menusuk, menembus sweater tebal yang saya kenakan.
Di desa itu kami menemui Budi, seorang petugas kesehatan. Ia penghubung kami dengan sang pemburu tusélak. Sayangnya tokoh yang kami cari sudah keburu tidur, sehingga kami harus datang lagi esok hari.
Kami duduk ngobrol di beranda rumah. Budi mengatakan, ia punya menu istimewa hari itu. “Kalau mau, masih ada sisanya,” ujarnya.
Saya seketika teringat buku yang memuat perjananan naturalis Alfred Russel Wallace selama delapan tahun di Nusantara. Di Buku “The Malay Archipelago” yang masyhur itu, Wallace juga menulis kisahnya selama tiga bulan di Pulau Lombok di tahun 1856.
Akses dari Ampenan menuju Mataram, tulisnya, berupa jalan rumput dengan lubang penuh lumpur di sana-sini. Kedua sisi jalan tumbuh pohon-pohon besar, diapit sawah yang menganak tangga, yang lebih bagus dari persawahan di Buleleng, Bali. “Padi sedang menguning. Jutaan capung mengapung di atasnya. Dan orang-orang, dengan keranjang bertangkai panjang, menangkap serangga bersayap dua itu, dikumpulkan dan digoreng untuk lauk,” tutur Wallace.
Capung-capung itu digoreng atau diberi bumbu dengan udang yang diawetkan sebagai salah satu bahannya. Saya memastikan bumbu yang dimaksud Wallace adalah terasi.
Menu yang ditawarkan Budi ternyata lauk berbahan baku serangga tersebut. “Tapi ini anak capung yang belum bisa terbang,” jelas Budi, sambil membawa sepiring nasi.
Nasi itu telah disiram kuah santan berwarna kuning, dengan puluhan anak capung yang bentuknya masih utuh. Inilah gulai serangga bernama kementer, masakan turun-temurun masyarakat Sembalun. Bumbunya dominan kemiri.
Saya mulai menyendok nasi yang berwarna kuning pekat diresapi bumbu. Suapan pertama yang tanpa serangga. Maklumlah, ini hidangan yang seumur-umur baru saya lihat kemunculannya di depan mata. Saya hanya pernah sekali mencoba menikmati pepes sarang lebah madu di Sumbawa beberapa tahun lalu. Bibir saya seperti ditempeli lemak tebal, karena kandungan zat lilin di dalam sarang.
Isi sendok kini telah berpindah ke dalam mulut. Saya mengunyah dengan ragu. Namun lidah saya mencecap sesuatu yang terasa familiar. Sengatan cabe rawit menyergap. Rasa pedas itu semacam perantara yang merangsang syaraf-syaraf selera. Di titik ini kesadaran mulai tergugah. Bahwa komposisi bumbu hidangan ini memaknakan suatu kelezatan citarasa dari sebuah tradisi yang tersembunyi di ceruk bumi yang terpencil.
“Kenapa belum disentuh capungnya?” tanya Agus yang terus memperhatikan saya tanpa berkedip.
Dengan tenang saya mengangkat dua ekor serangga itu yang nampak kehitaman, memasukkannya ke mulut. Sambil geraham melumat, lidah tak sabar menjelajah. Bumbu dalam kuah terasa meresap sempurna ke seluruh sel tubuh-tubuh capung. Tapi lidah saya masih bisa mengidentifikasi. Daging serangga itu rasanya mirip udang kering. Sendok berikutnya mengantarkan dua capung lagi. Saya kini lupa sedang menikmati kuliner asing untuk pertama kalinya. Dan dingin udara Sembalun berangsur lenyap. Boleh jadi hidangan itu menjadikan tubuh lebih tangguh menghadapi tantangan alam.
Pada suapan terakhir kuliner khas yang nikmat itu, saya membayangkan tubuh-tubuh lincah para porter yang mendaki lereng terjal Rinjani. Tak pernah berhenti melangkah meski masing-masing sedang membawa beban berat. Lelaki-lelaki Sembalun yang tangguh dan kuat. Seolah memiliki ilmu peringan tubuh. Apakah energinya berasal dari kementer, lauk berbahan capung itu? Hidangan historikal yang berkhasiat membuat tubuh seringan serangga itu? Tak menutup kemungkinan, inilah salah satu resep filosofis, menu rahasia survival orang-orang Sembalun selama berabad-abad.
Tapi saya baru sepiring saja mengonsumsi hidangan purba itu. Mungkin butuh 5-6 porsi lagi agar tubuh saya lincah seperti disusupi ilmu ginkang.(Buyung Sutan Muhlis)

Foto utama: Koleksi BSM