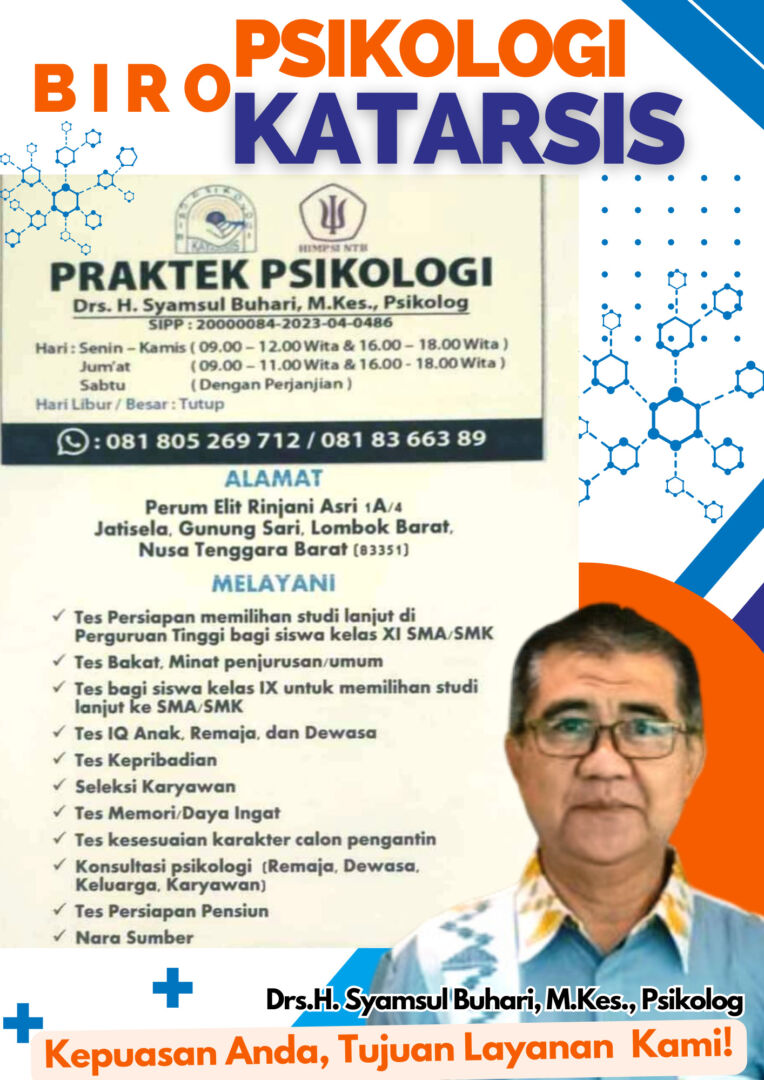Oleh: DR Salman Faris
Sungguhlah hina kita sebagai manusia jika kotoran yang keluar dari perut pejabat kita hirup aroma kasturi, sedangkan kebijaksanaan rakyat jelata miskin papa kita pandang sebagai tinja.


Betapa rendah peradaban kita jika hanya karena sang gubernur NTB menerobos hutan satu kali dinilai amat luar biasa sedangkan kaum jelata yang menemukan jalan setapak menuju gunung dan penemu jalan perambah hutan kita tidak anggap istimewa.
Karena itu, cobalah sejenak merenung jika esok lusa sang gubernur sudah tak lagi menjabat, adakah menerobos hutan itu tetap sebagai amat luar biasa atau sekadar haiking biasa-biasa saja. Dalam konteks ini, bukankah yang abadi ialah jejak perambah hutan pertama dari kaum jelata, bukan yang hingar bingar itu.
Bercermin kepada diri sendiri, amat diperlukan. Ia seringkali menjadi nutrisi yang penting ketika diri perlukan sendiri. Namun yang buruk dari bercermin kepada diri sendiri ialah sering kali kita buta terhadap luar. Terlalu dalam memasuki ruang sendiri membuat begitu banyak yang jadi terserak di luar sana.
Kebaikan di sini dapat dimaknakan sebagai kemuliaan, kehebatan, ketangguhan, kegemilangan, dan hal-hal lain serupa sesuatu yang luar biasa. Kebaikan yang dimaksudkan ialah kebaikan yang terabaikan, tidak tercover kamera dan pena jurnalis, tidak juga ditempeli di lidah-lidah para penggosip dan penyebar informasi lainnya.
Untuk dapat menjelaskan apa yang saya maksudkan terserak ialah dengan menyandingkan kebaikan yang menimbulkan hingar bingar oleh Gubernur NTB dengan kebaikan kaum rakyat jelata miskin papa. Kenapa ada yang begitu hingar bingar dan ada yang terserak di samudera kesunyian? Karena kita sebagai manusia, sebagai masyarakat, sebagai pejabat, sebagai birokrat, sebagai wakil rakyat sudah amat terbiasa kepada sesuatu bersifat elitis. Sudah menjadi budaya yang tangguh yang, kita ini memang merasa menjadi hebat jika mulut kita dorong untuk membicarakan apa pun yang dilakukan oleh publik figur. Kita amat lihai cerdik pandai mengopsisibinerkan antara kaum jelata dengan kuam elite. Dengan begitu, sebesar debu yang dilakukan seorang gubernur dapat menutup lautan kebaikan yang ditaburkan rakyat jelata di muka bumi ini. Di wajah NTB ini.
Hingar bingar lenguhan dan laku lakon pejabat membuat kita abai kepada kehebatan bertahan hidup satu orang miskin di kampung yang jauh dari kota. Dia yang tak punya harapan dari mana sesuap nasi dapat diperoleh namun tetap bertahan dalam kehidupan yang arif dan bijaksana. Tidak mengutuk siapa saja, apalagi mengutuk Tuhan. Ini baru satu orang miskin di desa. Belum digabungkan dengan ribuan bahkan jutaan orang miskin yang selalu bijaksana dan berlapang dada menyaksikan pamer kehidupan orang kaya kota, pejabat negara. Tidak mengasah belati dan tidak juga merakit sihir untuk memberikan pelajaran hidup yang pahit kepada sang tukang pamer.
Janganlah jauh-jauh. Kita selalu lupa kepada para sopir pejabat, yang setiap hari mendengar perbincangan pejabat yang segala keperluan hidupnya dijaminkan negara. Sementara dia, selaku sopir hanya bisa mendengarkan, tidak boleh memberikan komentar. Mendengarkan harum manisnya kekuasaan sang penguasa di tengah pahitnya hidup sebagai seorang sopir bergaji rendah dan lebih banyak hidup dalam ketidaklayakan. Begitu hebatnya sang sopir, dia tak pernah berfikir untuk tiba-tiba menabrakkan mobil yang dikendarai agar sang pejabat tercederai. Dalam kesabaran yang tangguh, dia mengendalikan setir kendaraan agar sang pejabat selalu dalam kenyamanan membicarakan apa saja berkaitan kekuasaan atau pertarungan politik sepanjang perjalanan. Di luar itu, dia harus bersabar melihat pejabat duduk di meja makan yang enak, sedangkan dia hanya di tepi berselisih nasi sesuai derajat dia sebagai sopir.
Kita abai kepada pembantu rumah tangga para pejabat yang, mengerjakan apa saja termasuk merawat anak-anak sang pejabat. Kita tak pernah berfikir betapa sabarnya mereka melayani berbagai karakter anak, istri, suami, menantu, cucu dan kerabat pejabat yang lain. Sedangkan sang pejabat tidur lelap dalam istirahat di tengah tidur terjaga sang pembantu sebab tak mau melukai sang pejabat. Ia tak peduli apakah sang pejabat pernah memikirkan kesejahteraan sang pembantu rumah tangga atau tidak. Yang ia lakukan hanya menjaga dan dan terjaga. Ia pun tak membuka aib rahasia pejabat meskipun bisa jadi setiap hari ia membersihkan tempat tidur pejabat sehabis bercinta. Kita abai kepada kemuliaan yang begitu tinggi sang pembantu rumah tangga di tengah derap hidup pejabat yang boleh jadi diliputi banyak sandiwara.
Kita tak pernah membayangkan perasaan mereka yang bertetangga dengan pejabat atau mantan pejabat yang tinggal di rumah megah mengendari mobil mewah. Mereka yang sehari-hari melihat gaya hidup kaum elite itu atau setiap saat menghidu aroma sedapnya makanan yang mengepul dari celah-celah dapur sang pejabat. Sementara mereka, hanya untuk makan mesti membaling dan membanting tulang. Hanya dapat menatap nanar kemewahan dan kemegahan namun tidak pernah berfikir untuk membakar rumah sang pejabat. Tidak pernah berfikir pergi ke tukar sihir untuk menyakiti sang pejabat. Bahkan sekali waktu, di tengah penderitaan menahan mau, mereka bisa jadi bangga bercerita kepada orang yang, mereka adalah bertetangga dengan pejabat.
Begitulah kita hampir setiap saat melahap pengabaian. Kita hanya pandai melihat bentuk design cincin yang kita pakai, namun tak pernah berfikir walau sesaat betapa hebatnya sang designer. Betapa hebatnya sang tukang bergaji rendah mewujudkan design cincin itu. Kita hanya melahap sedapnya masakan di warung-warung, namun tak behenti sejenak untuk membacakan fatihah dan meniatkan membalas budi kepada sang pembuat masakan yang berjuang melawan kepulan asap di dapur demi memuaskan pelanggan yang tahunya hanya membayar namun tak punya perasaan atas ketertindasan tukang masak di sisi lain.
Saking hebatnya sang pengucap dan penyebar informasi, setitik peluh sang gubernur NTB, kita jadi abai kepada rakyat jelata yang dilalui rumah mereka oleh rombongan sang gubernur. Perasaan ingin naik ke mobil mewah yang dikendarai, perasaan ingin dikawal oleh orang-orang yang setia dan sanggup mati membela sang gubernur. Perasaan mereka yang ingin merasakan bagaimana indahnya menjadi orang yang diperebutkan hanya untuk dipijit kaki dan punggung yang penat.
Kita juga abai kepada orang-orang di kapal dalam penyeberangan Kayangan Poto Tano yang, mungkin saja menyeberang dalam perut lapar, dililit hutang, digodam permasalah hidup yang amat berat. Sementara sang gubernur dan rombongan diberikan penghormatan di mana saja, termasuk di atas kapal.
Begitu banyak bahkan tak terhingga orang-orang yang hidup dalam penderitaan yang amat lama, amat dalam. Hidup dalam lilitan hutang yang mengancam nyawa. Hidup dalam bayang-bayang kesengsaran demi kesengsaraan yang berlapis-lapis. Hidup dalam pergulatan tanpa tali harapan dan tiang kecerahan. Namun mereka tetap bersikap arif dan bijaksana. Tetapi menjalani hidup dengan membagi senyum. Hidup dalam usaha sunggung-sungguh berdamai dengan keadaan tanpa menyulut api kekisruhan. Hidup dalam janji yang tertunaikan.
Dan begitu tiba masanya untuk memilih, meskipun mereka sudah tahu dan sudah mengalami berulangkali penipuan janji dan pengingkaran sang pejabat, mereka tetap memberikan pilihan. Pilihan tulus. Pilihan harapan. Sedangkan sang pejabat hanya pandai disanjung. Hanya hebat dilindung.
Begitulah, kalau kita mau dengan rendah hati membandingkan atas dasar kemanusiaan yang murni, antara setitik kebaikan seorang gubernur dan puluhan pejabat teras dengan beribu-ribu orang yang setiap hari bergelut dengan penderitaan. Terutama jika melihat dari sudut pandang yang jernih ketika sang gubernur dikritik membalas dengan ketersinggungan atau ketika sang birokrat dimutasi membalas dengan umpatan kebencian, sementara mereka yang menderita bertahun-tahun istikomah dalam kearifan, maka, sungguh kita akan meyadari bahwa apa yang dilakukan sang gubernur tidak ada apa-apanya dibandingkan pengorbanan rakyat jelata yang sengsara.
Rasa penat sang gubernur yang hanya sehari itu, sungguh tidak bernilai jika dibandingkan dengan mereka yang setiap hari bergulat dengan kepenatan dalam kesengsaraan.
Namun sekali lagi, kita memang manusia beradab yang tidak punya adab dalam melihat secara manusiawi. Adab kita hanya setakat kaum penyembah berhala kuasa bukan adab memberi rasa hormat, bukan adab tunduk dalam doa kepada mereka yang tak habis-habisnya sabar dalam kesengsaraan.
Sungguh, kita belum sampai pada kesejatian kuasa: kuasa manusiawi yang tidak menyerakkan kemanusiaan lain yang dekat dan setiap saat ada di sekeliling kita.
Malaysia, 1 November 2020