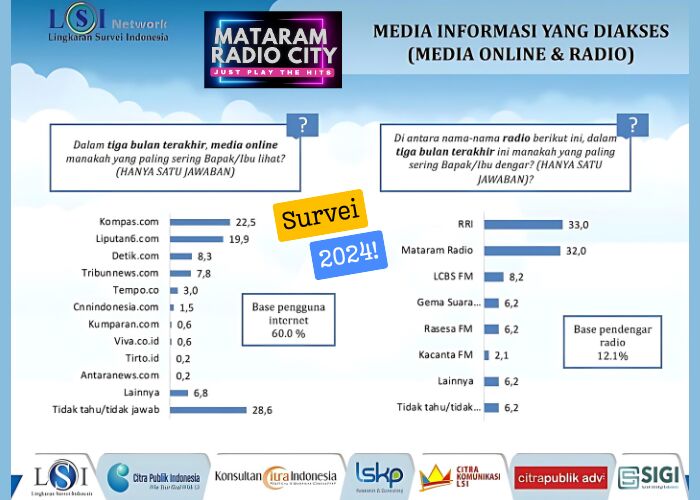Kisah Francisca Christy Rosana, atau yang akrab disapa Cica, bukan sekadar cerita seorang wartawan yang diteror karena keberaniannya mengungkap fakta.
Ini adalah cermin buram dari kondisi kebebasan pers di Indonesia, sebuah pilar demokrasi yang kini tampak rapuh di bawah bayang-bayang ancaman dan sikap acuh pemerintah. Di akhir pekan ini, saat kita merenungkan arah bangsa, kasus Cica menyeruak sebagai pengingat: kebenaran yang tak dilindungi adalah kebenaran yang akan tenggelam.
Cica, peladen Bocor Alus Politik dan wartawan desk politik, tengah menghadapi teror yang tak main-main. Pesan ancaman, telepon misterius, hingga kehadiran sosok tak dikenal di sekitar rumahnya telah menjadi bagian dari kesehariannya. Ia bukan korban pertama, dan sayangnya, mungkin juga bukan yang terakhir. Dewan Pers mencatat 89 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang 2024—angka yang cukup untuk membuat kita bertanya: apa yang salah dengan sistem ini?


Pernyataan Hasan Nasbi, yang menyebut ancaman semacam itu sebagai “risiko pekerjaan,” adalah pukulan telak bagi harapan akan perlindungan negara terhadap insan pers. Ucapan itu tak hanya dingin, tetapi juga menunjukkan betapa jauhnya jarak antara penguasa dan realitas yang dihadapi jurnalis. Jika risiko menjadi alasan untuk membiarkan teror berlangsung, lalu apa bedanya demokrasi dengan tirani yang menyamarkan wajahnya?
Kekecewaan publik, yang disuarakan dengan lantang oleh Fedi Nuril dan warganet, adalah cerminan dari keresahan yang lebih luas. Tagar #LindungiCica dan #KebebasanPers menggema di media sosial, bukan sekadar tren sesaat, tetapi seruan kolektif agar pemerintah membuka mata. Fedi, dengan tegas, menyinggung inti persoalan: “Kalau pemerintah tak bisa melindungi, apa gunanya kita bicara demokrasi?”
Pertanyaan itu menggantung, menanti jawaban yang tak kunjung tiba.
Kebebasan pers bukan barang mewah yang bisa dikorbankan demi stabilitas semu. Ia adalah darah yang mengalir dalam nadi demokrasi, memastikan kekuasaan tak menjadi dewa yang tak tersentuh. Ketika Cica dan rekan seprofesinya dipaksa memilih antara kebenaran dan keselamatan, kita semua kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar: hak untuk tahu, hak untuk bersuara, hak untuk hidup dalam negara yang adil.
Pemerintah, hingga kini, terkesan berdiam diri. Tak ada pernyataan tegas dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, tak ada langkah nyata dari kepolisian untuk menyelami kasus Cica. Sikap pasif ini bukan hanya kelalaian, tetapi juga pengkhianatan terhadap amanat konstitusi yang menjamin kebebasan berekspresi. Jika ancaman terhadap jurnalis dibiarkan menjadi “risiko pekerjaan,” maka kita sedang menyaksikan erosi demokrasi yang perlahan tapi pasti.
Akhir pekan ini, mari kita renungkan: sampai kapan kebenaran harus dibayar dengan ketakutan? Cica tak sendiri—di belakangnya ada ribuan mata dan telinga yang menanti keadilan.
Pemerintah harus bertindak, bukan dengan kata-kata kosong, tetapi dengan langkah konkret: usut teror ini, lindungi jurnalis, dan buktikan bahwa Indonesia masih layak disebut negara demokratis.
Jika tidak, suara rakyat, yang kini bergema di dunia maya, akan berpindah ke jalanan. Dan saat itu, diam bukan lagi pilihan.