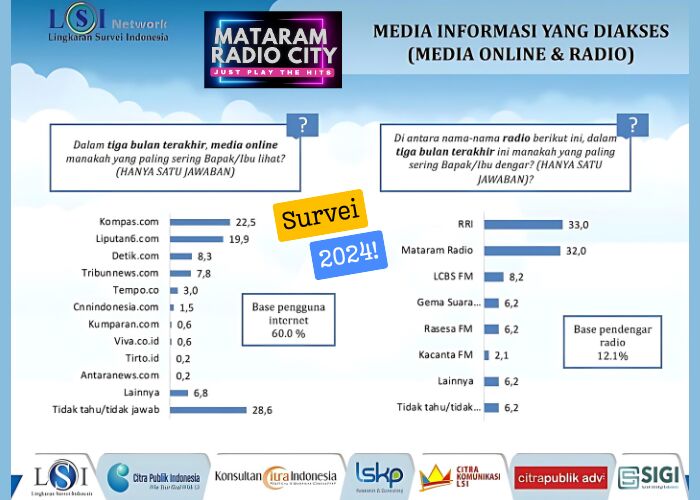Kita sudah terlanjur mengukur tidak miskin itu dengan standar tercukupinya keperluan material dan tidak mempunyai hutang. Pertanyaannya, apakah semua kaum berpendidikan sudah memenuhi standar itu? Tentu saja karena berpendidikan, pandangan umum pasti menempatkan kaum berpendidikan sebagai kelompok atau kelas sukses.
Dalam situasi ini, ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi. Pertama, kaum berpendidikan malu dikatakan miskin. Dengan begitu mereka akan melakukan segala macam cara untuk menutupi rasa aib malu tersebut. Yang paling populer ialah berhutang. Sampai di sini, sebenarnya sudah jelas, karena berhutang, kaum berpendidikan tak dapat dikategorikan kelas sukses.

Konsep hutang dalam konteks ini ialah hutang pasif atau hutang yang pengembaliannya hanya dari pendapatan tetap alias bulanan (yang jumlahnya amat tak seberapa). Bukan hutang untuk menggerakkan usaha sebagaimana kelompok pebisnis. Dan hutang pasif ini ialah penyakit kebanyakan kaum berpendidikan.


Kedua, kaum berpendidikan akan bekerja sebagai pengajar atau dosen atau guru di banyak tempat. Kenapa banyak tempat? Karena jika mengajar di satu tempat, keperluan ekonomi sudah pasti tidak tercukupi. Sampai di sini, semakin jelas yang kaum berpendidikan ini sebenarnya tergolong miskin karena meskipun mengajar di banyak tempat, mereka tetap tak dapat memenuhi keperluan ekonomi yang dikategorikan layak. Selain itu, keperluan istirahat dan menikmati senggang dalam kebahagiaan pasti terabaikan karena tenaga sudah habis untuk wira wiri mengajar di banyak kampus atau sekolah atau madrasah.
Ketiga, berafiliasi dengan penguasa. Tentu saja, ini pilihan rumit karena sebenarnya tidak banyak kaum berpendidikan terdidik untuk melacurkan pengetahuan. Pelacuran pengetahuan ini merujuk kepada satu keadaan di mana, sebenarnya afiliasi tersebut tidak dapat menjamin terpenuhinya keperluan ekonomi kaum berpendidikan. Afiliasi tersebut hanya nampak megah namun sesungguhnya kosong simpanan.
Sampai di sini, semakin jelas pula yang kaum berpendidikan mengalami krisis eksisteni dan kegelapan orientasi. Kedua hal ini ialah salah satu fondasi kemiskinan. Maknanya, kaum berpendidikan sebenarnya masih miskin meskipun mereka berada di tengah wangi kekuasaan. Kecuali kalau mereka juga terlibat dan pandai dalam merampok uang rakyat sebagaimana perampok yang sudah mapan, boleh jadi ekonomi terpenuhi. Namun dengan kaum berpendidikan seperti itu, mereka sudah masuk ke dalam jurang serendah-rendahnya kaum berpendidikan.
Keempat, kaum berpendidikan akhirnya masuk partai atau berpolitik. Tidak dapat dikatakan yang kelompok partisan sebenarnya ialah “pekerja” atau “buruh” dalam partai. Mereka mencari makan melalui lumbung partai. Namun melihat situasi demokrasi dan politik di Indonesia, misalnya, tak dapat juga ditampik yang banyak kaum partisan memang mencari makan dengan cara berpolitik. Nah, dalam situasi kegelapan seperti itulah, dengan terpaksa, kaum berpendidikan menceburkan diri tanpa modal ekonomi. Hanya mengandalkan modal budaya berupa sedikit pengetahuan. Akhirnya, ujung-ujungnya, terbawa arus habitus perampok uang rakyat yang sudah emiritus dalam dunia rampokan meski mereka berpendidikan rendah.
Jadi, kemiskinan terselubung ini sebenarnya bahaya laten. Ia sangat tersembunyi. Bersemayam di balik dunia citra ijazah dan pengetahuan. Namun amat disayangkan, kemiskinan jenis ini amat susah terdeteksi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Karena susah terdeteksi, maka fenomena ini sesungguhnya ialah virus yang paling berbahaya dibandingkan virus kemiskinan orang biasa.