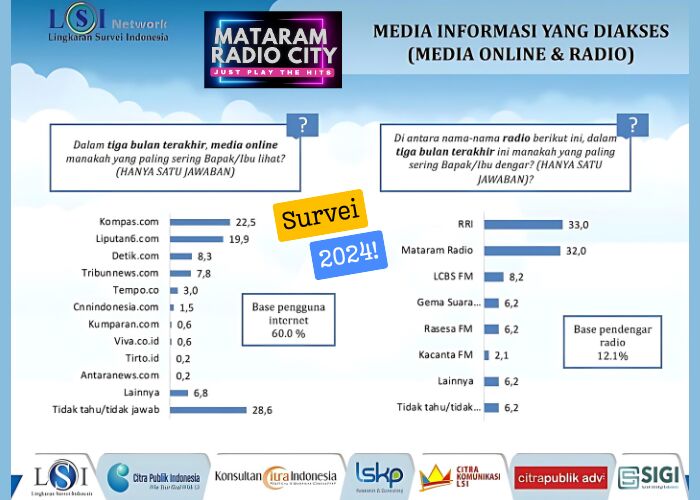Pasca kerusuhan 17 Januari 2000 di Mataram, situasi tak menentu. Di kompleks BTN Sweta tempat saya mengontrak, banyak rumah ditinggalkan pemiliknya dalam waktu lama.
Oleh: Buyung Sutan Muhlis
Selama seminggu Mataram lumpuh total. Jalan-jalan sepi. Tidak ada kantor dan toko-toko buka. Bank-bank tutup. Kami di rumah bertahan dengan persediaan yang pas-pasan. Saya punya uang, tapi di mana mencari bahan-bahan pokok? Mulai dari kios kecil hingga distributor besar tidak buka. Pasar-pasar tak beroperasi. Di hari ke enam saya gelisah. Logistik dapur hanya cukup untuk hari itu. Untunglah saya diberitahu saudara, ada warung sembako buka di kompleks pasar Ampenan. Siang itu juga saya melintasi jalan dari Sweta sampai Ampenan yang sunyi mencekam. Keadaan seperti demikian membuat saya merinding, meski hari terang. Itulah kali pertama saya ke luar kompleks. Ruko tempat menjual bahan-bahan pokok itu hanya sendirian buka. Menghadap ke barat, ke arah bangunan bekas sekolah Cina. Belum jam 11, tapi pemiliknya meminta saya cepat-cepat memilih bahan-bahan yang diperlukan, dan mengatakan ia akan segera menutup tokonya. Ia nampak gelisah. Saya bergerak cepat. Saya pulang membawa persediaan yang cukup untuk dua minggu ke depan.


Saya tinggal di Jalan Pakis VIII, menempati sebuah rumah yang berhalaman paling luas di kompleks tersebut. Totalnya sekitar 3,5 are. Dikelilingi tembok tinggi dan tebal, seperti benteng. Di pekarangan samping tumbuh dua pohon mangga madu. Saya juga menanam beberapa pepaya Bangkok dan sayuran di belakang rumah. Kami tak pernah kekurangan buah dan sayuran. Saya juga membagi-bagikannya pada para tetangga.
Sudah beberapa malam saya melihat beberapa ekor ayam tidur di pohon-pohon mangga itu. Saya memberitahu para warga satu RT ketika kami berkumpul di gardu ronda. Sejak kerusuhan meletus, ronda aktif kembali. Bahkan tidak bergilir lagi, karena semua warga selalu keluar malam, berjaga-jaga hingga subuh.
“Saya sudah ke RT-RT sebelah, tapi tidak ada yang mengaku kehilangan ayam,” jelas saya.
“Kalau begitu, itu ayam-ayam Tuhan,” seseorang menjawab.
Kami saling berpandangan.
“Kalau ayam Tuhan, lalu kita apakan?” saya bertanya.
“Kita potong, kita makan bersama.”
“Begitu?”
Malam itu seekor ayam yang ditangkap dari pohon mangga itu disembelih. Di dapur salah seorang tetangga, nampak kesibukan hingga larut malam. Tidak melibatkan para istri, sebab mereka semua sudah hanyut di alam mimpi masing-masing. Makanan terhidang di atas gardu. Semua masih mengepul, baik nasi maupun daging ayam yang sudah matang. Entah masakan apa namanya. Daging yang sudah dipotong-potong dimasukkan ke dalam air mendidih. Apa saja bumbu yang ditemukan di dapur dimasukkan.
Tapi, ternyata ketika kami mulai menyantap, lezatnya bukan main. Yang bertindak sebagai juru masaknya sendiri terheran-heran. Seumur-umur baru kali itu terlibat urusan dapur.
“Ini sangat enak, karena ayamnya dari Tuhan,” kata Haji Rifai, yang tinggal di tikungan jalan.
Tiap malam selama hampir seminggu kami bekela (pesta, bahasa Sasak). Sampai seluruh ayam Tuhan itu tak bersisa barang seekor pun.
Seminggu kemudian.
Seorang tetangga memandang ke atas dari bawah pohon mangga.
“Nah, itu ada lagi ayam Tuhan.”
“Bukan, Pak. Itu ayam malaikat,” sahut saya.
Ia menatap saya tak mengerti. Saya melanjutkan, “Ada kawan datang kemarin, membawa seekor ayam jantan. Ayam kesayangannya. Dia mau berangkat ke Jakarta, ayam jago itu dihadiahkannya. Anak saya gembira sekali. Karena dia baik, saya sebut dia berhati malaikat.”
“O begitu.”
Ia melangkah hendak pulang, tapi berhenti. Ia bertanya, “Lha, kalau punya ayam dari hasil curian, apa namanya?”
“Itu ayam iblis.”
Ia tertawa terbahak sambil ngeloyor pergi. Azan maghrib terdengar dari musholla di pertigaan jalan kompleks.(Buyung Sutan Muhlis)