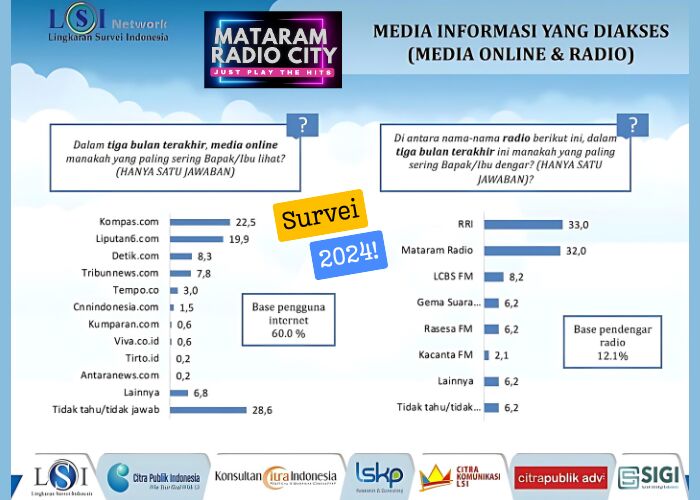Oleh: Buyung Sutan Muhlis
Tahun 1990an, Mataram punya julukan yang sangat tak enak didengar: Mataram Kota Tahi Kuda! Di mana-mana tahi kuda. Di gang-gang, hingga di jalan-jalan utama.
Ada ribuan cidomo (kendaraan tradisional dihela seekor kuda) yang bebas beroperasi di mana pun. Boleh dibilang tak ada zona terlarang untuk cidomo. Orang-orang tak punya pilihan. Hanya kendaraan inilah yang bisa mengantar hingga ke ujung kampung, yang tak terlayani kendaraan bermesin plat kuning atau bemo kota.



Leluasanya kendaraan yang dikendalikan para kusir itu, berdampak pada kekumuhan kota. Kota ternoda. Kuda-kuda berak di jalan. Kotoran-kotoran hewan ini sangat menyolok, mencemari wajah kota. Inilah salah satu problem yang dihadapi Pemerintah Kota Mataram. Saat itu masih berstatus kota administratif.
Beberapa upaya ditempuh, salah satunya dengan menerbitkan aturan, setiap cidomo harus menyiapkan karung yang diletakkan di bawah pantat kuda. Sehingga kotorannya tidak jatuh langsung ke jalan yang dilalui. Juga mulai dibuat sejumlah even untuk sosialisasi peraturan terkait ketertiban cidomo-cidomo di jalan raya.
Di bawah beringin besar di depan lapangan pacuan kuda, Selagalas, saya melihat teman-teman berkerumun. Puluhan pasang mata bersinar-sinar, menatap ke arah yang sama. Belasan meter di depan mereka, ada beberapa cidomo yang telah dihias sehingga nampak indah, jauh berbeda ketika sedang beroperasi di jalan.
Tetapi bukan cidomo-cidomo itu yang menarik perhatian mereka.
“La keseleh’n (wah, cantik sekali, bahasa Sasak),” puji beberapa diantaranya hampir bersamaan.
Hari itu berlangsung Festival Cidomo se-Kota Mataram. Ratusan pemilik kendaraan tersebut ambil bagian. Cidomo-cidomo peserta tampil beda di hari itu. Dihias seindah mungkin, sehingga menyerupai kereta-kereta yang membawa para putri raja.
Di atas masing-masing cidomo duduk dengan anggunnya seorang gadis berpakaian adat Sasak. Tentu saja semuanya cantik rupawan. Mereka ini disebut ratu-ratu cidomo.
Namun hanya tiga cidomo yang berhasil memenangkan kontes tersebut. Masing-masing mewakili tiga kecamatan, yaitu Ampenan, Mataram, dan Cakranegara. Juara pertama diraih cidomo dari Kecamatan Cakranegara. Cidomo berpenampilan terbaik, dan ratunya tercantik se-Kota Mataram. Gadis inilah yang membuat para pemuda itu tak berkedip sejak tadi.
“Kalian hanya berani memuji dari jauh,” saya menegur mereka.
“Dia ratu, soalnya. Memangnya kamu berani merayunya?”
“Kenapa tidak?”
Saya melangkah tenang, diikuti belasan pasang mata yang kini berubah cemas. Saya hampir berhenti ketika empat langkah lagi sampai. Mata saya yang agak rabun jauh sejak kecil kini semakin jelas melihat detil sosok di depan saya. Seperti ada kekuatan yang tak terlihat, memperlambat langkah saya. Saya baru insyaf, mengapa teman-teman tidak punya nyali mendekat. Gadis itu adalah magnit sejati. Sisi yang berbeda kutub akan membangun gravitasi, tapi di saat bersamaan ia adalah kutub yang memiliki daya tolak.
Bukan kali ini saja saya berhadapan dengan wanita cantik. Sudah berapa kontes kecantikan saya hadiri, dan mungkin saya, di luar kepanitiaan, orang yang paling sibuk dalam even-even demikian. Dengan berkedok wartawan saya mendekat. Dan begitu melihat saya, semua peserta kontes pasang aksi. Mata saya yang mestinya tertutup sebelah karena salah satunya fokus pada jendela bidik (viewfinder) saya tak pejamkan. Dari jarak dekat, saya puaskan mata saya menikmati wajah-wajah itu, tubuh-tubuh dengan lekuk indah itu. Mereka terus mengumbar gaya. Tapi mereka tak pernah tahu saya sudah kehabisan film sejak tadi.
Cepat-cepat saya mengubah keadaan yang telah dikendalikan oleh pesonanya. Jika ia magnit itu, saya adalah pasir atau logam besi, yang akan selalu mengikuti dan mendekati arus daya tariknya.
“Maharani,” ia menyambut uluran tangan saya, dan memperkenalkan nama.
Telapak tangan yang begitu lembut, seperti menyentuh kulit telur muda. Saya menyalaminya sambil terus menatap wajahnya, mencari-cari bagian hitam di bola matanya yang tadi sempat membuat langkah saya tertahan. Tetapi kepalanya sekarang agak menunduk.
Maharani, gadis 16 tahun, ratu cidomo dari sebuah kelurahan di Cakranegara. Dara dengan detil keayuan yang orijinal, terpapar cahaya senja yang masih terang. Ia primadona. Prime donne, perempuan pemeran utama pagelaran opera yang mulai menjadi istilah populer di Italia sejak abad 19.
Walahnya kalem, cantik yang tak sederhana. Puspa terindah di hektaran taman yang penuh bunga. Saya menyangka ia gadis persilangan antaretnis. Keningnya cermin perempuan Sasak yang sabar dan tegar. Sedangkan hidungnya mancung bersahaja. Bibirnya tipis ranum seperti anggur flame seedless yang dibudidayakan di Australia. Ketika ia menyebutkan namanya, saya sempat melihat deretan giginya yang rapi, putih berkilau. Ada belahan samar di ujung dagunya. Kulitnya putih seperti kebanyakan wanita Manado. Ia adalah Betsy dalam sajak Rick dari Corona gubahan WS Rendra.
Betsyku bersih dan putih sekali.
Lunak dan halus bagaikan karet busa.
Rambutnya mewah tergerai.
Bagai berkas benang-benang rayon warna emas.
Dan kakinya sempurna.
Singset dan licin bagaikan ikan salmon.
“Boleh saya midang (mengapeli, mengunjungi wanita, bahasa Sasak) ke rumahmu?”
Ia mengangguk. Mata kami sempat bertemu lagi. Matanya cukup lebar, seperti mata penari Bali. Seketika wajahnya bersemu merah.
“Mulai nanti malam, ya?” saya bertanya lagi.
“Iya.”
Iya. Suaranya lirih. Dia bilang iya. Midang atas perkenan perempuan yang dikunjungi, saya pastikan tanda-tanda penerimaan yang ikhlas. Memberi kesempatan midang, adalah kearifan gadis-gadis Sasak yang tak ingin mengecewakan seseorang yang hendak bersilaturahmi. Tetapi saya menerjemahkannya dengan lebih percaya diri. Kata iya dan sebelumnya sempat melihat wajahnya yang tersipu malu, adalah isyarat bahwa ia paham tujuan saya datang. Ia memberikan saya ruang untuk merayu, memujanya, dan selanjutnya ingin mendengarkan kejujuran saya. Satu tahapan ritual asmara sedang dimulai.
“Dan setelah itu tidak akan ada yang boleh mengapeli kamu selain saya.”
Tentu saja saya hanya mengucapkan itu dalam hati.
Setengah jam lagi matahari terbenam. Kami berpamitan. Tangan kami berjabat lagi. Kali ini saya rasakan telapak tangannya lebih hangat. Dan tangan saya sedikit gemetar ketika mata kami bertemu lagi.
Saya kembali ke tempat teman-teman, melangkah jumawa seperti pahlawan yang menang perang.
“Sumpret! Kamu pegang tangan anak orang lama sekali. Tidak ada orang salaman seperti itu,” seseorang memprotes saya, nadanya sangat cemburu.
Tetapi sebagian besar memuji nyali saya. Seseorang menarik tangan saya, mengajak saya agak menjauh.
“Kamu ngomong apa saja tadi?”
“Saya bilang mau midang.”
“Dia jawab apa?”
“Dia bilang iya. Dia menunggu saya.”
“Benar?”
“Saya bahkan diberitahu alamatnya.”
Senyum kawan itu mengembang.
“Kapan?”
“Mulai nanti malam.”
“Ajak saya, ya?”
Saya mengiyakan. Tapi itu kesalahan besar yang belakangan saya sadari.
Rumah Maharani berada di sebuah gang. Dengan mudah kami menemukannya.
“Maharani bodak? Terus saja. Rumahnya di deretan kanan,” seorang warga memberitahu kami.
Dia dijuluki bodak. Kata ini sering dilekatkan pada seseorang yang berkulit sangat putih atau seperti bule.
Gadis itu menerima kami di ruang tamunya. Dia menghidangkan kami dua cangkir teh. Saya memulai percakapan. Bertanya tentang keluarganya. Ternyata dia anak tunggal. Kawan yang menemani saya lebih banyak diam. Tapi bagaimanapun saya tetap merasa terganggu. Besok malam saya mesti datang sendirian.
Esoknya saya datang lagi. Tapi, belum lima menit duduk, saya mendengar deru puluhan sepeda motor datang dari ujung gang.
“Sumpret. Pasti mereka.”
Tak lama wajah-wajah itu muncul di depan pintu. Wajah-wajah yang sangat saya kenal. Mereka berhamburan masuk tanpa dipersilakan. Inilah yang saya khawatirkan.
“Teman-temanmu?” tanya Maharani.
Sebagian dari yang datang adalah mereka yang terpana menatap Maharani di atas cidomo, kemarin sore.
Ada semacam kesepakatan tak tertulis dalam pertemanan kami. Tidak boleh ada teman yang berbahagia, sementara teman lainnya gigit jari. Kekompakan yang konyol. Tidak boleh ada yang mencoba-coba memiliki pacar di saat hampir semua menjomblo. Jika ketahuan, dengan berbagai cara akan digagalkan. Saya pun pernah terlibat membubarkan hubungan beberapa kawan.
Ada teman yang sangat jahil. Ia diajak midang ke Lingsar. Kawannya itu baru berpacaran sekitar seminggu. Ada desas-desus ia akan segera merariq (perkawinan dalam tradisi Sasak).
Di rumah sang gadis, beberapa kali pemuda yang ditemani midang itu minta ijin ke kamar kecil.
“Mengapa dia sering ke kamar kecil? Sakit perut?” tanya gadis itu.
“Bukan. Pantatnya memang sering gatal. Dari dulu begitu. Dia cacingan. Cacing kremi.”
Wajah gadis itu mendadak seperti menahan mual, setelah mendapat penjelasan tentang penyakit yang dialami kekasih barunya. Penyakit yang sangat menjijikkan. Ia tidak butuh mengonfirmasi kebenarannya. Mulai besok malam, gadis itu tidak sudi menemui pemuda itu lagi. Rencana merariq pun buyar.
Saya sudah pasrah. Entah fitnah apa yang akan mereka ciptakan. Itulah malam terakhir saya mengunjungi Maharani. Dan itu lebih baik bagi kami. Ketimbang ketika hubungan terlalu larut, lalu badai yang tak mampu kami hadapi, muncul tiba-tiba.
Setahun kemudian festival cidomo kembali diadakan. Tetapi saya tak melihat Maharani lagi. Di manakah dia, apa kabarnya?
Betsy gemerlapan bagai lampu-lampu Broadway.
Betsy terbang dengan indah.
Bau minyak wanginya menidurkan New York.
Dan selalu sesudah itu aku diselimutinya
dengan selimut katun yang ditenunnya sendiri.
Betsy, di mana engkau, Betsy?
Maharani, gadis berpakaian adat Sasak yang jelita, puspa terindah di suatu senja. Ia pernah terlibat dalam mendukung program kota. Mataram lalu berangsur-angsur melenyapkan citra yang dulunya jorok dan semrawut. (Buyung Sutan Muhlis)