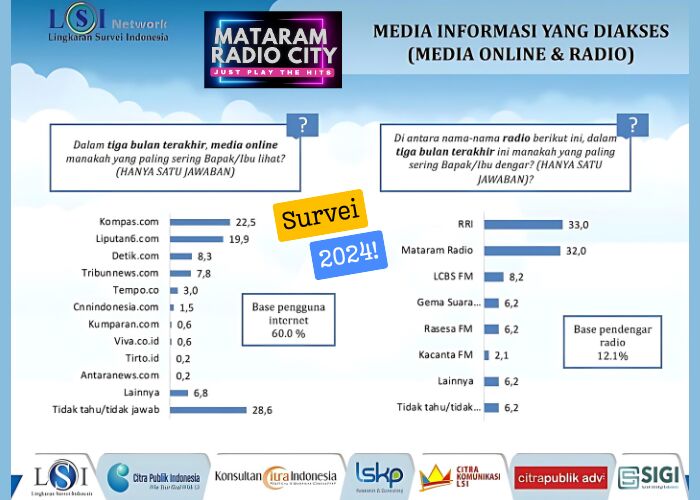“Meton, Insya Allah tanggal 16 November 2022, kita akan ada pengukuhan Guru Besar di UIN Mataram. Prof. Wahid dan Prof. Atun.”
Pesan singkat tersebut dari saudara terbaik saya, Prof. Dr. Masnun Tahir, Rektor UIN Mataram. Seperti biasa, beliau berkabar jika ada sahabat di UIN yang akan dikukuhkan menjadi Guru Besar. Saya dapat merespons pesan singkat tersebut setelah tiga hari .

Terbaru saya berjumpa dengan bung Wahid di bulan puasa tahun ini di rumah gagasan dan tapak juang Kalikuma. Rumah yang menjadi sebagian dari sejarah Alamtara, satu lembaga yang didirikan bung Wahid bersama mbak Atun yang konsen sepenuhnya tentang kemanusiaan dan ilmu pengetahuan. Karena sangat lama tidak jumpa, kami kebanyakan berbicara ringan. Tidak banyak bercerita soal Guru Besar karena itu bukan dirinya. “It’s natural, has to take it as a part of my life. Can not escape because it is a compulsory journey to take up.” Hanya itu yang beliau katakan. Dan saya mengangguk karena saya cukup memahami bung Wahid. Bung Wahid orang yang tak pernah berkata apa pun tentang dirinya karena hampir seluruh gagasannya untuk kepentingan orang lain. Dirinya tenggelam di dalam orang lain.


Di tengah sembang ringan itu, sambil “diganggu” oleh anaknya yang nomor empat, perempuan yang sangat mirip mbak Atun, saya dengar suara mbak Atun dari telepon bung Wahid. Pada waktu yang sama, mereka sedang ada tugas menguji di kampus UIN namun bung Wahid terlambat karena saya sedang bertamu. Beliau segan meminta saya pergi. Seketika itu saya mengakhiri perbincangan. “Salam saya untuk mbak, Atun.” Penutup diskusi.

Pengukuhuan Guru Besar kedua guru saya tersebut sejatinya alamiah. Namun jika dihubungkan dengan moralitas, maka sungguh memberikan ruang perenungan yang mendalam. Mbak Atun, apa yang saya tahu, sebenarnya sudah berhak dikukuhkan sejak tahun lalu. Namun menunggu hingga tahun ini ialah satu tanda moral. Bernilai mendalam. Pesan besar kepada semua kita tentang banyak hal.
Sebagai pemikir kritis, mbak Atun pasti dipandang etik jika mengambil kesempatan tahun lalu untuk dikukuhkan sebagai Guru Besar. Dalam standar moral Barat, antara diri beliau sebagai intelektual dapat dipisahkan dari dirinya sebagai istri. Referensi pengetahuan yang beliau baca pasti mendedahkan tentang perempuan berhak terbang jauh meski mengepak di sayap pernikahan.
Hebatnya, mbak Atun malahan tidak terkungkung oleh pengetahuan yang luas tentang perempuan itu untuk mendikte takdirnya. Lalu menjadikan semua itu sebagai alasan untuk mengambil kesempatan yang lebih banyak datang pada dirinya dibanding suaminya. Pengetahuan itu digunakan untuk meramu pernak pernik, bukan dijadikan hiasan utama untuk memantik kewibawaan diri dalam institusi bernama rumah tangga. Pengetahuan Barat yang beliau kuasai secara matang itu telah di-Timur-kan dan juga di-Islam-kan. Jadi standar moral mbak Atun bukan berpusat pada pengetahuan Barat melainkan Timur dan Islam. Pengetahuan Barat dalam dirinya ditaklukkan sedemikian rupa hingga tak nampak sedikit pun dalam perilaku. Ia hanya berkelindan sebagai pengetahuan di wilayah logos karena Timur dan Islam sebagai selancar dalam pergaulan dan hubungan sosial.
Perilaku mbak Atun di depan keluarga dan masyarakat bukan berteori melainkan praktik aqidah. Aqidah yang berperan besar mengonstruksi struktur berpikir setelah pengetahuan berpijak di laman logika. Dengan begitu, pengetahuan Barat yang dikuasainya malahan tidak nampak sama sekali dalam praktik sosial mbak Atun, baik di hadapan suaminya maupun orang lain.
Dalam konteks tersebut, mbak Atun telah menjunjung kehormatan suaminya di atas kewibawaan dirinya sebagai intelektual yang berpengetahuan luas dalam bidangnya. Lukisan semacam inilah yang dijumpai dalam intelektual muslim yang, pada akhirnya menegaskan perbedaan mendalam dengan pemikir Barat. Mbak Atun ialah salah seorang tokoh penting dalam hal ini. Salah satu maksudnya ialah mbak Atun menjadi cerminan yang menonjol bagi intelektual orbitan Barat. Mengaplikasikan ilmu Barat tanpa merusak rumah sendiri. Menggulung ijazah Barat tanpa membakar kampung sendiri. Tidak juga mengubah sejati diri. Ini ialah mbak Atun.
Menunggu bersama bung Wahid dikukuhkan sebagai Guru Besar, bukan pesan sederhana. Sekali lagi ini bernilai tak terhingga, tidak hanya kepada intelektual yang banyak tertatih di tengah-tengah ruang domestik dan ruang publik. Sangat hebat di publik namun kerdil di tilam domestik. Juga kepada semua keturunan mereka. Orang tua sebagai guru dan teladan yang sangat hebat. Bung Wahid dan mbak Atun benar-benar menjadi antitesis banyak intelektual yang sukses menjulang sebagai pengajar namun gelap gulita sebagai orang tua. Sampai di sini, dalam ranah nilai, bung Wahid dan mbak Atun, sebenarnya tak perlu mengajar lagi, karena peristiwa pengukuhan secara bersama ini memahat nilai yang terus relevan. Ialah pendidikan, pengajaan, dan pembelajaran itu sendiri.
Bung Wahid pula, kedalaman dan keluasan pengetahuan yang dimiliki dalam bidangnya, tidak membuat dia merasa tinggi hati dan tidak juga menjadikannya berpikir rendah diri di hadapan mbak Atun. Bung Wahid memberikan pintu samudera yang luas. Tidak menggunakan kuasa pengetahuan dan kuasa struktur sebagai suami untuk menghegemoni mbak Atun. Tidak ada praktik dominasi atas nama kedua hal tersebut. Kuasa Pengetahuan Michel Foucault sudah dibuburi oleh bung Wahid, namun diri bung Wahid malah Power is Nothing.
Maka diri mbak Atun dan bung Wahid memberikan penegasan secara jelas. Ilmu pengetahuan mesti mempunyai standar moral. Wajib memiliki standar nilai. Ilmu pengetahuan tidak boleh diberikan kebebasan untuk menguasai dalam bentuk apa saja. Meskipun ilmu pengetahuan dapat memberikan kekuasaan dan dapat juga digunakan untuk menghegemoni dan mendominasi, akan tetapi mbak Atun dan bung Wahid tidak menggunakannya secara membabi buta baik di ruang publik maupun bilik domestik.
Nukilan di atas, sebenarnya sudah cukup kuat alasan kenapa saya mengakui bahwa mbak Atun dan bung Wahid ialah guru saya. Namun, setinggi apa pun ilmu pengetahuan, semua orang boleh mendapatkannya. Karena itu, di bawah ini, sedikit saya akan gariskan perkara yang tidak kalah penting dari ilmu pengetahuan. Jika ilmu pengetahuan ialah senjata, maka baik buruknya senjata sangat bergantung kepada penggunanya.
Luasnya pengetahuan mbak Atun dan bung Wahid, bagi saya hanya sebagian kecil dalam diri mereka yang lebih luas lagi, yakni kebaikan hati mereka. Karena itulah, saya ingin mengatakan kepribadin yang baik itulah kekayaan utama mereka. Ilmu pengetahuan yang luas tersebut hanya penghias, hanya rumbai, hanya pernak kecil dari kedalaman kekuataan karakter dan kebaikan pribadi mbak Atun dan bung Wahid.
Bahkan seandainya suatu ketika, mbak Atun dan bung Wahid melepaskan segala atribut ilmu pengetahuan tersebut, lalu mereka berkelana di tengah lautan sosial kemasyarakatan, mereka tetap diterima secara terbuka di mana saja dan oleh siapa saja. Sebab, mereka iala orang baik. Orang baik yang berilmu pengetahuan. Orang yang berilmu pengetahuan dalam kebaikan.
Perjumpaan saya dengan mbak Atun dan bung Wahid ialah karena buku, diskusi, dan gerakan. Pada saat awal itu, mereka sudah mapan secara intelektual, profesional, finansial sekaligus mapan emosional. Jauh kebalikannya dibandingkan saya yang masih ugal-ugalan, pengangguran, amburadul, miskin papa, dan liar bagai busur panah tak bertuan. Rumah mereka menjadi pelabuhan segala destinasi. Segala jenis orang berkumpul di situ.
Pendengar yang sangat baik itu ialah bung Wahid. Sekaligus pengkritik yang berhati bunga. Untaian lidahnya tersusun berbaris rapi sehingga siapa saja yang dikritik malah semakin akrab dengannya. Bukan tak pernah tersinggung. Sebagai manusia sisi kemarahan itu pasti ada, namun terkespresikan melalui saya. Sayalah yang mengganaskan kritik bung Wahid kepada apa dan siapa sebab bung Wahid memang sangat jauh dari kata dan kalimat api. Sering karena situasi itu, saya malah yang disejukkan bung Wahid, bukan subyek-obyek kritik.
Sejak awal saya mengenali mbak Atun dan bung Wahid sebagai intelektual dan keluarga NU yang sangat kental. Bahkan banyak konstruksi berpikir mereka terbangun dari budaya NU. Termasuk kesalehan sosial yang tercermin dalam perilaku. Cara mentertawakan realitas, politik, pergaulan intelektual, hingga praktik keagamaan mengakar kuat ke dalam budaya NU. Untuk itu sangat menarik saya nukilkan sekuen kecil ini.
Mbak Atun duduk di samping bung Wahid yang tersenyum nipis. “Mas Salman, Wali itu, saya tanya, siapa tokoh idola dan panutannya? Tanpa berpikir panjang, dia menjawab TGB.” Selanjutnya mbak Atun bercerita yang Wali, anak pertama mbak Atun dan bung Wahid telah berniat lama, sebelum berangkat ke Mesir, harus sowan-ngalap berkah dulu ke TGB. Karena mbak Atun berkenalan baik dengan TGB dan keluarga, ia pun menghubungi TGB terkait niat Wali tersebut. Dengan senang hati dan tangan terbuka TGB menyambut baik.
Sekeluarga, mereka akhirnya bershilaturrahim dengan keluarga TGB. “Wali, kamu mau seperti siapa?” tanya TGB kepada Wali. “Saya mau seperti TGB atau lebih baik dari TGB.” Mendengar jawaban Wali, TGB tersenyum dan berdoa yang terbaik buat Wali. TGB memberikan apresiasi yang mendalam kepada mbak Atun dan bung Wahid selaku orang tua dan kepada Wali yang bagi TGB, telah memilih jalan yang sangat tepat.
Mbak Atun dan bung Wahid ialah pribadi yang sangat luas. Terbuka atas segala kebaikan dari manapun dan siapa pun sumber kebaikan tersebut. Membuminya budaya NU dalam diri mereka, tidak menjadi sekatan untuk mengibas sayap pada setiap ruang dan waktu. Bahkan, boleh saya katakan, meski mereka orang mBojo, mbak Atun dan bung Wahid ialah di antara yang amat sedikit kaum terpelajar (bahkan dari kalangan Sasak sendiri) yang betul-betul memahami cara dan posisi kesasakan saya.
Hingga kini, dalam beberapa perkara, saya selurus dengan mereka namun tidak setanding dalam ilmu pengetahuan. Lebih tidak sebanding lagi dalam urusan kebaikan. Saya berhasil menjadi murid mbak Atun dan bung Wahid dalam hal tidak mendengki, tidak membenci, tidak juga beriri hati-hasad kepada siapa pun. Sekali lagi sangat berhasil, namun saya bukanlah siapa-siapa jika ditulik dari sisi kebaikan mereka. Mbak Atun dan bung Wahid, orang berilmupengetahuan di lautan kebaikan sedangkan saya hanya berpijak pada kerikil kecil di mangkuk sempit kebaikan. Karena itulah, meski saya berhasil mengorak langkah mereka dalam hal tidak membenci siapa pun meski seberbeda apa pun, namun masih ada yang anti kepada saya. Berbeda jauh dengan mbak Atun dan bung Wahid, nyaris amat terbatas orang kontra dengan mereka.
Di penghujung tulisan ini ingin dikemukakan. Jika kita pergi ke gurun tandus nan luas, kemudian berjumpa dengan gerombolan binatang lapar dan nan buas. Maka binatang tersebut harus memakan bung Wahid terlebih dahulu. Jika tidak, gerombolan binatang tersebut apes dan tidak dapat apa-apa. Sebab membiarkan bung Wahid kesempatan hidup akan membuat gerombolan binatang tersebut menjadi jinak dan baik hati lalu rela hati menjadi pengawal setia bung Wahid.
Ilmu yang luas berada pada diri orang baik, kebaikan dari langit sentiasa bercucuran.
Maka istiqomahlah jadi guru berasaskan kebaikan itu. Bukan mengajar karena Guru Besar itu.
Malaysia, 16 November 2022