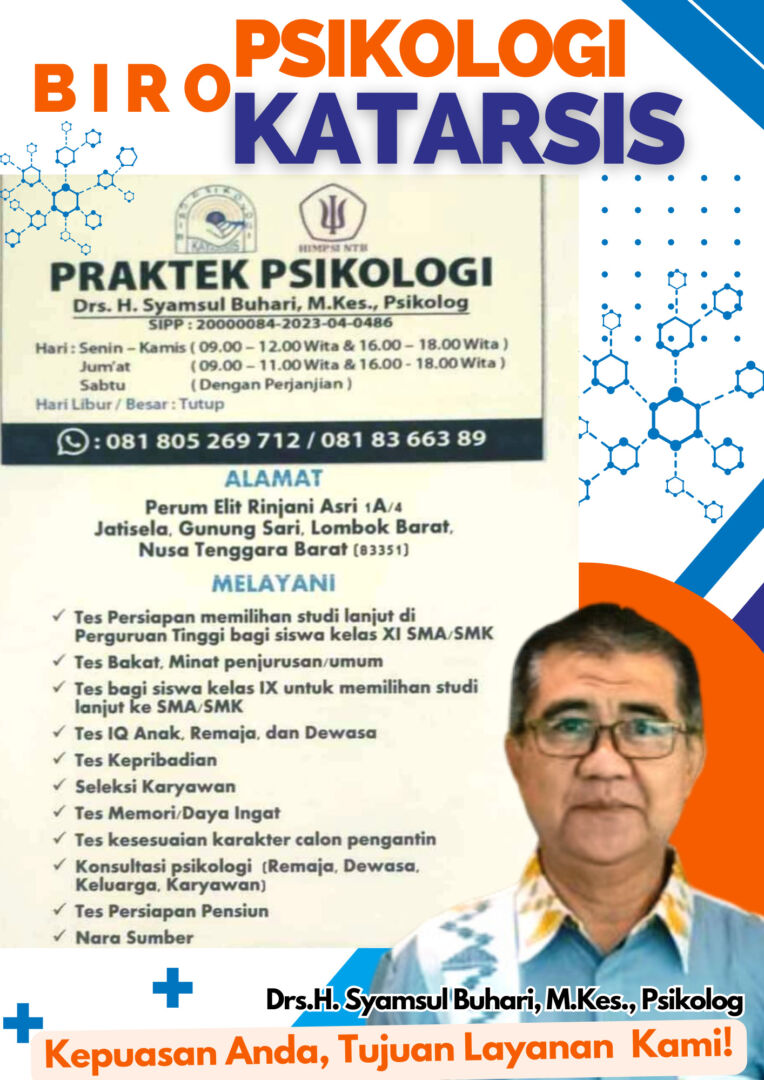Atika, nama yang cantik. Seindah kelokan air jernih di kelokan parit-parit kecil Desa Lenek. Satu desa yang cantik yang banyak juga melahirkan manusia cantik. Desa yang alamnya tidak miskin, bahkan, kalau saya membayangkan Lenek berada di Korea, ia akan setanding dengan Provinsi Jeju (Cheju-Cheju Do) yang memang segala hal berkaitan nasib dan hidup manusia didekatkan dengan alam. Dengan kata lain, karena alam kaya, maka seharusnya manusia hidup di atas kelayakan. Tak boleh ada kemiskinan di atas bumi yang melimpah ruah kekayaan. Tak boleh ada perampasan hak hidup layak di tengah kemerdekaan.
(Scene Satu)

Tak boleh ada orang kehausan di tengah dering air beraliran jernih macam di Lenek. Tak boleh ada tangis di tengah harmonisasi alam seharmonis alam Lenek. Namun sekali lagi, selalu ada penyimpangan, senantiasa ada perkara yang tidak terduga. Atika, ialah guratan lain dari keindahan alam Lenek. Ialah gugusan lain dari Lombok yang membuat orang luar jadi kaya raya berkuasa itu. Bintikan lain dari Nusa Tenggara Barat yang kadang maju kadang tenggelam itu, dan degup yang lain dari Indonesia yang, uuuuuuh, Indonesia. Ruwet deh.


Indonesia yang, disiram air tak basah-basah. Dipanas api tak kering-kering. Ruweeet-ruwet.
Atika, ialah tanda. Bukan tanda tanya. Tanda yang tak pernah hilang. Sebab kita tak pernah benar-benar secara tuntas menemukan makna tanda. Tak pernah mati-matian berusaha mendapatkan jawaban dari maksud tanda. Kita hanya bermain-main saja dengan tanda tersebut. Kita hanya berseloroh tentang Atika. Bahkan kita berdrama dalam diri Atika. Drama yang tanpa episode.
Seumpama lakonan absurd. Tidak jelas mana watak utama. Tidak jernih mana watak baik dan jahat serta watak penengah. Semua muncul sebagai pendrama. Kabur struktur yang mengakibatkan banyak orang mengemis-ngemis kepada pemerintah hanya untuk menyelamatkan Atika. Padahal kalau kita sungguh-sungguh manusia, Atika yang baru terhidup saja, kita terus mengambil tindakan, bersikap layaknya manusia. Ini malah Atika jadi tontonan.
Absurd sangat: tak jelas siapa pedagang dan pembeli manusia. Siapa pula yang melindungi dengan undang-undang. Semua sama saja.
Makin absurd, kita sebenarnya tahu siapa pedagang dan pembeli manusia. Kita paham siapa yang melindungi mereka. Namun keadaan tak berubah. Kejadian begitu-begitu saja. Luka terus berulang. Episode Atika bukan ending.
Sungguh menjadi komedi ketika, misalnya, ada lembaga yang tak henti-henti menggedor pemerintah baik melalui media atau menjumpai langsung sang pemerintah, hanya untuk keselamatan Atika. Padahal tanpa diminta pun pemerintah semestinya menunjukkan yang, mereka juga manusia. Tapi itulah komedi. Dalam komedilah kita dapat menyaksikan secara leluasa pemerintah memberaki wajahnya sendiri. Beruntung ada komedi, sebab di dalamnya kita dapat melihat pemerintah menghina-dina diri sendiri.
Atika, nama yang futuristik dalam budaya Sasak. Saya pastikan, tidak banyak yang bernama Atika, sebab orang Sasak mempunyai jurus yang lain dalam pemberian nama. Mungkin Atika dipanggil, Ati, Atik, atau Tika, atau juga Ika. Juga panggilan yang tak banyak di Sasak. Sudah pasti tujuan orang tuanya memberikan nama yang futuristik itu agar nasib Atika lebih baik dari orang Sasak kebanyakan. Lapar di lumbung padi. Terjajah di negeri sendiri. Pergi karena terusir nasib mujur orang asing.
Namun, nasib memang skenario rumit. Atika menemukan luka malah di negeri orang. Siapa yang salah?
Karena kita tidak mempunyai budaya tinggi dalam menghargai orang miskin. Malah sebaliknya, adat kita sangat adiluhung dalam menistakan orang miskin. Karena kita menganuti faham sadisnya kesenjangan ekonomi dan ketimpangan sosial. Maka, kita tidak boleh melarang Atika, melarang siapa saja meninggalkan tanah Lenek yang subur makmur itu.
Sebab Indonesia tak mampu menghidupi rakyatnya di tengah kelimpahan kekayaan alam, maka boleh saja moratorium tenaga kerja ke luar negeri itu berhukum haram. Sebab dampak keburukan moratorium tersebut jauh lebih besar dibandingkan kebaikan yang dihasilkan.
Sudah pasti tujuan Atika ke luar negeri ialah mengubah nasib. Pasti ada sebab yang Atika tak dapat tampik. Nasib buruk yang menimpanya ialah mimpi yang lain. Namun moratorium bukan solusi bagi negara yang memang sangat pandai menghambakan rakyatnya. Moratorium itu kutukan bagi orang yang terhina di negara sendiri, hanya karena mereka miskin.
Negara yang tak pandai melindungi kelompok miskin berkewajiban membuka peluang rakyat yang ingin mengais nasib ke luar negeri. Haram bagi negara meminta apalagi memaksa rakyat balik kampung jika kesenjangan kemiskinan yang menghina-dina kelompok miskin masih menjadi muka utama Indonesia.
Karena itu, ketika mereka menemukan nasib yang malang seperti Atika, tanpa perlu diminta siapa saja, pemerintah wajib segera bertindak.
(Hahahahahaha).
Namun begitulah pemerintah. Dalam kesengsaraan rakyat yang pahit pun, pertama kali yang dilakukan ialah: legal atau tidak legal. Pendatang haram atau halal. Gelap atau terang. Dalam penderitaan Atika yang kelam saja, pemerintah masih mengurusi dokumen. Otak pemerintah memang dokumen. Padahal merekalah yang sebabkan penderitaan itu.

Negara Indonesia memang penganut faham dokumentis. Maka dalam kesengsaran yang paling pahit pun, dokumen diutamakan. Pemerintah masih belum percaya seseorang ialah warga negara Indonesia jika kosong dokumen. Meskipun nyata-nyata sang warga berbahasa Indonesia. Punya logat khas lagi.
Nah, watak dokumen inilah yang membuat struktur penanganan penderitaan rakyat di luar negeri jadi berundang-undangkan dokumen. Bukan merujuk substansi penderitaan yang sedang gawat darurat itu. Bagi pemerintah, ketiadaan dokumenlah gawat darurat, bukan warga negara yang sedang sekarat karena kemalangan nasib itu.
Apakah dokumen penting. Sangat penting. Sekali lagi, sangat penting. Namun bagi mereka yang sedang digulitakan nasib, kesakitan atas nasib itulah dokumen utama. Atika sudah berbahasa Indonesia. Atika juga sudah berbahasa Lenek. Logat Lenek yang kental. Ingatannya tentang asal usul sangat jelas. Itulah dokumen yang hakiki. Itulah dokumen yang jauh lebih bermakna dibanding kartu identitas di tengah-tengah badai kesengsaraan.
Lucu, kan? Orang sudah tenggelam, masih ditanya, “ada KTP?”. Itulah watak Indonesia dalam penanganan darurat.
Ah, tapi sudahlah.
Samudera kritikan tentang cara penanganan penderitaan Atika yang dialamatkan kepada pemerintah, tidak akan mengubah watak dokumen pemerintah itu. Watak prosedur. Watak birokratis. Watak anggaran. Watak Undang-undang. Watak “saya dapat untung apa?”.
Tuhan saja tidak sebirokratis pemerintah.
Jadi sudahlah. Kalau Atika ada sayap, terbanglah. Kalau Atika ada sirip, berenanglah. Pulang sendiri. Itu lebih baik dibandingkan berharap pemerintah yang ujung-ujungnya semakin menghinakan nasib orang miskin itu.
(Scene Dua)
Seribu buku, bahkan lebih, tidak akan mampu menampung kisah kegelapan para pemburu ladang kehidupan di luar negeri. Kadang kita tertipu oleh segelintir dari mereka yang sukses. Dan kita lebih banyak abai kepada sebagian besar bertopang luka di gambut penderitaan.
Karena kita lebih suka tertipu, maka ketika segelintir orang yang sukses sebagai perantau itu dibesar-besarkan. Media berebut mengundang dan mempublikasikan. Didukung pemerintah yang memang memerlukan model sukses bagi para pengais nasib di negeri orang. Kita dan pemerintah sama saja, sama-sama bangga, bahagia, dan senang menumpang dalam perahu kecil kesuksesan segelintir perantau itu, dibandingkan menyelam di buritan dan lambung kapal besar kesengsaraan mereka.
Kita benar-benar munafik dalam banyak hal, termasuk yang utama ialah dalam pasal buruh migran.
Seandainya kita meminjam sejuta, bahkan lebih, lidah yang paling fasih berbicara untuk mengisahkan tentang kelam pahit getirnya menjadi perantau duit di luar negeri, itu tidak akan mampu menggoreskan lembaran dan jalanan panjang kekelaman yang setiap hari berlaku.
Namun kita lebih senang mendengar para agen, para lembaga yang mengaku sebagai pelindung. Bahkan kita lebih percaya kepada omong kosong kedutaan yang seribu persen berwajah pemerintah. Kita tahu, pemerintah ini kan ingin bersih. Ingin suci. Ingin nampak sebagai pelindung agung baik di mata rakyatnya sendiri maupun di muka dunia.
Apakah pemerintah tidak pernah berbuat baik kepada para perantau kepeng di luar negeri? Pasti sudah. Itu pasti. Namun sejuta kebaikan pemerintah itu hanya sedebu di tengah samudera kemalangan derita nasib Atika dan jubinan penderitaan yang masih tersembunyi.
Penderitaan yang belum terkuak sebab belum waktunya. Kesengsaraan yang belum mengemuka sebab ada kekuatan lain di atas kekuatan negara yang, mendapatkan remah berlimpah dari aliran kesengsaraan nasib para perantau yang tiada habis-habisnya.
Jadi, duhai Atika. Meski kamu ialah saya, meski kamu ialah kita. Saya tak mampu menolongmu dengan yang lain selain bersuara, selain melalui tulisan.
Apalah saya, siapalah kita di tengah-tengah kekuatan dan kejahatan yang diundang-undangkan yang, membuat kesengsaraan kita.
Yang pasti, niat kita tidak salah. Namun niat kiat telah salah digunakan.
Faham, kan Atika?
Malaysia, 21 Bulan Puasa 1442 H
foto utama: google image