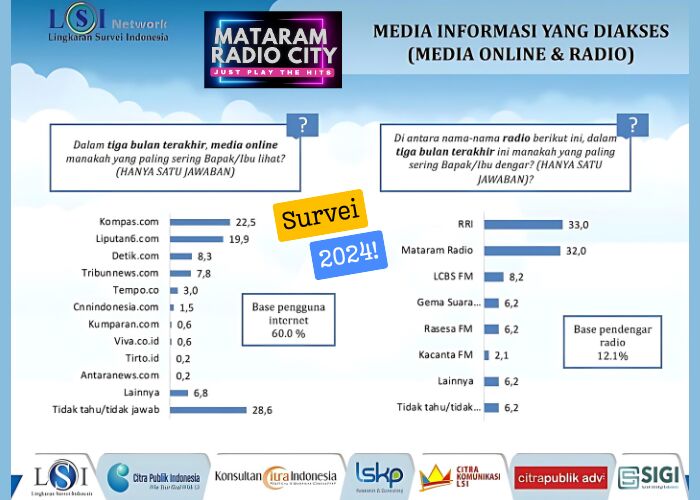Oleh: Buyung Sutan Muhlis
Sedikitnya ada tiga kekalahan saya ketika berhadapan dengan sosok lelaki uzur bernama Ncek Muhammad Nurdin.
Kekalahan pertama, saya tidak pernah menang menghadapinya bermain catur. Belakangan saya memperoleh keterangan, ia salah seorang pecatur tangguh di Ampenan di kurun waktu 1970-1980an.


Selisih usia saya dengannya sekitar 60 tahun. Ia meninggal di usia lebih dari 90 tahun. Tetapi hingga menjelang wafatnya, ia masih kuat mengendarai sepeda, dari Cakranegara ke Ampenan, bolak-balik.
Ke dua, saya kalah soal ketajaman penglihatan.
Saya punya masalah dengan mata sejak kecil. Mata saya minus. Sehingga saya selalu duduk di deretan depan agar bisa menyalin catatan-catatan guru di papan tulis.
Sementara Ncek Muhammad tidak pernah menggunakan alat bantu berupa kaca mata hingga akhir hayatnya. Matanya tajam. Tak pernah khilaf terutama ketika menghitung uang.
Ihwal menjaga kesehatan matanya agar senantiasa normal itu, Ncek Muhammad sempat berbagi cara terapi. Ini kiat ekstrem, yang tak akan pernah dianjurkan kalangan medis. Setiap bangun tidur, ia selalu membasuh matanya dengan air seni! Air kencing sendiri, tentunya. Dengan terapi itu, selain matanya tetap tajam, ia tak pernah satu kali pun menderita sakit mata.
Nah, yang terakhir, kekalahan ke tiga saya. Ini soal dunia laki-laki. Tentang sesuatu yang empirik, sejauh mana reputasi seorang laki-laki dalam menaklukkan hati wanita. Tetapi saya akan bahas ini di bagian akhir.
Saya jelaskan dulu sosok Ncek Muhammad. Ia pendatang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tahun-tahun pertama di Lombok, ia tinggal di Kampung Banjar, Ampenan. Ncek Muhammad telah empat kali menikah, tapi tak pernah berpoligami. Nasibnya kurang beruntung, karena tidak pernah lama menikmati kebahagiaan. Baru beberapa tahun menikah, istrinya meninggal. Lalu ia menikah lagi. Sama. Demikian seterusnya. Ketika istrinya yang ke empat dipanggil lagi oleh Sang Pencipta di awal 1980an, ia memutuskan tidak menikah lagi. Dari ke empat istrinya, Ncek Muhammad dikarunia sepuluh anak.
Ncek Muhammad punya profesi yang sangat prestisius. Ia seorang kleder. Bidang pekerjaan yang berurusan dengan pengiriman hewan ternak. Tugas utama seorang kleder mengurus dan merawat hewan-hewan sampai ke tujuan.
Sejak tahun 1940 hingga 1970an, Ncek Muhammad mengumpulkan puluhan hingga ratusan ekor sapi dari sejumlah wilayah di Lombok. Ternak-ternak itu ia berangkatkan melalui Pelabuhan Ampenan. Dengan profesinya ini sedikitnya dua kali dalam setahun ia menginjakkan kaki di luar negeri.
Hong Kong, wilayah bekas koloni Inggris, negeri tujuan ekspor sapi saat itu. Inilah masa keemasan Kota Ampenan, ketika para penduduk setempat memiliki peluang bepergian ke luar negeri terkait usaha ekspor langsung ke negara-negara tujuan.
Sekali berangkat, para kleder asal Ampenan berada di Hong Kong hingga tiga bulan. Pulangnya mereka membawa bermacam oleh-oleh. Diantaranya sepeda, arloji, jam dinding, dan radio transistor.
Tapi saya tidak terlalu tertarik membicarakan barang-barang bawaan itu. Ada yang lebih mengusik benak saya. Selama tiga bulan di Hong Kong setiap membawa ternak, saya tak yakin ia hanya jalan-jalan cuci mata.
“Pak, tiga bulan itu tidak sebentar. Masak tidak bosan jalan-jalan. Pasti Bapak punya bini di sana,” saya memancing-mancing.
Percakapan itu berlangsung pada pertengahan 1990an, di suatu siang.
Ncek Muhammad menatap saya tajam. Ia bukan tipe orang yang banyak bicara. Lama ia terdiam. Lalu terdengar juga suaranya. Pelan.
“Tidak. Saya tak ada istri di sana.”
“Masak. Saya tidak percaya.”
“Cuma punya pacar.”
Nah! Pertanyaan saya terjawab juga. Saya lalu mendesaknya untuk bercerita.
Ia hirup asap tembakaunya dalam-dalam. Ia kembali menatap saya seperti tadi. Di wajahnya masih tersisa ketampanan seorang lelaki etnis Banjar. Perawakan Ncek Muhammad tinggi ramping. Semasa muda ia gemar bermain sepak bola. Saya tak berlebihan jika mengatakan Ncek Muhammad tidak kalah ganteng dengan bintang-bintang Hong Kong. Sebut saja Andy Lau, Aaron Kwok, Michael Miu, atau artis lainnya. Ncek Muhammad juga berwajah Mandarin. Orang-orang kerap menyangka ia marga Tionghoa.
Tetapi, untuk menggaet gadis-gadis cantik Hong Kong, tentu tak cukup bermodal wajah tampan.
Di Hong Kong, kata Ncek Muhammad, para kleder dikenal sebagai kalangan berkantong tebal. Kendati demikian, kaum Adam tak bisa sekehendak hati menentukan pilihan.
“Tidak mempan rayuan di sana. Bukan kita yang memilih, tapi wanita-wanita itu. Kalau ada diantaranya yang tertarik, dia sendiri yang maju, lalu memegang tangan laki-laki yang dikehendakinya,” tuturnya.
“Kalau tangan sudah dipegangnya, lantas apa?”
“Itu berarti dia siap diajak jalan-jalan, nonton, atau ke mana saja.”
Ncek Muhammad bercerita, kebetulan seorang gadis cantik yang sejak awal ditaksirya, akhirnya memilihnya. Mereka menyusuri tempat-tempat indah di Hong Kong. Ke mana-mana berdua. Sepasang kekasih, seperti merpati. Saling menautkan hati, meski berbeda negeri. Tiga bulan tak terasa berlalu, putaran bumi seperti jarum jam yang bergerak terlalu melaju. Tibalah waktu berpisah. Derai tangis mengiringi kepulangan Ncek Muhammad yang kembali ke Ampenan.
Beberapa bulan kemudian ia muncul lagi di Hong Kong.
“Pasti Bapak mencari pacar yang dulu itu.”
“Kadinapa (mengapa, bahasa Banjar) mencari pacar lama?”
Astaga.
“Lantas?”
“Kita cari pacar baru lagi.”
Busyet! Saya memaki diri sendiri. Betapa jauh tertinggalnya saya dibanding kleder itu. Saya, yang lahir di masa moderen, hanya berputar-putar di pulau-pulau terpencil yang nyaris tak nampak di peta bumi. Dan, ternyata, saya hanya Don Juan regional, seorang playboy cap kambing dalam serial Lupus karya Hilman di tahun 1980an. Diam-diam saya mengalkulasi. Jika dalam setahun kleder itu berangkat dua kali saja, lalu kalikan dengan masa aktifnya sebagai kleder, taruhlah selama 20 tahun, maka ketemu angka 40. Sedikitnya 40 gadis Hong Kong telah ia pacari! Tiba-tiba saya lemas memikirkan itu. Saya kalah telak.(Buyung Sutan Muhlis)