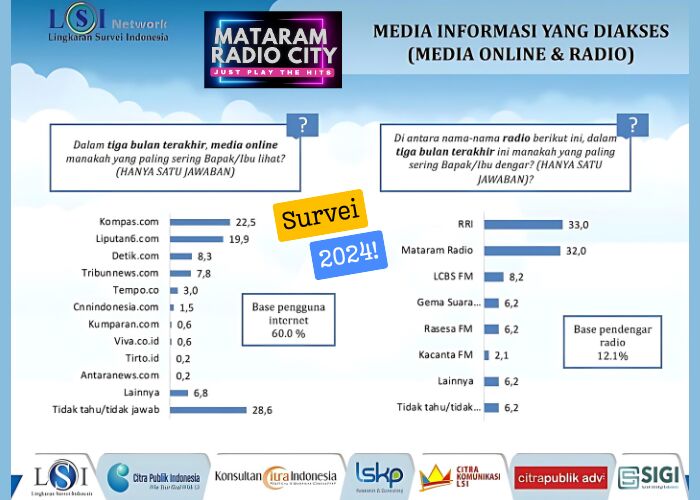Oleh: DR Salman Faris
Saya tidak tahu pasti, apakah tulisan ini salah alamat. Namun ketika darurat fitnah BIL ini semakin tak terkendali, di kepala saya hanya gubernur. Ya, gubernur NTB. Jika betul saya salah alamat, setidak-tidaknya saya tidak salah seratus persen. Dan yang lebih penting dari itu, mudah-mudahan saya tidak menulis fitnah.


Penolakan kesekian kalinya yang dilakukan masyarakat lingkar bandara pada tanggal 15 November 2020 terhadap kebijakan pemerintah mengenai BIL, bagi pandangan saya tidak boleh lagi dipandang biasa-biasa saja. Semua lapisan masyarakat di Indonesia sudah sangat jenuh dengan distabilitas sosial yang tiada habis-habisnya. Terutama karena kekeruhan sosial itu disebabkan oleh remeh temeh yang berujung pada fintah dalam bola liar yang memberikan risiko besar. Saya mengira, hal sama berlaku pada masyarakat NTB, khususnya masyarakat Lombok. Kemuakan sosial yang dirasakan oleh masyarakat, sekali lagi tak boleh dipandang remeh dengan pemerintah menganggap semua itu selesai dengan pembagian sembako.
Apa yang saya namakan sebagai darurat fitnah dalam konteks kisruh BIL ini mewujud kepada berseliwerannya fitnah satu sama lain. Pemerintah yang mungkin juga bertujuan baik, dituding bertindak semau-maunya oleh masyarakat. Masyarakat yang melakukan penolakan juga dituding oleh pemerintah sebagai gerakan yang ditunggangi oleh kelompok tertentu. Pihak yang menentang dipandang keras kepala, keras hati, bahkan jahil oleh pihak yang mendukung perubahan nama BIL. Begitu juga pihak yang menolak menilai pihak yang mendukung sebagai kelompok yang ambisius, angkuh, mau menang sendiri. Dan terakhir, Dinas Pariwisata NTB yang hanya menjalankan tugas itu pun dituding sebagai yang tidak tahu malu, tidak tahu diuntung, dan lupa daratan. Semua ini ialah kalkulasi fitnah yang bengis yang, jika diakumulasi secara sosial merupakan penggambaran situasi batin masyarakat yang amat letih, gerah, gulita. Masyarakat yang boleh jadi hampir kehilangan kepercayaan kepada satu sama lain dan kehabisan rasa hormat kepada legitimasi pemerintah. Sungguh, gubernur benar-benar tidak peka jika masih menilai situasi ini ringan dan dapat diselesaikan dengan siaran pencitraan yang juga tiada habis-habisnya itu.
Menurut hemat saya, kelindanan masalah di BIL itu bermuara pada dua lokus yang satu sisi tak berkaitan namun pada tepi yang lain, amat berkaitan. Pertama ialah kelompok yang menolak menilai yang, pergantian nama BIL ialah cacat prosedur. Bagi mereka, pengusulan yang dilakukan oleh pihak pemerintah NTB dan pihak lain yang berkepentingan ialah gegabah dan sewenang-wenang tanpa melalui mekanisme yang sesuai. Kedua, penolakan masyarakat tersebut disebabkan oleh faham alias isme alias aliran. Untuk yang kedua ini, saya merasa tidak etis mengutarakannya panjang lebar dalam tulisan ini. Namun secara umum saya memberikan gambaran yang, apabila sudah masuk ke wilayah faham, memang antara pihak yang menolak dan mendukung pergantian nama BIL tidak pernah punya faham yang sama. Baik faham yang menyangkut adat istiadat maupun faham teritorik. Kedua kelompok ini hidup dalam suasana kebatinan adat dan budaya yang berbeda. Dibesarkan dalam rukun keguruan yang tidak sama. Kedua hal ini kemudian saling berkelindan jika dasar penolakan tersebut ialah faham, ialah aliran. Karena aliran masing-masing kubu tidak sama, maka segala hal dapat ditumpangtindihkan atas nama penolakan atau dukungan.
Terhadap kedua kubangan masalah tersebut, bagi pandangan saya tidak dapat diselesaikan dengan jurus yang sama. Sekali lagi tidak dapat. Kedua hal tersebut berada di wilayah ontologis yang berbeda, maka secara epistemologis, ia harus ditangani dengan cara berlainan, meskipun, mungkin aktor penanganannya sama yakni gubernur. Untuk masalah prosedural, jelas ini merupakan wilayah hukum bertata negara. Dalam hal ini, gubernur berkewajiban di depan sebagai penyelesai. Jika benar apa yang dituduhkan oleh mereka yang menolak sebagai ada kesalahan prosedur, maka gubernur berkewajiban membongkar ulang kesalahan tersebut. Siapa dan atas nama apa pengusul tersebut. Adakah pihak yang mendukung pergantian nama terlibat sebagai pendorong utama pengusulan tersebut. Setelah itu, apakah mekanismenya sudah sesuai prosedur hukum bernegara atau tidak. Jika ya atau pun tidak, semua semestinya jelas, diterangbenderangkan agar tidak menimbulkan fitnah berkepanjangan. Jika mekanisme mendengar pendapat keterwakilan masyarakat ialah wajib dalam prosedur tersebut, lantas tidak dilakukan, maka dasar penolakan masyarakat lingkar bandara berpatutan. Namun jika tidak wajib, atas nama hukum bernegara, gubernur berkewajiban menjelaskan kepada mereka. Setelah itu, ada konsekuensi hukum bernegara dapat berlaku.
Jika masyarakat yang benar, gubernur wajib mengakui kesalahan prosedur dan bertekad menindaklanjuti pengusulan melalui prosedur yang benar. Jika masyarakat yang keliru memahami prosedur tersebut, gubernur pun berkwajiban menerapkan hukum bernegara. Kewenangan selaku pemerintah yang sudah diamanatkan undang-undang pun wajib dijalankan. Gubernur tidak elok lembek dan menunjuk bawahan berdiri di depan yang, akhirnya menjadi korban fitnah juga. Sekali lagi, untuk masalah prosedur yang digugat masyarakat lingkar negara ini, hukum bertata negara yang mesti menjadi payung. Dengan kata lain, jika prosedur sudah betul-betul benar sesuai undang-undang, ya, gubernur tak boleh lagi senyum-senyum di balik kelambu sambil menyaksikan masyarakat yang sedang saling tikam saling ancam karena fitnah salah sasaran.
Sedangkan untuk wilayah kerangkeng fitnah yang ditimbulkan oleh faham, oleh aliran yang berlainan antara pendukung dan penentang masuk dalam ranah adat istiadat. Jika ada norma yang wajib diterapkan, itu adalah norma adat. Masyarakat lingkar bandara beragumentasi yang mereka tidak dilibatkan dalam pengusulan dan pergantian nama BIL. Kemudian mereka bersumpah atas nama harga mati untuk mempertahankan nama BIL. Gubernur sebaiknya faham, ini ialah ekspresi adat. Sepintas nampak seperti bidang hukum bernegara karena substansi gugatan prosedur dan perasaan adat ditumpangtindihkan, namun sebenarnya ini ialah luahan adat istiadat. Dengan begitu, sekali lagi, secara epistemologis, ia mesti diselesaikan dengan cara adat. Menggunakan pendekatan hukum adat ialah kemestian.
Meskipun hal tersebut ranah adat istiadat, lantas siapa yang di depan. Ya tiada lain tiada bukan, gubernur. Sekali lagi gu-ber-nur. Namun dengan menerapkan nilai yang bersesuaian dengan adat yang diperlukan. Dalam hal ini, gubernur tak boleh langsung berbicara dengan bupati karena bupati tidak mempunyai kekuatan hukum adat. Karena ini berbicara adat, maka aktor yang termasuk di dalamnya ialah sesepuh, tokoh adat, tokoh agama, tokoh budaya, aktivis budaya, tokoh seni, tokoh guru dari kedua belah pihak. Mereka wajib dipertemukan untuk merumuskan faham yang berbeda guna mendapatkan kesamaan nilai. Jika benar masyarakat merasa dilangkahi, merasa tidak dihargai, merasa dipinggirkan secara adat, maka kesamaan nilai dalam masing-masing faham kedua belah pihak mesti dirumuskan secara adat pula. Jika masyarakat wajib tahu yang, aset di BIL itu bukan lagi milik mereka, bahkan bukan lagi milik pemerintah daerah, terangkan secara adat melalui medium perjumpaan keterwakilan tokoh tersebut. Mereka adalah orang beradat, mereka pasti faham mana yang hak dan mana yang bukan hak. Mereka juga faham ruang di mana hukum negara dan hukum adat dapat diaktualisasikan. Hanya saja, apabila dikomunikasikan dengan hukum negara, yang terjadi ialah perlawanan. Di situlah pentingnya kepekaan gubernur dalam memetakan bilik setiap permasalahan yang muncul terkait daruat fitnah BIL ini.
Jika kedua pendekatan tersebut yakni hukum bernegara dan adat istiadat sudah dijalankan dengan baik, namun, fitnah masih berlaku juga. Itu satu tanda bahwa masyarakat yang mengaku memiliki adat tersebut sebenarnya samasekali tidak beradat dan tak juga beradab. Sebab adat mereka adalah isme yang ujung-ujungnya fitnah. Terkait hal ini, gubernur lebih tahu, apa yang semestinya diperbuat. Namun jika gubenur tak jujur dalam prosedur hukum bernegara, masyarakat juga berhak menepuk dada.
Kenapa darurat fitnah BIL ini wajib diselesaikan? Salah satunya karena agar jamur kekeruhan sosial tidak terus bertumbuhan yang ujungnya-ujungnya kedaulatan sosial terganggu. Goal dari semua gangguan tersebut ialah musnahnya legitimasi gubernur. Apa gunanya punya jabatan gubernur kalau akhirnya tidak legitimate hanya karena soal sosial yang remeh temeh.
Memang semua orang faham yang, bukan hanya kisruh dan darurat fitnah BIL yang mesti diselesaikan di NTB ini, namun percayalah, jika gubernur tidak berhasil menuntaskan masalah ini secara cerdik, bersih, dan adil berkuntungan, boleh jadi periode kedua (jika gubernur masih mau lagi) tertiup angin. Terbang ke tangan orang lain.
Kalau tak percaya, buktikan saja.
Malaysia, 17/11/2020