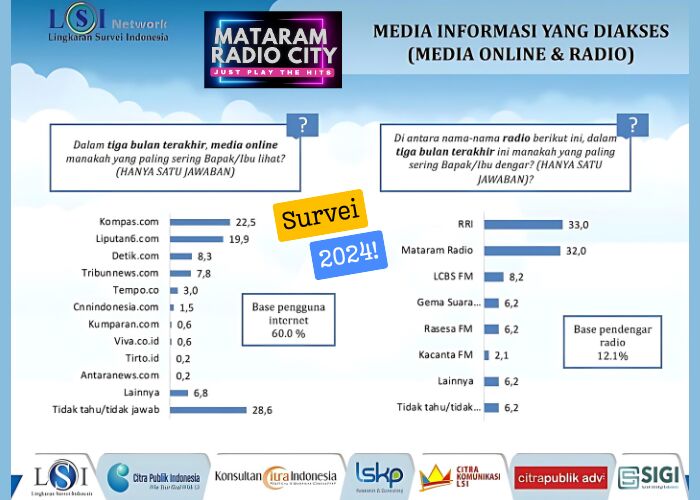Kalau merujuk kepada teori hierarki keperluan manusia yang dibuat oleh Abraham Harold Maslow (self actualization, esteem, love/belonging, safety, physiological), dapat saya pastikan bahwa semua perempuan yang meninggalkan kampung halaman dan orang-orang tercinta ialah karena terpaksa. Sangat terpaksa.
Jadi meski Anda sekalian belum mempunyai jalan keluar untuk menjawab penderitaan perempuan yang serba terpaksa itu, saya ingin mengabarkan tentang persentuhan saya dengan ratusan perempuan di rantauan yang, hebatnya semua sama. Sama-sama terpaksa pergi dari pertiwi yang konon kaya raya itu. Yang konon pemimpinnya lahir dari rakyat. Yang konon pemimpinnya ialah jelmaan ratu adil. Yang konon pemimpinnya blusukan itu. Negeri yang hampir semuanya konon, kecuali satu yang nyata: rakyat menderita. Banyak perempuan sengsara.


Setiap saya bertemu dengan perempuan “Indonesia” di rantau, baik di kebun, di bangunan, di kota, di kampung, bahkan di rest area, saya pasti menanyakan satu hal. Kenapa meninggalkan kampung halaman? Meskipun saya sudah tahu jawabannya. Namun itu ialah pertanyaan wajib. Untuk membuktikan bahwa saya tidak berprasangka kepada negara yang hampir sepenuhnya konon itu.
Ya, mereka meninggalkan kampung karena sangat terpaksa. Di kampung mereka tidak mendapatkan ruang yang cukup untuk mengaktualisasikan diri. Banyak keinginan mereka yang terbentur oleh keadaan. Sudah pasti kekurangan ekonomi, namun yang sering terabaikan ialah aktualisasi perasaan dalam bentuk hak kegembiraan. Hak tertawa. Hak bercengkrama secara leluasa. Hak berperasaan. Hak berfikir bahkan hak berimajinasi. Semuanya dirampas melalui sistem kejam bernama negara dan kampung.

Banyak faktor yang menyebabkan keperluan aktualisasi diri tersebut tersekat. Sekali lagi ekonomi sudah pasti. Selain itu ialah adat-budaya, bahkan agama. Untuk yang ketiga ini, mereka dapat terima sebagai satu nilai yang kadang memang bersifat absolut. Jadi, sikap tidak membantah ialah pelajaran sehari-hari. Akan tetapi, sistem ekonomi neolib yang sudah menusuk hingga ke kampung menjadi faktor yang susah disangkal. Baik di kampung maupun di kota sama saja: yang kaya makin kaya, yang menderita semakin miskin.
Karena sistem neolib begitu kuat, orang kampung yang sebelumnya bersifat tolong menolong jadi tak peduli kepada keperluan orang. Akibatnya, perempuan yang secara kebetulan berekonomi lebih bagus memamerkan aktualisasi diri secara berlebihan di tengah perempuan kebanyakan yang bertolak belakang. Maka jadilah perempuan yang kebanyakaan itu hanya dapat menelan ludah. Hanya dapat mencuci mata yang ujung-ujung menambah luka mata batin mereka sebab keperluan dasar mereka tidak terpenuhi secara baik.
Menariknya, adat-budaya, bahkan agama secara berangsung-angsur kompromi terhadap sistem yang ditawarkan oleh neolib tersebut. Adat-budaya tidak lagi peduli kepada perempuan yang menderita aktualisasi diri mereka akibat sebagain kecil perempuan yang mengaktualisasikan diri secara berlebihan. Agama pun lama-lama tak turut campur ketika sebagian kecil perempuan di kampung berlengak lenggok dengan perhiasan dan pakaian mahal di tengah rekan mereka yang digodam penderitaan.
(Sungguh satu ironi kejam ketika pejabat datang ke kampung, berjumpa dengan masyarakat bawah dengan riang gembira mengenakan pakaian dan perhiasan serba mahal. Apakah hati nurani mereka sudah mati? Membuat perempuan tak berdaya itu bermimpi tentang perhiasan pejabat yang tak mungkin mampu mereka miliki ialah kekejaman simbolik)
Tumbuh dendam pada diri perempuan yang bernasib kurang beruntung tersebut. Namun sayang sekali, mereka tidak mempunyai modal. Mereka tak mempunyai akses kepada sumber-sumber ekonomi di kampung. Maka pilihan satu-satunya ialah meninggalkan kampung. Jadi sebab mereka meninggalkan kampung ialah karena di kampung yang dulu toleran dalam segala aspek sudah berubah kejam setelah perpaduan kompromis antara adat-budaya dan agama dengan sistem neolib. Adat-budaya dan agama pun akhirnya berpihak kepada sosial tinggi dengan membenarkan sistem nilai kampung berubah menjadi sistem pasar dan gaya hidup ala kota. Mereka tak lagi mengatur masalah dasar kaum perempuan tertindas, perempuan marhaen demi menjaga hubungan dengan neolib: neoliberalisme agama. Neoliberalisme adat-budaya.
Jelas, perempuan yang meninggalkan kampung tersebut tidak lagi mempunyai pembela. Di kampung tak ada lagi prinsip komunitas, tidak ada lagi dasar-dasar komunalitas. Semua serba plastik. Semua serba cermin halus yang hanya memperlihatkan kegembiraan palsu melalui kepemilikan motor, mobil, televisi, pesta, dan gaya hidup hedonistik yang lain. Sayang sekali, adat-budaya di kampung mereka pun telah menjadi hedonistik.
Karena kampung juga sudah menjadi hedonistik, jadi sumber penghargaan orang lain kepada seseorang tidak lagi karena perempuan tersebut rajin mengaji, rajin sholat berjamaah ke masjid, baik budi pekertinya. Melainkan karena perempuan memiliki simbol materialistik. Mulut perempuan kampung sudah dihiasi oleh rumpian mall besar di kota, make up fantasi, dandanan artis, riak kafe. Sepatu beralas tinggi. Bukan terompah.
Situasi tersebut membuat kebanyakan perempuan di kampung tidak mendapatkan penghargaan. Mereka tidak dapat memiliki simbol harga diri seseorang. Dapat dibayangkan, betapa rendahnya derajat kebanyakan perempuan di mata sebagian kecil perempuan yang lain hanya karena pergi ke sawah, pergi ke ladang. Berjemur di bawah terik matahari. Lalu jika pun dapat menonton televisi, hanya yang channel gratis yang, dipenuhi iklan sampah, perusak negara itu. Sedangkan perempuan kampung yang terpapar virus hedonistik tersebut mampu membayar netflix.
Ditambah lagi adat-budaya dan agama yang kompromistis itu, tidak lagi meletakkan daya juang perempuan petani, peladang, perempuan buruh, perempuan pekerja kasar sebagai suri tauladan yang baik. Adat-budaya dan agama berperan besar dalam menelantarkan mereka dengan membuat definisi-definisi palsu tentang kemajuan yang sudah dikonstruksi oleh sistem neolib. Jadi sudah pasti, perempuan pekerja keras, ulet, teguh dalam alur mengubah nasib dan bertahan hidup itu menjadi orang lain di garis sosial yang besar. Dengan begitu, mereka pun kehilangan penghargaan diri. Padahal, merasa dihargai atau mendapatkan penghargaan serta penghormatan yang layak ialah keperluan dasar bagi siapa saja, seperti yang dikatakan Maslow. Sekali lagi, lari dari kampung yang semakin menjerumuskan itu ialah jalan satu-satunya. Pahit.
Seterusnya, pergaulan sosial, di kampung pun saat ini sangat mahal. Jika dahulu hanya dengan sebuah sisir rambut, begitu banyak perempuan dapat memetik kegembiraan. Mereka bercengkrama sambil menunggu giliran rambut disisir. Tertawa lepas. Jarang yang mengukur dan menilai pergaulan sosial dari kepemilikan benda secara eksklusif. Perempuan yang satu punya kacang tanah, yang lain punya biji asam, dan yang lain punya jagung kering. Mereka berkongsi, berbagi dalam keceriaan sambil saling menyisir rambut, pun dalam kesetaraan.
Kini, adat-budaya dan agama tidak lagi melihat itu sebagai standar mulia dalam pergaulan sosial kaum perempuan. Malahan, kacang tanah yang diporduksi di ladang oleh tangan kuat perempuan, biji asam yang diolah oleh perempuan kretaif, dan biji jagung kering yang disulam menjadi makan renyah dipandang sebagai kelas rendah. Bahkan kadang dinilai tak punya kelas samasekali. Adat-budaya dan agama memberikan nilai kebenaran untuk kaum perempuan menghabiskan waktu di depan televisi, mall, mini market yang, kesemunya itu telah membentuk satu demarkasi yang kuat antara perempuan kampung yang hebat dengan perempuan telivisi yang rapuh. Anehnya, meski perempuan televisi tersebut mengalami kerapuhan, adat-budaya dan agama malah berkompromi dengan neolib untuk memberikan kebenaran yang, perempaun televisi ialah kemajuan.
Adalah satu kekejaman jika adat-budaya dan agama sudah terlalu otoritatif dalam urusan mengklasterisasi penderitaan dan kebahagiaan perempuan berdasarkan standarisasi rekayasa neolib.
Akibatnya, ruang sosial yang sudah mengakar sebagai sumber pergaulan sosial yang setara bagi setiap perempuan lenyap begitu saja. Banyak perempuan yang tidak mempunyai ruang pergaulan sosial karena tidak memiliki banyak modal ketika pergaulan sosial tersebut telah dikapitalisasi hingga ke kampung terpencil sekalipun. Banyak perempuan kampung yang dibenarkan oleh adat-budaya dan agama untuk membuat perkumpulan motor yang, hanya perempuan yang memiliki motor sebagai anggotanya. Sedangkan mereka yang sebaliknya, terpaksa merasa terasing dari pergaulan sosial yang kejam itu.
Sudah tentu, jika perempuan tidak memiliki ruang yang layak untuk mengaktualisasikan diri, tidak mendapatkan penghargaan yang baik, dan memiliki ruang pergaulan sosial yang sempit di kampung mereka sendiri, mereka sudah pasti tidak mendapatkan jaminan keamanan. Dalam doktrin neolib, keamanan hanya diperuntukkan bagi kelas sosial tinggi, keamanan menjadi mahal, berbayar dengan tarif yang sudah ditentukan pula.
Pelecehan yang dialami oleh perempuan yang dipandang sosial rendah dinilai sama rendahnya dengan pelecehan yang mereka alami. Berbeda dengan perempuan sosial tinggi, terhantuk kerikil pun, jika mereka merasa dilecehkan, hal tersebut dapat berujung di ranah hukum.
Rasa selamat, rasa aman, rasa dilindungi tidak lagi bersifat kelompok. Semua itu telah berubah menjadi privat. Perempuan yang mempunyai duit lebih banyak membentengi diri dengan keamanan yang lebih sedangkan mereka yang lemah secara ekonomi harus berjuang sendiri untuk keselamatan mereka sendiri. Menariknya, untuk rasa selamat ini pun, adat-budaya dan agama melakukan kompromi dengan neolib seolah mereka setuju menelantarkan perempuan sosial bawah untuk menjaga keselamatan mereka sendiri.
Hal yang sama dalam keperluan perempuan yang bersifat fisiologis. Adat-budaya dan agama sering nampak sangat kejam. Ruang publik semacam tempat berolah raga seolah-olah hanya disediakan untuk lelaki dan perempuan sosial tinggi. Lapangan voli, misalnya, harus memakai seragam olah raga. Untuk hal ini sudah pasti berbayar. Bagi perempuan sosial tinggi sudah pasti mampu. Dan untuk menyekat keperluan fisiologis perempuan sosial bawah, mereka memutuskan seragam berkualitas tinggi dengan harga yang mahal. Anehnya, adat-budaya dan agama kadang nampak samasekali tidak punya kepedulian terhadap perkara ini.
Perkumpulan joging sudah masuk ke kampung. Bahkan lacurnya, negara berperan besar dengan membuat senam nasional semacam poco-poco sebagai gaya hidup. Padahal untuk satu kali senam poco-poco, berapa biaya yang diperlukan. Bagi perempuan yang tidak mampu membeli seragam, sudah pasti paling istimewa akan menjadi penonton dan penepuk sorak. Jika tidak, mereka mengurung diri dalam rumah pengap kemiskinan mendekap hati yang terluka sebagai perempuan yang tidak diakui ruang sosial fisiologis.
Narasi di atas menggambarkan betapa negara tidak menjaminkan ketersediaan hierarki keperluan bagi setiap warga. Pembangunan, hukum, sistem ekonomi, bahkan pendidikan yang disebut sebagai ladang pencerahan pun (komedi kampus merdeka), telah bias menjadi ladang pembumihangusan kemanusiaan karena pada akhirnya tidak semua orang dapat mengaktualisasikan diri. Tidak semua masyarakat mendapatkan rasa dihargai, rasa selamat. Tidak semua manusia mendapatkan ruang pergaulan sosial yang memadai dan kebanyakan mereka terkungkung secara fisiologis.
Perampasan lima keperluan dasar manusia tersebut ialah bentuk utama dari sebuah negara yang dikendalikan neolib. Meski negara tersebut mendeklarasi diri sebagai negara paling demokrasi sekalipun, jika manusia terbelah ke dalam jarak sosial yang kejam, maka demokrasi yang dimaksudkan itu ialah tak lain sebagai wajah pengabsahan neolib.
Apakah perempuan yang terpaksa meninggalkan kampung menuju negara lain tidak menjumpai situasi yang sama? Tentu saja sama. Karena kebanyakan negara di dunia telah menjadi sumber kekuasaan neolib. Namun sekurang-kurangnya mereka dapat pengalaman yang lebih baik.
Misalnya perempuan yang datang ke Malaysia, jika di kampung mereka direndahkan hanya karena menjadi pemetik sayur di ladang, di Malaysia mereka dibayar. Meski tetap saja dipandang rendah oleh tauke, namun setidak-tidaknya mereka dibayar. Beda halnya dengan di kampung. Mereka direndahkan serendah-rendahnya sekaligus tidak mendapatkan bayaran.
Karena itu, perempuan yang terpaksa meninggalkan kampung tersebut tidak pernah mempunyai pilihan yang lebih baik. Selalu terjebak dalam pilihan yang serba sulit. Namun dengan datang ke Malaysia, dalam kondisi sering mendapatkan pelecehan, namun setidak-tidaknya mereka dapatkan ruang aktualisasi diri yang lebih baik. Mereka merasa mempunyai hak sekaligus kewajiban. Dengan sedikit uang yang mereka dapatkan, mereka dapat menikmati kemajuan yang lebih baik dibandingkan kampung bahkan negara asal mereka.
Meski mereka bekerja di ladang, di kebun sawit, dan tinggal di rumah sempit, namun di Malaysia mereka dapat menikmati ruang terbuka tanpa berbayar. Mereka dapat olah raga, dapat duduk di taman yang tersedia baik di tengah kota maupun di kampung paling terpencil. Bahkan mereka dapat membeli motor karena motor di Malaysia harganya jauh lebih murah dengan di negara asal meski merek motor sama.
Sekali lagi, sebagai perempuan pekerja, apakah mereka tidak tertindas di rantau? Apakah mereka tidak mendapatkan pelecehan yang mengerikan? Tentu saja mereka dapatkan semua itu, namun meski negara tujuan sangat neolib, setidaknya sistem negara masih memberikan keberpihakan kepada mereka yang dilemahkan.
Apa artinya semua itu? Di negara yang konon pemimpinnya merakyat itu, di negara yang serba konon itu, selain berwatak neoliberalisme juga sangat kejam kepada rakyat. Termasuk kepada perempuan. Bayangkan saja, kalau negara yang serba konon itu alfamart membunuh semua sumber ekonomi rakyat marhaen, di Malaysia mini market dapat bersanding dan bersaing dengan kedai runcit, toko sembako baik di kota maupun di kampung.
Jadi, jelas perempuan yang terpaksa pergi itu karena negara mereka ladang penderitaan. Ditambah adat-budaya dan agama yang terlalu banyak terlibat dalam keleliruan negara.
Lacurnya, penderitaan kaum perempuan yang dikategorikan sosial bawah itu tak akan berpenghujung karena standarisasi kebahagiaan manusia ciptaan kaum neoliberaliasme terus berevolusi layaknya handphone dengan merek sama namun seri handphone terus berganti.
Berharap itu sebaiknya pada siapa?
Malaysia, awal Zulhijjah 1442 H.
llustrasi foto: google image