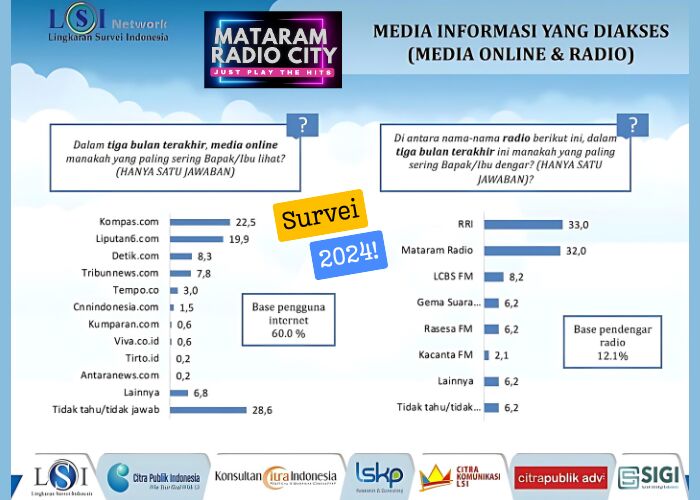Oleh: DR Salman Faris
Saya sering tertanya-tanya dengan perempuan yang memosisikan diri sebagai pejuang perempuan. Mendongak dunia namun tidak menunduk melihat pijakan kaki. Mencerna nasib di tumit mereka lalu menelaahnya secara mendalam sebagai satu kesanggupan melawan keadaan. Karena mereka senangnya mendongak langit, akhirnya rujukan perjuangan jauh dari ujung jemari kaki tempat bau tanah mereka ciumi. Orientasinya barat seolah terbenamnya matahari menandakan semua waktu dan peristiwa ialah indah dan romantik di barat sana. Malangnya, mereka hanya melihat perempuan sebagai tanda yang berbeda dengan lelaki, kemudian memosisikan diri sebagai penanda yang menerjemahkan petanda dalam posisi sebagai lawan lelaki. Terutama sekali mereka yang beraliran gerakan perempuan ekstrim. Watak ini, hampir sepenuhnya barat yang, secara gegabah menolak definisi dan pemaknaan futuristik Islam: Semua manusia, bahkan seluruh makhluk setara di hadapan Tuhan. Pembedanya ialah tingkah laku.
Saya faham mereka terpelajar. Namun apakah perempuan terpelajar tidak mempunyai bau tanah? Dalam sisi yang ini, saya ingin mengatakan kebanyakan mereka lebih senang menunjukkan diri sebagai pejuang udara, bukan sebagai pejuang tanah yang mereka pijak. Tanah tempat mereka dilahirkan sebagai air mata. Karena itu, saya sering juga geram. Adakah mereka sudah membaca Dende Aminah, perempuan yang berjuang dari dalam Puri agar rakyat Sasak dapat hidup sebagai manusia setelah ratusan tahun dirampas kemanusiaan mereka. Adakah mereka mengenali secara mendalam Dende Bini Ringgit yang membunuh Jenderal Van Ham ketika perang mempertahankan kehormatan. Adakah mereka sudah membaca Babad Praya yang menceritakan betapa hebatnya pejuang yang jumlah hanya beberapa orang itu namun bisa bertempur habis-habisan dan hampir mengalahkan musuh yang ribuan jumlahnya? Mereka kemungkinan tidak tahu siapa di balik kehebatan pejuang itu. Dia adalah perempuan misterius yang selalu datang mengantar makanan untuk pejuang. Semakin misterius karena makanan tersebut membuat pejuang merasa tidak pernah merasakan lelah sehabis menyantap: Dari tangan perempaun misterius itu tumbuh berkecambah azimat tak henti-henti.
Apakah mereka mengenali secara mendalam Doyan Nede yang menunjukkan betapa perempuan bernama Dewi Anjani sebagai pusat kosmologi Lombok. Atau saya sangat ragu mereka tahu Dewi Rengganis dalam dunia pewayangan Sasak yang mempunyai pengaruh melampaui kehebatan lelaki sebagai yang terdepan dalam politik dan yang utama dalam juru taktik perang. Atau tidak usah jauh-jauh, saya sangat tidak yakin mereka mengenal secara mendalam Siti Maryam Salahuddin, perempuan Bima yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa perempuan itu hebat dan kuat. Menariknya, perempuan yang saya sebutkan tersebut lahir dari kosmologi Lombok Sumbawa. Mereka dikonstruksi secara sadar dan total dalam bingkai filosofis yang jauh dari barat. Etika perjuangan mereka sepenuhnya produksi lokal namun menghasilkan bentangan nilai yang tidak secara ekstrim mempertentangkan jenis kelamin dan posisi lelaki dan perempuan. Perjuangan mereka ialah kemanusiaan. Siapa pun manusia ialah bagian dari perjuangan yang dilaburkan. Dan mereka tak perlukan gelar feminis.



Kalau hal-hal di atas mereka tak kenali, apalagi tokoh-tokoh perempuan dalam novel saya. Saya yakin mereka tak tahu siapa Papuq Odah dalam novel Tuan Guru. Seorang belian beranak yang membantu persalinan setiap anak di puluhan kecamatan di Lombok Timur. Termasuk membantu kelahiran seorang Tuan Guru yang kemudian menjadi lawan hanya karena berbeda cara memahami hidup. Namun apa yang menjadi kemenangan Papuq Odah, tidak meminta terima kasih dan balas jasa. Ia juga tidak membenci mereka yang memusuhinya. Tidak membalas kebencian Tuan Guru. Cukup Papuq Odah mengatakan, kebencian hanya dipunyai oleh mereka yang tidak cukup ilmu dan tak kuat iman meskipun mereka dipanggil Tuan Guru.
Mereka juga tidak mengenal tokoh perempuan yang melahirkan Guru Onyeh yang sanggup memeras dan mengubah batu jadi air susu hanya untuk sebuah tujuan hidup di masa depan yang lebih besar. Perempuan yang mempersiapkan anaknya menjadi pengubah zaman. Pasti mereka juga tidak mengenal tokoh Sumar dalam novel saya Guru Dane. Perempuan yang memilih jalan paling pahit pada masanya hanya untuk menyelamatkan orang Sasak dari keterjajahan yang panjang. Mereka pasti menolak tokoh Zippora dalam novel Perempuan Rusuk Dua yang saya tulis bersama Eva Nourma. Perempuan yang melakukan perlawanan terhadap feodalisme dengan cara kiri. Berhadapan dengan risiko terburuk ialah jalan nasib karena menjadi perempuan sudah jalan kepastian. Mereka juga tidak mengenal tokoh Sriri dalam novel Sri Rinjani yang ditulis Eva Nourma. Perempuan yang meletakkan hakikat perempuan sebagai bendera perjuangan. Sekali lagi ini ialah perempuan bentukan timur.
Saya tidak hendak ingin membawa pejuang perempuan pendongak langit itu berkitab kepada mitos. Tapi sekurang-kurangnya seperti ini. Pertama, ada masalah yang sangat besar dalam sistem kebudayaan di mana perempuan NTB ini berjuang. Sistem kebudayaan yang sudah berjalan ratusan tahun. Bekerja membentuk bawah sadar semua manusia NTB. Sistem yang juga dibentuk dari salah satu unsurnya ialah sejarah, legenda, dan mitos yang membiak di tengah masyarakat. Begitu bermasalahnya sistem tersebut, berdampak kepada budaya “menerima” sebagai solusi akhir menghadapi masalah yang ada: stoikis. Bukan perempuan Sasak tidak tahu siapa diri mereka, namun sekali lagi, sistem kebudayaan mempertanyakan mereka: siapa mereka? Nah, ketika perempuan disubjekkan ke dalam siapa mereka, maka begitu banyak masalah yang dapat dijumpai dan kebanyakannya terletak pada sistem kebudayaan yang terpaksa mereka jalani. Lalu jika sistem kebudayaan sebagai satu masalah pangkal, kenapa perempuan pejuang mengabaikan kebudayaan ini. Mereka asik membuat propaganda, kampanye, agitasi, dan hal-hal sejenis, namun mereka tidak masuk sedalam-dalamnya ke wilayah paling menyakitkan perempuan, yakni sistem kebudayaan yang mereka warisi. Misalnya, dalam sistem kebudayaan itu mereka diposisikan sebagai penyusui bukan sebagai manusia yang memproduksi susu. Penyusui ialah subordinat dari produksi susu. Ia adalah opisisi biner dari produksi susu. Susu yang dihasilkan dari tubuh mereka sendiri diakuisisi secara hegemonik oleh sistem kebudayaan mereka sehingga susu tersebut menjadi altar kekerasan simbolik dalam sistem kebudayaan yang mendera.
Hal di atas nampak sepele. Hanya berupa sistem tanda bahasa yang biasa, namun dampaknya dalam membuat sistem kebudayaan telah melahirkan perempuan-perempuan yang terdidik namun menerima diri sebagai bagian dari sistem kebudayaan nerimo. Kedua, saya ingin melihat perjuangan perempuan ini lebih membumi. Lebih berdarah daging. Kenapa? Karena jika perjuangan perempuan ini dilekatkan dengan negara, dengan pemerintah secara penuh, maka perjuangan itu adalah nihil. Wong negara, wong pemerintah kadang banyak menjadi muncikari dalam penderitaan perempuan kok. Lalu jika perjuangan perempuan ini bersanding dengan muncikari, bagaimana jadinya jalan juang itu? Bukankah akhirnya semua menjadi muncikari karena pada akhirnya pejuang perempuan hanya bisa menolong diri mereka sendiri. Sedangkan perempuan yang lain masih menari telanjang dalam penderitaan berabad-abad. Jadi, bagi saya, perjuangan perempuan ini tidak pernah beranjak dari level elitis. Hanya turun satu undak ke permasalahan mendasar lalu kembali lagi ke level elitis. Dengan kata lain, menjadi pejuang perempuan itu “enak”. “Nikmat”. Tidak segetir Dende Aminah, Dende Bini Ringgit, Sumar, Papuq Odah, Sriri. Karena dia “enak”, maka perjuangan perempuan hanya menghasilkan candu.
Karena ia candu, maka ia akan terus-menerus memproduksi masalah untuk memabrik candu-candu yang lain seperti sertifikat, penghargaan, dan kehormatan individu.
Jadi, tak perlu mesti menjadi feminis untuk memperjuangkan perempuan. Diperlukan perjuangan dari akar umbi.

DR Salman Faris
adalah Akademisi, Pekerja Seni Budaya dan Pemerhati Sosial Politik dan Media. Kini tinggal di Kuala Lumpur Malaysia.