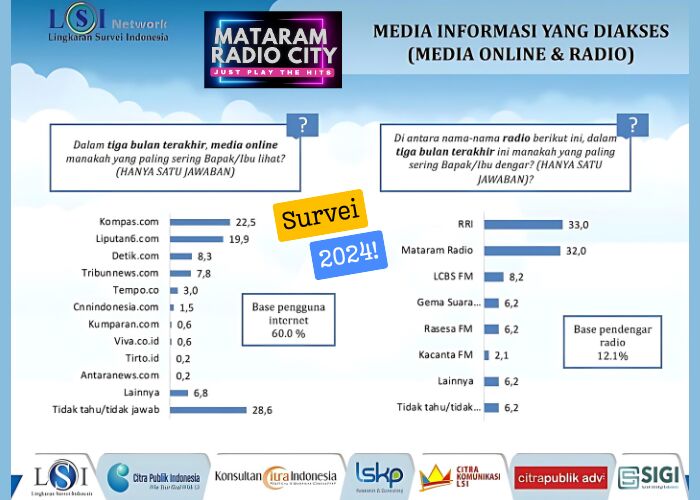Oleh: Muhammad Azzuri S.Pd/Pegiat Sosial – Alumni Universitas Mataram
Proses seleksi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) belakangan ini menjadi perhatian luas publik. Secara formal, mekanisme seleksi telah dijalankan sesuai ketentuan melalui tahapan administratif, asesmen kompetensi, penulisan makalah, serta wawancara oleh panitia seleksi. Namun, muncul dan menguatnya istilah “Sekda impor” di ruang publik menandakan bahwa persoalan ini tidak berhenti pada aspek prosedural. Ia telah bergerak ke wilayah yang lebih mendasar: kepercayaan, simbol kepemimpinan birokrasi, dan martabat sosial daerah.
Dalam persepsi publik, wacana Sekda dari luar daerah kerap dimaknai bukan semata sebagai pilihan teknokratis, melainkan sebagai sinyal berkurangnya kepercayaan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) internal daerah. Tafsir sosial ini berkembang menjadi kesan bahwa ASN lokal, khususnya pejabat eselon II dianggap belum cukup layak atau belum sepenuhnya dipercaya untuk menduduki jabatan puncak birokrasi provinsi. Benar atau tidak secara faktual, tafsir ini telah menjadi realitas sosial yang memengaruhi emosi kolektif dan membentuk opini publik.


Dari sudut pandang sosiologi birokrasi, jabatan Sekda tidak hanya dipahami sebagai posisi administratif. Ia adalah simbol puncak karier ASN daerah, hasil dari proses panjang pengabdian, pengalaman, dan pembentukan kapasitas kepemimpinan dalam konteks lokal. Karena itu, ketika posisi simbolik ini diisi oleh figur dari luar daerah, kegelisahan publik menjadi sesuatu yang wajar. Yang dipersoalkan bukan semata kompetensi individu, tetapi bagaimana simbol dan martabat birokrasi daerah diperlakukan.
Teori birokrasi modern Max Weber menekankan pentingnya merit, profesionalisme, dan rasionalitas dalam pengisian jabatan publik. Namun Weber juga mengingatkan bahwa birokrasi tidak pernah bekerja dalam ruang sosial yang hampa. Ia selalu beroperasi dalam konteks budaya, nilai, dan ekspektasi masyarakat tertentu. Rasionalitas formal yang sah secara aturan dapat berbenturan dengan rasionalitas sosial yang hidup di tengah masyarakat. Dalam konteks NTB, proses seleksi yang legal dan transparan belum tentu sepenuhnya diterima jika tidak disertai kepekaan terhadap dimensi kultural dan psikologis masyarakat daerah.
Birokrasi NTB tumbuh dalam masyarakat yang memiliki ikatan kultural kuat dan rasa memiliki tinggi terhadap institusi publik. Ketika SDM lokal yang telah lama mengabdi tidak memperoleh ruang pada jabatan strategis, muncul kesan bahwa jalur karier birokrasi daerah kehilangan makna simboliknya. Dampaknya bersifat sistemik: menurunnya motivasi kerja, melemahnya loyalitas institusional, serta terkikisnya kebanggaan ASN sebagai pelayan publik daerah.
Fakta seleksi justrumenunjukkan bahwa NTB tidak kekurangan SDM unggul. Mayoritas kandidat Sekda berasal dari lingkungan ASN internal: tujuh pejabat eselon II Pemprov NTB dan satu pejabat eselon II Pemkab Bima. Mereka adalah figur-figur yang telah lama berkarier, memahami anatomi birokrasi daerah, serta terbukti menjalankan tugas dengan prestasi sesuai bidang masing-masing. Fakta ini menegaskan bahwa narasi “ketiadaan SDM lokal yang layak” tidak sejalan dengan realitas objektif birokrasi NTB.
Justru karena itulah, menguatnya opsi figur dari luar daerah memunculkan pertanyaan substantif: bukan tentang transparansi seleksi, melainkan tentang arah kepercayaan strategis pimpinan daerah. Publik membaca pilihan tersebut sebagai pesan implisit bahwa kapasitas, kesiapan, atau kecocokan ASN lokal belum sepenuhnya diyakini untuk mengelola kompleksitas birokrasi provinsi atau bahkan mungkin ada kepentingan lain dibalik itu. Tafsir inilah yang melahirkan kegelisahan sosial, bukan karena proses seleksi dianggap cacat, tetapi karena pilihan akhir dipersepsikan mengabaikan potensi internal daerah.
Meritokrasi sejati tidak berhenti pada kompetensi teknis dan administratif. Ia juga menuntut keadilan simbolik, keberlanjutan karier birokrasi, dan keberpihakan pada pengembangan kepemimpinan lokal. Tanpa dimensi ini, meritokrasi berisiko berubah menjadi teknokrasi kering: sah secara aturan, tetapi rapuh dalam kepercayaan publik.
Pada akhirnya, polemik Sekda impor bukan semata soal siapa yang terpilih. Namun bagi publik NTB, kebijakan dinilai dari pesan yang ditinggalkannya. Ketika SDM lokal tersedia, berpengalaman, dan teruji, maka pilihan terhadap figur luar akan selalu dibaca sebagai cermin arah kepercayaan kepemimpinan daerah. Di titik inilah kepemimpinan diuji, bukan hanya pada ketepatan administratif, tetapi pada kebijaksanaan merawat martabat birokrasi daerah dan menumbuhkan keyakinan kolektif bahwa NTB mampu berdiri dan maju dengan kekuatan anak daerahnya sendiri.***