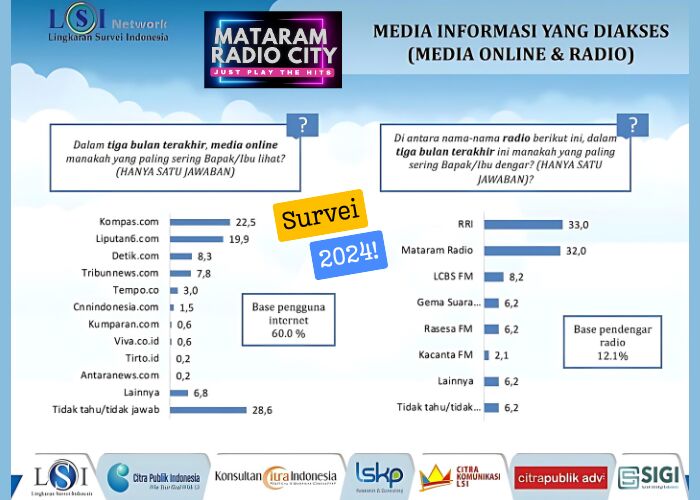Pertama saya ingin tegaskan bahwa saya berada di arus yang sama dengan gerakan rakyat di akhir agustus 2025 yang salah satunya dipicu oleh tingkah laku oknum wakil rakyat yang secara terang-terangan di luar batas melanggar etika kebangsaan.
Namun saya juga tidak dapat menerima anggota dewan dikorbankan oleh partai dengan mekanisme penonaktifkan. Karena hal ini bukan penyelesaian yang adil dan menjanjikan perbaikan.
Terkait peristiwa akhir Agustus 2025 memperkuat kritik terhadap praktik penonaktifan anggota dewan oleh partai. Gelombang protes nasional yang dipicu oleh tunjangan rumah anggota DPR sebesar 50 juta per bulan, diikuti insiden tragis tewasnya Affan Kurniawan oleh kendaraan taktis Brimob dalam aksi 28 Agustus, memicu kemarahan publik secara masif.


Dalam mengantisipasi gelombang kritik, Partai NasDem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Sementara PAN menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya.
Ikut serta juga Adies Kadir yang dinonaktifkan Golkar. Semua keputusan efektif per 1 September 2025. Kendati tindakan tersebut tampak responsif terhadap tekanan publik, sebenarnya langkah itu hanya menyoroti paradigma yang sama yakni penonaktifan individu sebagai alat mitigasi krisis citra partai.

Padahal, akar permasalahan yakni lemahnya sistem kaderisasi, ketiadaan transparansi terhadap tunjangan parlemen, dan ketiadaan badan etik independen masih tetap menganga. Dengan demikian, penonaktifan yang dilakukan tidak lebih dari simbolisme formal tanpa disertai reformasi substantif terhadap tata kelola politik dan mekanisme kontrol sipil yang hakiki.
Keputusan partai politik untuk menonaktifkan anggota dewan mereka yang terjerat kasus atau dianggap bermasalah, memunculkan pertanyaan serius tentang cara kerja sistem kepartaian di Indonesia.
Langkah ini tampak seperti upaya tegas, tetapi bila ditelaah lebih dalam, sesungguhnya hanya menyingkap wajah lama politik kita yang gemar mencari kambing hitam.
Masalah perilaku anggota dewan memang nyata dan tidak bisa dinafikan, tetapi menyelesaikannya dengan cara menyingkirkan individu justru mengaburkan akar persoalan yang bersifat struktural.
Sistem kepartaian yang rapuh, undang-undang yang belum memadai, serta lemahnya etika kelembagaan merupakan faktor mendasar yang harus dibenahi agar politik Indonesia tidak terus terjebak dalam sirkulasi krisis moral.
Penting ditegaskan sejak awal bahwa tingkah laku menyimpang anggota dewan tidak dapat dipisahkan dari proses kaderisasi partai. Ketika perilaku buruk oknum menjadi alasan partai bertindak, kita seolah diarahkan untuk melihat persoalan hanya dari sudut pandang personal.
Padahal, siapa yang mengusung, membiayai, dan melegitimasi seorang calon hingga menduduki kursi dewan kalau bukan partai itu sendiri? Proses rekrutmen politik yang lebih menekankan pada popularitas, kedekatan, dan kekuatan modal dibandingkan integritas moral dan kapasitas intelektual telah melahirkan banyak figur yang jauh dari standar etis.
Maka, jika anggota dewan berperilaku di luar batas, itu bukan hanya kegagalan individu, tetapi juga kegagalan institusional partai dalam membangun kader yang layak mewakili rakyat.
Tindakan menonaktifkan anggota dewan dapat terlihat seperti bentuk tanggung jawab moral partai, tetapi sesungguhnya langkah itu lebih menyerupai strategi penyelamatan citra.
Dengan mengorbankan individu, partai berupaya menegaskan bahwa mereka tegas menolak penyimpangan, walhal mekanisme internal yang memungkinkan terjadinya penyimpangan tersebut tidak pernah disentuh.
Fenomena ini mencerminkan gejala klasik politik kita yakni menutup luka dengan plester tanpa mengobati penyakit. Penonaktifan dijadikan perisai politik.
Bukan jalan menuju reformasi. Dalam kerangka ini, publik dihadapkan pada sandiwara moral di mana partai tampil sebagai pembersih. Padahal sesungguhnya mereka adalah bagian dari sumber masalah.
Kegagalan terbesar partai ketika menonaktifkan anggota dewan adalah hilangnya akuntabilitas kelembagaan. Anggota yang dinonaktifkan seolah menjadi beban pribadi, sementara partai bebas dari tuntutan pertanggungjawaban.
Padahal, rekam jejak calon legislatif tidak mungkin tidak diketahui partai sebelum dicalonkan. Keterlibatan partai dalam setiap langkah karier politik anggotanya sangat besar sehingga tidak adil bila ketika terjadi pelanggaran, seluruh kesalahan ditimpakan pada individu semata.
Dengan demikian, praktik penonaktifan justru menutup ruang bagi publik untuk menuntut tanggung jawab struktural partai yang seharusnya ikut memikul konsekuensi dari kegagalan sistemik partai politik.
Kebijakan ini juga menimbulkan implikasi serius terhadap demokrasi representatif. Jika seorang anggota dewan dinonaktifkan oleh partainya, apa artinya suara rakyat yang telah memilihnya? Logika demokrasi seharusnya menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Bukan di bawah kendali penuh partai.
Namun dalam praktik politik Indonesia, kedaulatan rakyat sering tereduksi menjadi kedaulatan partai. Penonaktifan bukan saja mengkhianati hak rakyat yang telah menitipkan suara, tetapi juga memperlihatkan betapa partai masih menempatkan diri sebagai pemilik kursi dewan. Bukan sebagai perantara kehendak masyarakat.
Menyelesaikan masalah ini tidak bisa dilakukan dengan pendekatan reaktif seperti penonaktifan. Solusi sejati harus bersifat sistemik melalui reformasi undang-undang partai politik yang jelas dan ketat.
Regulasi harus memuat mekanisme rekrutmen yang lebih transparan. Termasuk dengan kriteria etis yang dapat diukur secara objektif. Tidak boleh lagi ada kelonggaran yang memungkinkan orang dengan rekam jejak buruk melenggang menjadi calon legislatif hanya karena ia populer atau memiliki modal besar.
Partai harus diwajibkan membuka data rekam jejak calon mereka kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai secara langsung kualitas kandidat yang akan dipilih. Dengan cara ini, tanggung jawab moral partai tidak bisa lagi ditutupi dengan langkah formalitas seperti menonaktifkan anggota yang bermasalah.
Selain itu, perlu ditegakkan kode etik kelembagaan yang tidak hanya beroperasi di bawah kendali partai, tetapi juga berada dalam pengawasan lembaga independen. Dewan Kehormatan yang dibentuk partai sering kali tidak memiliki daya, karena keberadaan mereka subordinatif terhadap kepentingan politik.
Oleh karena itu, diperlukan badan etik nasional yang bersifat independen dan memiliki legitimasi hukum untuk menilai, mengawasi, serta memberikan sanksi terhadap perilaku anggota dewan. Dengan demikian, partai tidak lagi bisa memainkan peran tunggal dalam menentukan nasib anggota.
Sebab mekanisme kontrol eksternal akan memastikan bahwa akuntabilitas tetap terjaga dan tidak dimanipulasi.
Dalam konteks ini, partai juga harus diposisikan sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab apabila anggota dewan mereka terbukti melakukan pelanggaran berat.
Artinya, sanksi tidak hanya diberikan kepada individu, tetapi juga pada partai yang meloloskan individu tersebut. Konsekuensinya dapat berupa pengurangan dana bantuan partai, pencabutan hak mencalonkan dalam periode tertentu, atau bentuk hukuman politik lain yang bersifat korektif.
Dengan demikian, partai tidak bisa lagi berlindung di balik argumen bahwa pelanggaran adalah kesalahan pribadi. Pertanggungjawaban kolektif ini akan mendorong partai lebih berhati-hati dalam proses kaderisasi. Sebab risiko politik dan hukum yang ditanggung menjadi nyata.
Lebih jauh lagi, keterlibatan publik dalam proses politik harus diperkuat. Selama ini, publik hanya diberi ruang untuk memilih, tetapi tidak pernah benar-benar memiliki akses untuk mengetahui siapa calon yang akan dipilihnya secara transparan.
Reformasi politik harus membuka kanal informasi yang memungkinkan masyarakat menilai rekam jejak, integritas, dan kapasitas calon sebelum hari pemilihan.
Dengan cara ini, rakyat tidak lagi memilih dalam ruang gelap. Seterusnya partai tidak lagi memiliki monopoli atas informasi. Transparansi akan menjadi kunci agar demokrasi tidak terjebak dalam praktik kosmetik.
Jika kita biarkan praktik penonaktifan berlanjut tanpa koreksi sistemik, maka demokrasi Indonesia akan terus terjebak dalam sirkulasi masalah yang sama. Anggota dewan berganti, partai tetap bertahan, tetapi penyimpangan moral, lemahnya etika, runtuhnya simpati-empati, gelapnya kepekaan dan korupsi politik tidak pernah surut. Publik hanya disuguhi drama politik di mana partai tampil seolah-olah berbenah.
Padahal yang terjadi hanyalah pergantian aktor dalam panggung yang rusak. Kedaulatan rakyat semakin direduksi, partisipasi publik tetap dangkal, dan demokrasi kehilangan makna substantifnya.
Maka dari itu, respons kritis terhadap kebijakan partai menonaktifkan anggota dewan harus diarahkan pada desakan reformasi struktural.
Perubahan undang-undang partai politik, penguatan badan etik independen, penerapan sanksi kolektif kepada partai, serta keterlibatan publik dalam penilaian calon legislatif adalah langkah-langkah yang harus ditempuh agar sistem demokrasi lebih akuntabel.
Sekali lagi, penonaktifan hanyalah jalan pintas yang menyesatkan. Sebab selamanya tidak menyelesaikan akar masalah. Malahan hanya memperindah wajah partai untuk sementara waktu.
Dengan begitu, mereka yang dinonaktifkan (termasuk yang terkini ialah Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, Uya Kuya, Adies Kadir) bukan jalan penyelesaian yang adil dan menjanjikan kekuatan sistem partai politik dan politik itu sendiri di masa depan.
Karena itu, partai politik tidak boleh lagi bersembunyi di balik penonaktifan anggota dewan. Tanggung jawab sejati terletak pada reformasi menyeluruh terhadap sistem kepartaian dan undang-undang yang mengaturnya.
Selama akar masalah ini tidak disentuh, demokrasi Indonesia akan terus menjadi panggung sandiwara, di mana rakyat hanya berperan sebagai penonton yang kecewa.
Malaysia, 1 September 2025