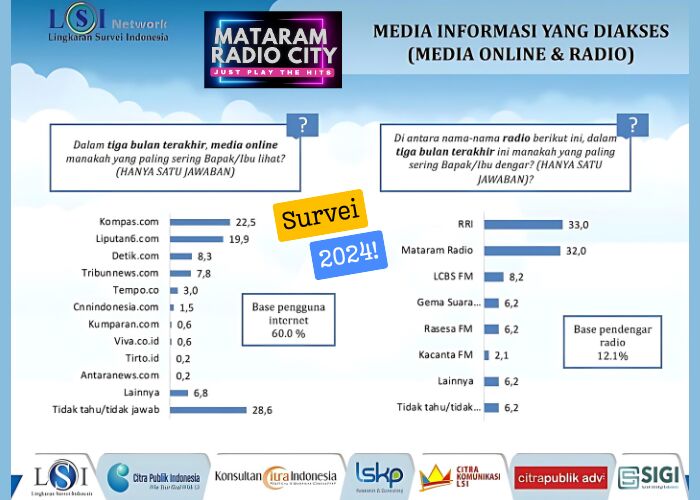Malam itu di Pantai Saliper Ate, Sumbawa, obrolan mengalir sehabis menyantap hidangan sepat yang begitu istimewa.

Hadir beberapa sahabat: seorang tokoh ormas, birokrat kabupaten, dan praktisi kebudayaan. Angin laut tenang. Percakapan bergerak ke mana-mana.
Ketika topik bergeser ke madu, seorang kawan tiba-tiba memotong, “Istri saya tidak suka dibawakan madu.”


Ia melanjutkan, “Bukan cuma tidak suka. Dia benci sekali.”
Kami terdiam sesaat, lalu tertawa hampir bersamaan. Yang dimaksud bukan madu hutan—salah satu komoditas populer Tana Samawa—melainkan status sosial yang paling ditakuti banyak perempuan: dimadu.
Di Sumbawa, madu bukan sekadar cairan manis. Madu menyimpan ingatan tentang hutan. Sumbernya bergantung pada Apis dorsata, lebah hutan liar yang bersarang di tajuk pohon tinggi dan tidak bisa diternakkan.
Sarang-sarang hitam menggantung di perbukitan dan tepi hutan, menunggu musim bunga. Rasa madu kuat, aromanya tajam, warnanya berubah mengikuti lingkungan dan waktu panen.
Di masa lalu, menyebut Sumbawa, itu identik dengan madu.
Panen madu tidak dilakukan sembarangan. Ada aturan tradisi, waktu yang harus ditunggu, dan sarang yang dilarang diambil. Para pemanjat memahami konsekuensinya: ketika keserakahan mengambil alih dan aturan dilanggar, musim berikutnya bisa kosong. Panen menjadi sumber nafkah sekaligus latihan menahan diri.
Perubahan datang. Madu hutan masuk ke ruang pameran dan laboratorium. Botol-botol berlabel “organik”, “liar”, dan “premium” tersusun rapi di stan-stan pameran.
Sejumlah penelitian di perguruan tinggi Nusa Tenggara Barat menguji madu hutan Sumbawa dan menemukan aktivitas antibakteri terhadap beberapa bakteri, juga kandungan antioksidan yang signifikan. Dalam istilah ilmiah, madu berperan sebagai antibakteri alami, humektan pada luka, dan sumber senyawa fenolik.
Temuan tersebut memberi kerangka ilmiah pada praktik lama komunitas setempat: madu untuk luka bakar ringan, sayatan, dan gangguan tenggorokan.
Namun penelitian yang sama menegaskan satu catatan penting: kualitas madu sangat bervariasi. Musim panen, ketinggian lokasi, komposisi flora berbunga—sebagai sumber nektar dan serbuk sari lebah, serta cara penyimpanan menentukan hasil uji. Tanpa standar pengambilan sampel, klaim kesehatan mudah melebar.
Sementara itu, kondisi hutan bergerak ke arah berlawanan.
Data pengelolaan kehutanan menunjukkan produksi madu hutan di beberapa unit KPH di Sumbawa kini hanya ratusan liter per tahun—sekitar 500 liter pada unit tertentu.
Angka tersebut tergolong kecil untuk wilayah dengan bentang hutan luas. Produksi bersifat musiman dan terputus. Pembukaan lahan, kebakaran, dan panen berlebihan membuat sarang sering ditinggalkan.
Ketika pohon hilang, lebah berpindah. Ketika panen dipercepat demi pasar, regenerasi gagal.
Saya teringat cerita seorang kawan yang tinggal di Jakarta. “Di sini, kalau ditotal, madu Sumbawa yang dijajakan volumenya bisa berbarel-barel,” selorohnya.
Dari mana memperoleh madu Sumbawa sebanyak itu?
Yang berkurang bukan hanya volume madu, tetapi juga pengetahuan tentang jeda perburuan.
Madu hutan Sumbawa kini dikelilingi klaim. Wacana “naik kelas” kerap berhenti pada kemasan dan harga, jarang menyentuh fondasi. Hubungannya sederhana: tanpa hutan, tidak ada madu; tanpa tata panen yang disiplin, tidak ada musim berikutnya.
Keberlanjutan madu menuntut langkah yang terukur. Ini meliputi standar riset dan mutu agar klaim kesehatan dapat diuji ulang. Dan yang tak kalah penting rantai nilai yang memberi manfaat langsung bagi pemanjat dan komunitas hutan, serta perlindungan habitat Apis dorsata melalui pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
Malam di pantai itu berakhir dengan tawa dan suara ombak. Diskusi tentang madu berhenti. Tapi persoalan tentang keberlangsungan produksi madu Sumbawa tentu belum berakhir.