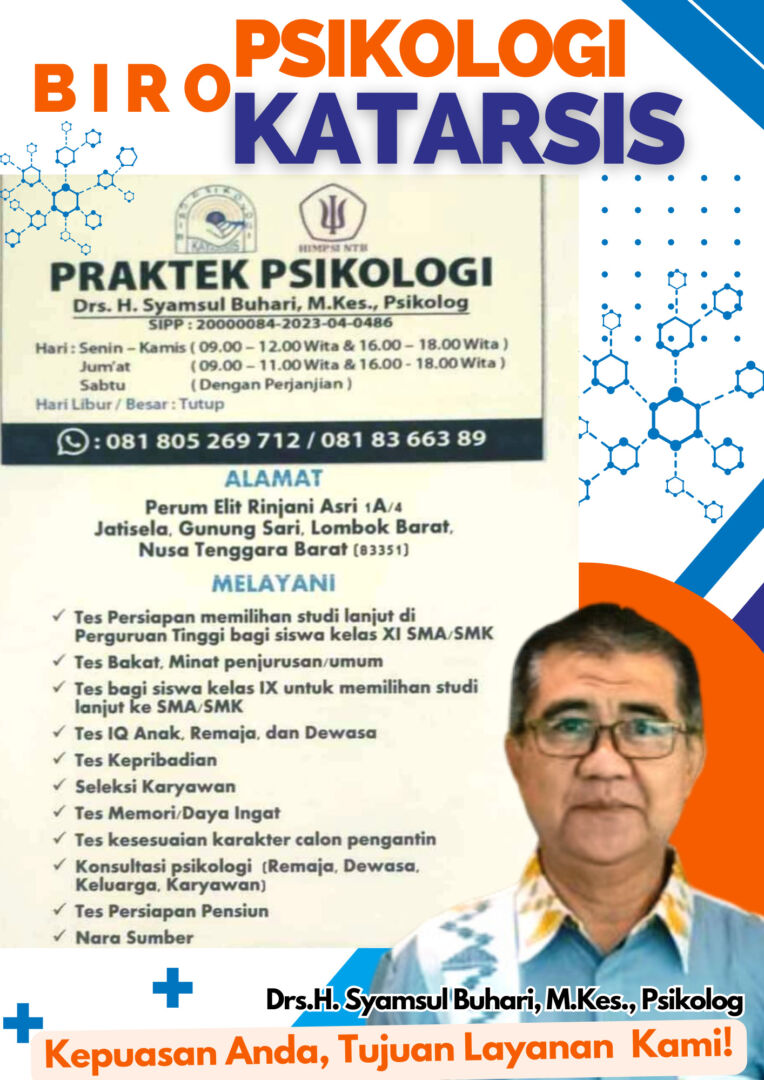“Jangan kalahkan rasa malu oleh mau sebab setitik rasa malu yang hilang dapat memusnahkan segalanya “(Amak Kesek)
Meski Yudi Latif benar dan saya sangat setuju, namun ia terlalu jauh mengambil cerminan hanya untuk mencerminkan para pemimpin di Indonesia. Boleh jadi, sebagian besar pemimpin di Indonesia juga tidak mengenal George Washington apalagi mendalami warisan etis kompas kepemimpinan yang dipegang Amerika Serikat hingga kini. Meski mereka mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk mengubah undang-undang, namun boleh jadi sampai kapan pun hal itu tidak akan dilakukan sebab kompas etis kepemimpinan yang diwariskan tersebut diletakkan lebih tinggi di atas undang-undang. Begitulah garisan pesan tulisan Yudi Latif yang berjudul “Kompas Etis Kepemimpinan”.
Sekali lagi, iktibar ini cukup jauh (apalagi untuk menjadi cerminan pemimpin yang berhati buta) karena sebenarnya ada yang lebih dekat, bahkan tidak berjarak dengan diri kita, yakni rasa malu.



Rasa malu ialah diri. Ia juga nature sekaligus nurture. Ia ada dalam diri manusia sejak berlaku persetujuan dan perjanjian dengan Tuhan. Karena keadilan, Tuhan meletakkan kadar rasa malu yang sama pada diri manusia. Namun besar kecil dan kualitas kadar itu juga ditentukan oleh perjuangan manusia untuk mengolah rasa malu tersebut sebagai aset diri yang paling tinggi. Rasa malu dibentuk secara sadar dan ditempa oleh lingkungan. Ia diasah di tengah-tengah kemauan yang juga nature. Dalam masa pengasahan itulah kadar rasa malu diuji, adakah ia akan menjadi perisai yang melindungi atau malah sebaliknya, menjadi stimulus dan penyuplai untuk kemauan yang akhirnya mendominasi rasa malu itu sendiri.
Begitu dekatnya rasa malu dengan diri kita, untuk menggambarkan kedudukan dan kedekatan rasa malu tersebut, nabi Muhammad SAW seperti yang diwartakan oleh Buhkari Muslim yang, rasa malu ialah bagian dari iman. Kepercayaan ialah keperluan, bukan hanya kewajiban. Dan suplemen besar iman ialah rasa malu. Dalam pendekatan lain dapat dikatakan ukuran manusia layak dan tidak layak, jika iman tak dapat menggambarkannya, maka temukanlah dalam rasa malu. Begitu kita menemukan rasa malu masih ada dalam diri kita, maka itu menunjukkan yang, kita masih mempunyai kepercayaan. Tegasnya, kita tak akan pernah menemukan rasa malu di dalam kemauan.
Sebagai contoh, kebanyakan dari kita memilih pekerjaan karena kita memerlukan pekerjaan tersebut. Kita terdesak karena harus bekerja dan punya pekerjaan. Karena pekerjaan tersebut menjanjikan sesuatu yang menarik maka kita meletakkan keperluan sebagai yang dominan. Dalam situasi ini, kita pasti melupakan rasa malu. Menanyakan diri kita, adakah kita mampu melaksanakan perkerjaan tersebut? Adakah pekerjaan tersebut sesuai dengan bidang saya? Adakah pekerjaan tersebut dapat menjadi ladang kebaikan dan pengabdian sebesar-besarnya untuk manusia yang lain? Ini ialah pertanyaan yang mencirikan sedang terjadi proses internalisasi dan negosiasi antara kemauan dan rasa malu. Hasilnya, kebanyakan dari kita telah didominasi oleh kemauan.
Akibatnya, banyak pemimpin di Indonesia, baik eksekutif maupun legislatif tak nyambung antara casing dengan merek diri kita. Kita sejak kecil bercita-cita jadi guru dan untuk itu sejak Sekolah Dasar kita konsen mempelajari keguruan hingga tamat strata satu. Namun tiba-tiba kita jadi bupati atau wakil rakyat. Kedua jabatan ini ialah casing yang menutupi keaslian diri kita yang berimajinasi menjadi guru. Maka yang terjadi ialah kita gagal menjadi guru sekaligus gagal menjalankan amanah sebagai bupati atau anggota dewan. Malah kita menjadi koruptor atau pemeran berwatak jahat untuk rakyat. Ini lucu, kan? Namun ada yang paling lucu, artis mendadak dewan. Namun kita tak pernah tertawakan kelucuan ini. Kenapa? Karena kita sakit. Rasa malu yang semakin tergerus menunjukkan kita sakit.
Oiya, atau kita sedang menjalankan undang-undang yang membolehkan siapa saja menjadi apa saja atas nama demokrasi? Kita susah membedakan kedua situasi tersebut, bukan? Sekali lagi itu karena miskinnya rasa malu dalam dada kita. Dalam dada Indonesia.
Rupanya, fenomena itulah yang telah menggurat Indonesia. Banyak orang yang bertarung habis-habisan untuk mencapai cita-citanya, namun karena kesempatan yang ada hanya menjadi bupati, maka jadilah kita bupati yang, sayangnya aimless: Bupati yang hingga masuk tahun ketiga jabatan masih belum menemukan irama dan tujuan yang pasti. Maka jadilah kita anggota dewan yang hanya datang mengisi daftar hadir dan duduk termenung dalam ruang sidang.
Itulah sebabnya Tuhan meletakkan rasa malu sebagai nature dan nurture sekaligus. Agar ada dinamisasi yang harmonis antara kemauan dan rasa malu. Hanya saja, sayangnya rasa malu amat susah diukur. Orang yang telanjang di Gili Trawangan, entah kenapa kita begitu susah menyebutnya sebagai tidak punya rasa malu namun diketahui orang lain tidak punya uang, tidak punya jabatan, tidak punya kendaraan begitu terasa dan nampak sebagai rasa malu. Orang yang mengambil uang rakyat begitu rumit kita ukur dengan kaca mata rasa malu, namun tidak pakai baju bagus, tidak punya pulsa, kuota lemah begitu mudahnya nampak sebagai rasa malu.
Situasi tersebut, lacurnya lama-lama menjadi habit dalam bawah sadar kita yang seterusnya mengontsruksi perilaku kita untuk membentuk tradisi pengaburan. Maka kita pun tak ada norma, tak ada etika, tak ada dacin ukuran untuk menilai apakah orang yang mewacanakan presiden tiga periode dan jelas-jelas melenceng dari undang-undang untuk menyatakan yang, mereka tidak punya rasa malu. Karena kita kehilangan standar itu, maka pelencengan undang-undang tersebut seolah-olah berterima menjadi tradisi yang kedudukannya lebih tinggi dari undang-undang.
Begitu suramnya standar rasa malu itu, kita pun tak ada koreksi ketika, misalnya, seorang calon pemimpin semasa kontestasi menjadi presiden mengatakan begini, “Indonesia itu negara besar”. Kita selesai hanya pada pernyatan tersebut. Tidak meneruskannya kepada pernyataan yang sebenarnya “Karena itu diperlukan pemimpin yang besar”. Karena kita tidak mendorong pernyataan lanjutan dari pernyataan pertama, maka momen menguji kadar kemauan dan rasa malu calon pemimpin kita lupakan. Kita tenggelam ke dalam pesta kemauan yang membabibuta dibungkus pesta demokrasi yang sejatinya juga buta.
Lihat saja, bagaimana calon presiden tersebut menyakatan yang, “Indonesia itu negara besar” namun dia tidak mengukur pernyataan tersebut dengan kemampuan dirinya. Mempertanyakan relevansi komparatif antara negara Indonesia yang besar dengan kemampuan dirinya. Adakah saya mampu? Adakah kemampuan saya memang benar-benar menjadi presiden untuk sebuah negara besar bernama Indonesia? Ataukah ini hanya dominasi kemauan yang dikondisikan oleh pendukung buta dan partai lintah darat?
Kalau melihat apa yang dihasilkan oleh apa yang kita sebut pesta demokrasi itu, sungguh, sang calon pemimpin yang kemudian menang, misalnya, benar-benar tidak pernah bertanya kepada dirinya menggunakan kadar rasa malu yang ada pada dirinya. Kalau pernah, mungkin pesta demokrasi tersebut akan menghasilkan cerita yang lain.
Hal yang sama, misalnya, ketika sekelompok orang ramai-ramai menggerus kemauan agar jabatan presiden diubah tiga periode. Seperti yang disinggung Yudi Latif, meski ada ruang legal untuk mengubah undang-undang tersebut, namun jika sekelompok orang itu atau orang yang digadang-gadang masih menitikberatkan kualitas diri pada rasa malu, maka sekecil apa pun riak gelombang wacana ini, tidak akan pernah dibiarkan apalagi sengaja dibuat terjadi.
Sebagai pemimpin yang punya rasa malu, jangankan membiarkan sekelompok orang menyuarakan dan menggerakkan pelencengan undang-undang, terbersit untuk menjabat tiga peroide dalam hati pun tidak akan pernah. Jika rasa malu masih sedikit saja menghiasi lembing-lembing kepercayaan dalam dada, pemimpin tersebut tidak akan mendiamkan saja pelencengan tersebut bergerak liar. Ia akan menindak tegas bahkan memenjarakan sekelompok orang tersebut. Sebab secara hakikat, mereka boleh jadi lebih makar dari kemakaran yang lain.
Namun begitulah, seumpama dongeng, begitulah Indonesia, kebahagiaan bukan kenyataan ia hanya mimpi. Disebabkan rasa malu yang sudah terkikis, kita dengan legowo menerima seseorang yang dahulu bertarung untuk mendapatkan kekuasaan, tiba-tiba menerima kekuasaan dari orang yang mengalahkannya hanya karena alasan mengabdi kepada negara. Lacurnya lagi, kita tak pernah membayangkan yang, kebiasaan tersebut dapat merusak demokrasi yang Indonesia agungkan itu. Kekuasaan yang tidak ada lawan ialah kehancuran negara paling besar.
Orang yang masih punya rasa malu pasti berkata, “Persahabatan itu wajib sebagaimana wajibnya mengabdi kepada negara, namun karena saya harus merawat rasa malu sebagai pusat harga diri saya, pengabdian kepada negara akan saya lakukan di jalur yang lain.”
Hanya saja, begitulah kita, meskipun yang kita harapkan masih punya rasa malu ikut berkuasa juga, dan kita terima ia sebagai satu kebiasaan, jangan-jangan kita semua saja. Sudah tidak punya rasa malu.
Maka, jangan heran segala hal dapat terjadi di negara yang penduduknya sudah kehilangan rasa malu. Sebab setitik rasa malu yang hilang dapat menghilangakan segala hal tentang Indonesia.
Apa yang mau diharapkan pada negara yang sudah tidak punya rasa malu, hah?!
Malaysia, pertengahan Zulqaidah 1442 H.