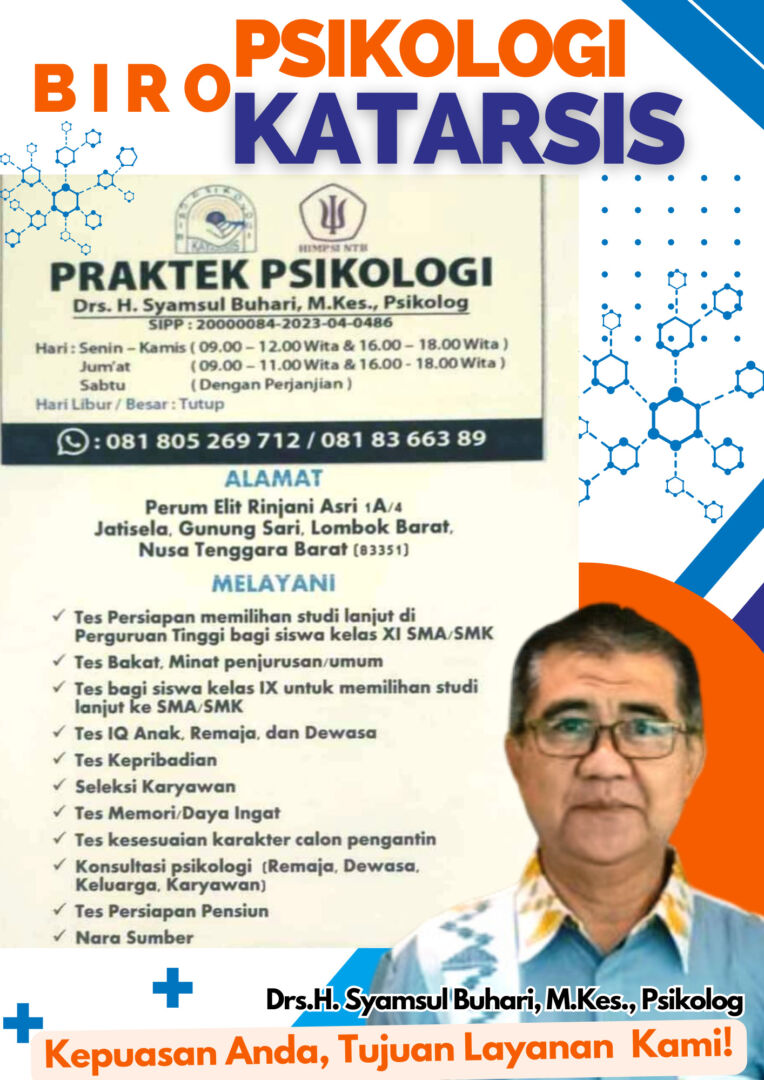Oleh: DR Salman Faris
Sekitar enam atau tujuh tahun yang lalu saya melauncing semacam gerakan yang saya namakan KAJAKU (Kaya, Jahat, dan Kuasa). Banyak respons dari kalangan teman-teman yang kebanyakannya menilai gerakan tersebut sesat dan lemah secara ontologis dan belum jelas epistemologinya. Sekasat mata memang gerakan ini nampak menjadi anti tesis terhadap gerakan kebaikan, gerakan mulia, gerakan putih manusia kebanyakan. Bahkan jika disandingkan dengan gerakan yang pura-pura baik, gerakan yang memanipulasi kemuliaan dan mensimulakra putih pun, gerakan ini masih nampak kontradiktif. Namun jika ingin memahaminya secara sederhana, dapatlah dikatakan bahwa untuk menunjukkan perjuangan kebaikan alias perjuangan yang legal pun, sebenarnya KAJAKU ini amat diperlukan. Mendirikan sebuah partai politik yang berasaskan Pancasila dan melahirkan Ormas yang harus mengacu, juga, Pancasila, KAJAKU ini amat penting posisinya.


Selebihnya, banyak teman-teman yang berseloroh sambil mencandai yang gerakan ini lahir dari kebosanan yang amat puncak terhadap kondisi kemiskinan, ketiadaan, dan kekalahan yang saya alami. Saya menerima seloroh ini dengan senang hati bin berlapang dada karena secara fenomonelogis, gerakan ini memang empirikal. Sebagai orang yang pernah sedikit belajar, saya memahami yang bahkan filsafat pun lahir untuk memecahkan keadaan yang bersifat empirikal. Sains juga demikian, berangkat dari adanya keadaan yang dirumuskan dalam satuan pengetahuan untuk memecahkan fenomena yang ada di dalam adanya keadaan tersebut. Dengan begitu, ialah lumrah jika saya terdorong untuk memecahkan kemiskinan menurun-menaik, kekalahan mendarah basah, dan ketiadaan yang mendera-dera. Bagi siapa saja yang mengalami hal serupa, pasti dapat menangkap situasi rahim dan kebatinan gerakan KAJAKU ini.
Semakin sengit di ranah wacana teman-teman karena ambivalensi, ambiguitas, kontradiksi, bahkan absurditas terjadi secara nyata di depan mata. Dialami oleh saya dan kebanyakan teman-teman. Berada di lingkungan kekuasaan, bernapas bersama penguasa, berdendang berayun bersama mereka yang menakhodai kejahatan namun tak tercederai sebagai orang jahat di lingkungan sosial tidak serta merta mengubah keadaan kemiskinan, ketiadaan, dan kekalahan tersebut semakin baik. Kasarannya, nasib tak berubah. Hanya nampak solah tanduran gunung, manis di mata namun amat menyakitkan dalam realitas yang dirasakan.
Gerakan KAJAKU belum mempunyai rumusan atau bangunan saintifik yang kukuh hingga sekarang. Saya harus mengakui itu, terutama karena tidak ada kesempatan untuk membuktikan gerakan ini sebagi sebuah teori yang sahih atau metode yang jitu dalam mengubah nasib sial manusia. Namun saya selalu berusaha menyederhanakannya, sekali lagi, dengan menggunakan pendekatan fenomonelogis yang meminjam Edmund Husserl (1859-1938) secara permukaan sebagai suatu pengalaman subjektif atau fenomenologikal yang diasaskan pada studi tentang kesadaran perspektif inti seseorang dan kolektif. Selain itu secara amat sederhana memakai Martin Heidegger yang melihat kesadaran tumbuh berkecembah dari samudera kesadaran dunia dan manusia nyata. Sekali lagi atas dasar analisis deskriptif dan introspektif dari pintu kedua tokoh tersebut saya berupaya mensimplikasikan gerakan KAJAKU dengan menyandingkannya secara tidak setara antara nasib saya dan teman-teman dengan fatamorgana dan panorama realitas.
Kerlap kerlip dan tebaran aroma parfum di Lombok Epicentrum Mall (LEM) tidak dapat dinikmati sebagai kenyataan kemajuan yang diklaim oleh cukong dan politisi tanpa kekayaan. Karena kita berpunya kelengkapan, maka kita pun mendefinisikan dan memungsikan LEM sebagai kemajuan atau penggambaran peradaban maju atau kemakmuran ekonomi. Karena kita memiliki perangkat operasional yang kuat, maka LEM tiba-tiba menjadi tempat yang membahagiakan, menggembirakan dan sebagai pusat bersosialisasi. Namun jika kita bernasib sebaliknya, maka LEM hanya mimipi. Hanya sumber aliran elor alias liur pahit, LEM tak lebih dari sebuah panorama keindahan puncak gunung yang hanya bisa dinikmati dari kejauhan. LEM lebih kurang sebagai scenery dari alam tahayyul. Jadi, LEM ialah sumber kesetaraan manusia dengan kemajuan jika kekayaan sebagai penyertanya. Akan tetapi LEM sebagai sumber penderitaan jika kita sebagai orang miskin, tiada, dan kalah.
Hal yang sama pasti berlaku jika kemiskinan, kekalahan, dan ketiadaan masih melekat ketika KEK Mandalika sudah benar-benar menjadi tangki penyimpanan bagi orang kaya dan sumber kerukan buldoser bagi mereka yang berpunya. Saya dan teman-teman yang miskin itu, pasti hanya dapat menyungging senyum hasrat tinggi yang tak kesampaian. Bagai jauh pantai dari lautan. Maka dalam situasi apa yang diperjuangkan manusia kaya yakni kemajuan yang menyediakan segala lepahan hasrat, kekayaan amat diperlukan. Mutlak diperlukan.
Pada sisi yang lain, teman-teman diperas otak mereka yang cemerlang itu untuk berkontribusi dalam apa yang disebut pemerintah sebagai pembangunan dan investasi dalam panggilan orang kaya. Karena mereka dekat dengan kekuasaan, teman-teman dapat berdiskusi, meluahkan gagasan hebat. Kemudian diaplikasikan sebagai rancang bangun yang amat jitu oleh mereka yang kaya dan berkuasa sedangkan teman-teman tidak memperoleh apa pun jua. Bahkan menjadi penggembira pun tidak. Hanya sesekali ditraktir makan di Rumah Makan Taliwang atau diundang sebagai tamu biasa saja ke kediaman orang kaya dan para penguasa. Sementara di luar, pada mulut dan pikiran masyarakat, teman-teman dikenali sebagai ring satu dalam segala hal, yakni dapat mengakses ekonomi dan kebijakan dengan mudah. Ini menambah pahit nasib teman-teman: orang ring satu masih naik ojek atau kehujanan. Sementara kalau Idul Fitri tiba, kepala pecah memikirkan uang untuk sewa mobil dan sedikit hol untuk dibagi kepada masyarakat atau keluarga yang sudah kadung menilai mereka ring satu: orang hebat. Orang kaya. Orang berkuasa. Alias orang sukses.
Amat naif memang. Di tengah-tengah banyak teman yang hebat itu, berdiri necis pemimpin yang kadang hanya karena dia mempunyai uang lebih untuk membayar partai dan kampanye, dia bisa menjadi pemimpin. Padahal amat lemah kemampuan sebagai pemimpin. Tak pandai mengonstruksi gagasan, pemikiran dan amat doif dalam membuat keputusan. Yang sedikit terhormat sebatas karena dia hobi (bukan hebat) berpartai, ditambah kelebihan uang, maka jadilah dia pemimpin. Memang sangat absurd, teman-teman yang hebat itu dikelilingi oleh beberapa legislator berotak tumpul namun hanya karena menurunkan kuasa dari papuk balok alias nenek moyang mereka, nasib baik sebagai pengawal legislatif jatuh kepada mereka. Kemudian teman-teman ini menyuplai gagasan dan pemikiran hebat untuk dieksekusi oleh beberapa barisan berkepala tumpul. Miris memang, teman-teman menjadi centeng beberapa eselon dua yang hanya pandai duduk di kursi, namun nihil inisiatif. Apalagi gagasan. Satu-satunya ide mereka ialah merumuskan anggaran untuk mengganti mobil dinas dan merenovasi ruang kerja. Mereka benar-benar menduduki jabatan hanya karena sarat kepangkatan sudah memenuhi. Selebihnya mantera songel. Dalam pasal ini,KAJAKU menegaskan bahwa teman-teman saya yang hebat itu perlukan kekuasaan. Dengan sudut lain, kekuasaan memerlukan orang-orang mumpuni secara intelektualitas dan spiritualitas agar ranah strategis ini tidak disesaki oleh manusia kosong bermodal kepeng dan nama papuk balok.
Untuk Kekayaan dan Kekuasaan ini, teman-teman tidak memperpanjang polemik gerakan KAJAKU. Mereka sadar, kedua hal tersebut diperlukan. Mutlak. Terutama teman-teman yang gagal nyaleg atau gagal jadi bupati dan walikota hanya karena kalah uang dengan pesaing. Yang hingga kini masih menjadi perdebatan ialah rancang bangun teoretis jahat. Saya sendiri tidak mau memaknakan jahat ini sebagi premanisme, brutalisme, nihil moral penuh asusila. Dalam konteks ini, saya sama sekali tidak menyandingkan Jahat dalam KAJAKU dengan Niccolo Machiavelli yang secara tegas manjauhkan asas susila dengan asas negara yang dapat dimaknakan sebagai kekuasaan yang mengharamkan asas moral, asas susila, agama, dan budaya. Jahat dalam KAJAKU juga tak saya maknai sebagai negara yang memperoleh kekuasaan lalu mengumpulkannya secara besar dan absolut sehingga penguasa dapat melakukan kejahatan penindasan kepada rakyat demi kepentingan kekuasaan sebagaimana teori Niccolo Machiavelli (pemikir kelahiran Florence, Italia pada tahun 1469).
Dengan begitu saya pun menyederhanakan Jahat itu lebih kepada mentalitas teman-teman yang terlalu lugu, polos, bongoh, jamak-jamak untuk bermetamorfosis menjadi orang hebat yang bermental “Wani Piro”. Boleh juga didekatkan kepada mentalitas “Anda Jual, Saya Beli”. Dengan kata lain, teman-teman harus berani membuat margin tarif atas semua gagasan, pemikiran, ide, kreativitas, dan kerja keras yang dikongsikan kepada penguasa yang berkuasa karena kaya atau kepada mereka yang kaya disebabkan berkuasa. Teman-teman harus menciptakan strategi agar eselon dua yang berotak tumpul itu secara sadar menarifkan pemikiran karena mereka tak mampu berfikir. Secara sederhana, Jahat yang saya maksudkan dalam KAJAKU ialah keberanian teman-teman untuk mematerialkan pemikiran kepada legislator yang kebetulan bernasib baik bukan berkemampuan mumpuni.
Lantas kenapa saya senang? Tentu saja saya amat gembira ketika mengetahui teman-teman yang dulu mencandakan KAJAKU itu sekarang sudah mulai menjadi subjek dalam remah-remah kuasa. Mereka terlibat dalam pengadaan, meskipun masih selevel sedang, di pemerintahan. Mereka sedikit terbuka dalam membicarakan pampasan dengan eselon dua yang tanpa mereka, mungkin sang birokrat tak jadi siapa-siapa di birokrasi. Saya amat berbahagia, mengetahui teman-teman sudah bermental kalkulator, yang berhitung pendapatan setelah mengeluarkan berlembar-lembar pendapat yang bermutu. Mengetahui mereka berani menjdi ketua partai politik setelah bosan menjdi anak buah ketua yang tak berkelas, sungguh menghilangkan dahaga saya.
Pertanyaannya, apakah teman-teman yang sudah teruji dan terbukti integritas dan kemampuan itu memiliki stamina serta kekuatan yang cukup bertarung di arena yang semua orang ingin tempil sebagai pemenang itu? Jika ya, sungguh inilah era yang ditunggu itu: Enyahnya kemiskinan. Terkaparnya ketiadaan. Terkuburnya kekalahan.
Malaysia, 20/06/2020

DR Salman Faris
adalah Akademisi, Praktisi Seni Budaya, Pemerhati Sosial Budaya dan Media. Kini tinggal di Kuala Lumpur Malaysia.